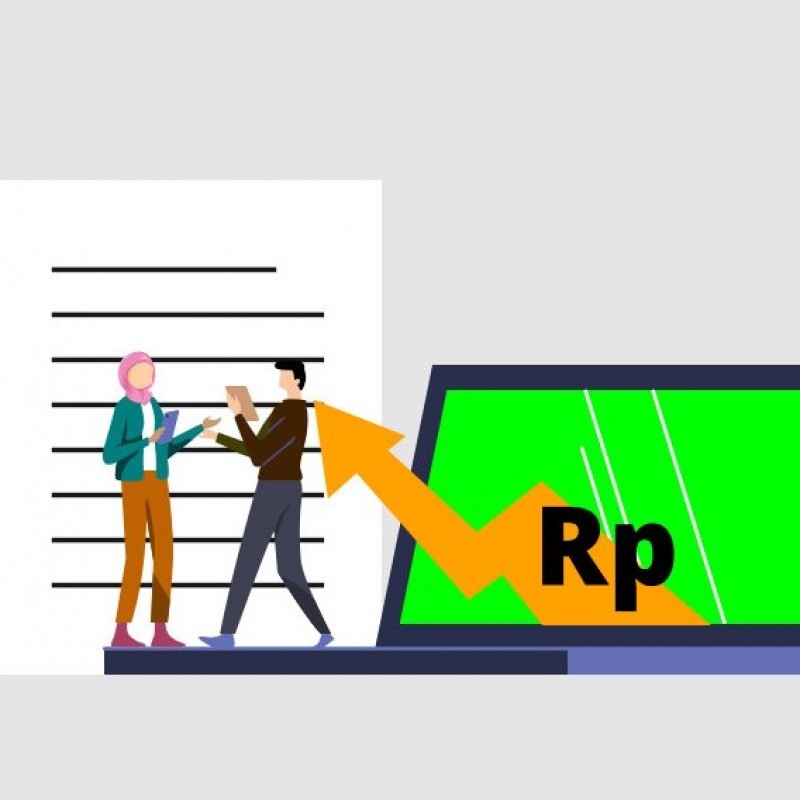Yang disebut untung dalam mengelola modal - secara matematis - adalah bilamana hasil yang diperoleh dari menjalankan usaha adalah lebih besar dibanding dengan modal dan biaya pengelolaan yang dikeluarkan. Bila nilai modal dan biaya pengelolaan ini justru berbanding terbalik dari hasil maka hal semacam ini disebut merugi.
Berangkat dari sini maka jelas sudah bahwa yang dibagi dalam akad permodalan (mudharabah/qiradh) adalah hasil usaha yang diperoleh dari selisih hasil jual barang setelah dikelola dibandingkan dengan harga asalnya. Untuk itu pula maka berlaku ketentuan bahwa “harga asal” barang, sebagai yang wajib diketahui oleh kedua pihak (pengelola dan pemodal).
Berbekal pengetahuan dasar di atas, kita bisa menghukumi praktik paron sapi yang berlaku di beberapa wilayah. Praktik itu umumnya dilaksanakan dengan jalan seseorang (pemodal) menyerahkan seekor sapi agar dirawat oleh petani (pengelola), kemudian dengan hasil bagi keuntungan berupa anak sapi yang harganya dibagi dua antara pihak yang merawat dan pemilik modal. Praktik seperti ini merupakan sebuah bentuk akad mudharabah yang rusak disebabkan karena ketidakjelasan (jahalah) nilai modal dan keuntungan yang hendak dibagi sehingga memungkinkan timbulnya gharar (penipuan) yang berakibat merugikan kepada pihak pengelola (petani). Lain halnya bila akad tersebut dilaksanakan sebagai berikut:
“Pemodal menyerahkan seekor sapi betina dengan harga 10 juta yang dibeli bersama-sama. Kemudian setelah dirawat selama 2 tahun, sapi betina ini menghasilkan anak. Keharusan tata cara pembagian hasil menurut akad mudharabah adalah berlaku sebagai berikut:
1. Sapi betina tersebut dijual, dan modal pokoknya diambil oleh pemilik modal. Selisih dari harga jual dengan modal, wajib dibagi berdua antara pemodal dan petani yang merawat.
2. Anak sapi yang lahir setelah perawatan induknya selama dua tahun itu juga mutlak harus dijual, kemudian harganya langsung dibagi berdua antara pihak pemodal dengan petani yang merawat.”
Kedua item ini merupakan solusi bagi hasil akad mudharabah ternak antara pemodal dan perawat, bila modal tersebut harus berupa ‘urudl. Namun, solusi ini seringkali menemui hambatan pelaksanaannya mengingat akad muamalah ini sudah mendarah daging di beberapa wilayah negeri kita tercinta ini. Sebenarnya kasus yang sama juga tidak hanya terjadi di zaman sekarang. Bahkan, sejak masa para ulama mazhab pun hal yang sama juga sering terjadi. Untuk itu, perlu langkah antisipatif maka tidak heran bila kemudian kalangan Malikiyah dan Syafiiyah serta jumhur (mayoritas) ulama Amshar mengeluarkan pernyataan dicegahnya penggunaan ‘urudl (barang materiel) ini sebagai modal.
Mayoritas ulama sepakat bahwa modal harus bisa dinyatakan dalam bentuk angka riil. Yang membolehkan ‘urudl sebagai modal adalah Abu Laila. Untuk Abu Hanifah, ada catatan kebolehan pemakaian “barang materiel” sebagai modal, dengan catatan jika dijual dulu. Sebagaimana ini diulas oleh Ibnu Rusyd dalam kitabnya, yaitu Bidayatu al-Mujtahid.
وَأَمَّا مَحِلُّهُ: فَإِنَّهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ جَائِزٌ بِالدَّنَانِيرِ وَالدَّرَاهِمِ، وَاخْتَلَفُوا فِي الْعُرُوضِ فَجُمْهُورُ فُقَهَاءِ الْأَمْصَارِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ الْقِرَاضُ بِالْعُرُوضِ، وَجَوَّزَهُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى.
Artinya: “Sifat modal. Hal yang disepakati oleh para fuqaha’ dalam soal modal adalah boleh bila disampaikan dalam bentuk dinar atau dirham. Adapun bila disampaikan dalam bentuk ‘urudl, maka para ulama berselisih pendapat. Jumhur ulama Amshar menyatakan tidak boleh suatu modal disampaikan dalam bentuk ‘urudl (modal barang), namun tidak dengan Abu Laila, beliau membolehkan” (Ibnu Rusyd al-Andalusy, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
Terkait dengan illat yang menyebabkan ketidakbolehan menggunakan barang/obyek materiel sebagai modal, Ibn Rusyd menyampaikan:
أَنَّ رَأْسَ الْمَالِ إِذَا كَانَ عُرُوضًا كَانَ غَرَرًا; لِأَنَّهُ يَقْبِضُ الْعَرَضَ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً مَا، وَيَرُدُّهُ وَهُوَ يُسَاوِي قِيمَةً غَيْرَهَا، فَيَكُونُ رَأْسُ الْمَالِ وَالرِّبْحُ مَجْهُولًا وَأَمَّا إِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَالِ مَا بِهِ يُبَاعُ الْعُرُوضُ، فَإِنَّ مَالِكًا مَنَعَهُ وَالشَّافِعِيُّ أَيْضًا، وَأَجَازَهُ أَبُو حَنِيفَةَ
Artinya: “Sesungguhnya jika modal itu berupa urudl (barang), maka secara tidak langsung telah terjadi gharar, disebabkan pengelola menerima berupa barang yang tidak diketahui nilai padanannya. Lain halnya bila ada padanan nilainya (maka unsur gharar menjadi hilang). (Jika tidak diketahui nilai padanannya) maka modal menjadi bersifat majhul (tidak diketahui). Sementara itu bila modal adalah berupa obyek materi (urudl) yang dijual dulu, maka menurut Imam Malik hukumnya dicegah. Pendapat yang sama disampaikan oleh Imam Syafii. Lain halnya dengan Abu Hanifah, ia menyatakan boleh” (Ibnu Rusyd al-Andalusi, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
Dasar utama penolakan modal berupa ‘urudl (barang materiel) oleh Imam Malik, adalah sebagai berikut:
وَعُمْدَةُ مَالِكٍ: أَنَّهُ قَارَضَهُ عَلَى مَا بِيعَتْ بِهِ السِّلْعَةُ وَعَلَى بَيْعِ السِّلْعَةِ نَفْسِهَا، فَكَأَنَّهُ قِرَاضٌ، وَمَنْفَعَةٌ، مَعَ أَنَّ مَا يَبِيعُ بِهِ السِّلْعَةَ مَجْهُولٌ، فَكَأَنَّهُ إِنَّمَا قَارَضَهُ عَلَى رَأْسِ مَالٍ مَجْهُولٍ
Artinya: “Dasar pedoman Imam Malik (atas penolakan ini) adalah dengan modal berupa urudl, maka pemodal mengeluarkan modal berupa barang yang potensi dijual saja (belum berupa nilai pasti). Berdasar sifat barang yang hanya potensi bisa dijual unsigh, maka seolah pemodal memodali pelaksana dengan barang plus mengambil manfaat dari modal tersebut (barang yang diutangkan). Dengan demikian, karena harga pasti barang bersifat tidak diketahui, maka seolah pula pemodal telah mengeluarkan modal berupa barang majhul (tidak diketahui)” (Ibnu Rusyd al-Andalusy, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 631).
Walhasil, alasan ketidakbolehan memodali seorang ‘amil berupa barang materiel (‘urudl), adalah disebabkan karena unsur jahalah (ketidaktahuan) atas nilai barang sehingga berpotensi timbulnya gharar (penipuan) yang bersifat merugikan bagi pengelola atau bahkan bagi pemodal sendiri. Dalam praktiknya, seseorang yang menyerahkan sapi kepada pengelola agar dirawat, bisa saja dia memberitahukan bahwa sapi tersebut memiliki harga sebesar 12 juta. Padahal harga aslinya adalah 10 juta. Angka 2 juta itulah yang dimaksud sebagai mengambil manfaat dari barang modal yang dicegah oleh Imam Malik dan jumhur ulama’. Seharusnya, penyerahan modal ini dianjurkan berupa uang yang mana kedua pihak kemudian berangkat ke pasar untuk membeli sapi. Dengan begitu, maka peluang timbulnya unsur jahalah bisa diminimalisir sebagaimana harus dihindari dalam akad, sehingga pula konsekuensi timbulnya grarar (penipuan) tidak terjadi di antara kedua pihak antara pengelola dan pemodal.
Adapun perhitungan untung rugi dari model akad mudharabah dengan modal berupa uang untuk membeli sapi akan menjadi sebagai berikut:
1. Harga beli sapi merupakan modal
2. Harga jual sapi di akhir akad merupakan kumpulan dari untung dan modal
3. Selisih antara harga beli sapi dengan harga jualnya adalah keuntungan yang bisa dibagi menjadi dua sesuai dengan nisbah yang disepakati antara kedua pihak
4. Bila sapi tersebut memiliki anak, maka anak sapi juga harus diwujudkan dalam bentuk nilai jual. Harga jual anak sapi ini langsung dibagi dua antara pemodal dan perawat, tanpa dipotong biaya modal sebelumnya.
Wallahu a’lam bish shawab.
Ustadz Muhammad Syamsudin, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur