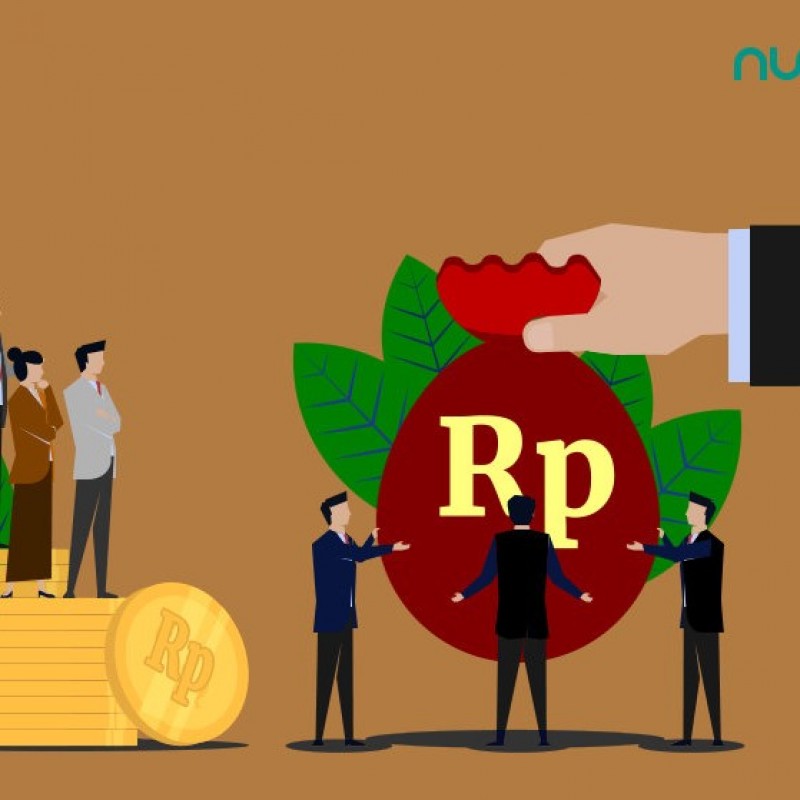Muhammad Syamsudin
Kolomnis
Keuntungan (az-ziyadah) yang didapat dari riba hukumnya haram, disebabkan karena dua illat hukum yang terlibat di dalamnya, yaitu: adanya penindasan (zhulm) dan akibat adh’afan mudha’afah (berlipat hampir dua kali lipat). Ketiadaan memenuhi dua illat hukum ini, menandakan bahwa muamalah yang dilakukan adalah sesuai dengan maqashid syariah sebagai praktik menjaga hak-hak atas harta (hifzhul mal).
Kepatuhan menghilangkan unsur penindasan (zhulm) dan eksploitatif (adh’afan mudha’afah) merupakan praktik menjaga hak-hak atas agama (hifzhud din), sebagaimana keduanya merupakan yang diharamkan secara ijma’. Karena keduanya diharamkan secara ijma’, maka demikian pula dengan riba, adalah diharamkan secara ijma’ pula. Sesuatu yang diharamkan secara ijma’, maka hukumnya adalah kafir bila mengkufurinya.
Semangat menghilangkan penindasan ini juga berlaku atas jual beli. Meskipun di dalam nash disebutkan bahwa jual beli itu adalah halal, namun dalam realitanya, ada mekanisme jual beli yang dilarang oleh syara’. Beberapa praktik jual beli yang nyata dilarang oleh syariat secara ijma’, antara lain, adalah jual beli talaqqy rukban (mencegat rombongan pedagang di tengah jalan), jual beli hadhir lil bad (mencegat rombongan pedagang luar kota sebelum masuk pasar), ihtikar (menumpuk barang saat masyarakat sedang paceklik), dan jual beli barang yang tidak bisa dijamin.
Meskipun semua sah dan dibenarkan oleh syariat, akan tetapi bila praktik itu dilakukan dengan talaqqy rukban, bai’ hadhir lil bad, ihtikar, atau menjual barang yang tidak bisa dijamin, maka tidak diragukan lagi bahwa praktik-praktik itu sebagai yang tidak dibenarkan oleh syariat. Karena dilarang, maka termasuk haram dilakukan. Bahkan untuk menanggulangi ihtikar (monopoli), diperbolehkan bagi seorang pemimpin negara atau pihak yang mewakilinya, atas nama menjaga kemaslahatan umum masyarakat, guna mengambil kebijakan yaitu merampas secara paksa harta yang ditimbun oleh pedagang, kemudian membagikannya kepada khalayak masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Selanjutnya, karena ada hak milik yang harus dijaga, negara dibenarkan untuk memberikan ganti rugi berupa harga mitsil (harga standard) kepada pemilik barang.
Mencermati terhadap kasus ini, ada dua komponen yang rupa-rupanya hendak dijaga oleh syariat demi terwujudnya kemaslahatan, yaitu hak pemilik harta dan hak masyarakat karena adanya illat paceklik. Kedua hak ini harus dipenuhi seiring adanya maslahah dharury yang harus dicapai.
Hal yang sama ternyata juga berlaku atas harta milik seseorang yang diduga ia memiliki tabiat israf (boros). Demi menjaga kemaslahatan hidup person individu tersebut, negara/hakim/pemimpin masyarakat setempat (wali) dibenarkan untuk melakukan tindakan hajr (menahan penasharufan) barang milik musrif (pemboros) tersebut untuk tidak dibelanjakan, sehingga semua transaksinya dianggap tidak sah secara syariat. Sudah pasti tindakan hajr ini adalah karena sebuah alasan yang dibenarkan syariat, yaitu menghadirkan kemaslahatan. Menghadirkan kemaslahatan umum/khusus kepada masyarakat adalah tanggung jawab dari pemimpin/wali.
Dalam praktik riba yang berkaitan dengan tukar menukar barang ribawi, sangat dikenal adanya transaksi bai’ araya. Bai ‘araya didefinisikan sebagai:
بيع العرايا: (مصطلحات) أن يشتري رجل من آخر ما على نخلته من الرطب بقدره من التمر تخمينا ليأكله أهله رطبا
Artinya: “Jual beli araya (secara istilah), adalah jual beli yang dilakukan oleh seseorang dengan jalan membeli kurma hijau (ruthab) milik pihak lainnya ditukar dengan kurma kering untuk kebutuhan makan keluarganya.” (Mu’jam al-Ma’any)
Jadi, suatu ketika ada orang yang membutuhkan kurma kering untuk kebutuhan makan bagi keluarganya. Ia tidak memiliki sesuatu apapun selain kurma yang masih hijau di atas pohon. Lalu ia menghubungi saudaranya yang memiliki kurma kering untuk melakukan transaksi tukar menukar dengannya. Kurma kering ditukar dengan kurma yang masih dipohon, akad ini jelas-jelas merupakan transaksi ribawi. Kaidah yang diabaikan dalam hal ini adalah kaidah tamatsul (kesamaan dari sisi berat). Karena praktik jual beli barang ribawi yang sama jenisnya (sama-sama kurmanya) melazimkan tiga ketentuan, yaitu wajib hulul (kontan), tamatsul (kesamaan takaran), dan taqabudh (saling serah terima). Praktik bai’ al-araya ini mengabaikan ketentuan tamatsul. Itu sebabnya kemudian diterapkan sebuah pendekatan (taqriban) terhadap kaidah tamatsul ini. Sebagaimana hadits:
عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا: أَنْ تُبَاعَ بِخَرْصِهَا كَيْلًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
Artinya: “Dari Zaid bin Tsâbit radliyallahu ‘anhu: Sesungguhnya Rasulullah SAW telah memberi keringanan dalam jual beli araya, yaitu: Jual beli dengan melakukan kharsh takaran.”(HR: Bukhari dan Muslim).
Kharsh dalam istilah ilmu hitung sering dimaknai dengan menaksir, dan mengira-ngira. Yang dikira-kira adalah kurma muda yang masih ada di pohon. Hadits ini memiliki jalur sanad sahabat Zaid ibn Tsabit. Beliau terkenal sebagai pakar ilmu hisab di jaman Nabi Muhammad SAW. Adapun batasan kebolehan jual beli araya adalah 5 ausuq. Sebagaimana hal ini tertuang dalam hadits:
وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالى عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا من التَّمر، فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ، أو فِي خَمْسَةِ أَوْسُقٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
Artinya: "Dari Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu: Rasulullah SAW telah menetapkan keringanan jual beli araya dengan jalan menaksir seberat kurma kering, dengan catatan beratnya tidak lebih dari 5 awsuq. ” (HR: Bukhari dan Muslim)
Lima ausuq itu setara dengan 1 nishab barang zakat. 1 wasaq setara dengan 60 sha’. 1 sha’ setara dengan 4 mud = kira-kira 2.5 kg beras. Jadi, 1 wasaq itu kurang lebih setara dengan (60 sha’ x 2,5 kg) beras = 150 kg. 5 wasaq kurang lebih sama dengan dengan 150 kg x 5 = 750 kg atau 7,5 kwintal beras. Sebuah angka pertukaran barang ribawi yang sejatinya cukup besar bagi masyarakat kita.
Batasan 5 awsuq ini ibarat tahdids sil’i (pamatokan kuantitas barang ribawi yang dibolehkan oleh Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam) sehingga masuk akad pertukaran ribawi yang ditoleransi (rukhshah) oleh syariat. Sudah pasti toleransi ini memiliki illat kemaslahatan yaitu berupa kebutuhan manusia (hajatun nas) terhadap kurma kering sebagai makanan pokok.
Jika ternyata dalam praktik jual beli ada juga jual beli yang dilarang, sementara dalam praktik riba, ternyata ada bagian pertukaran barang ribawi yang masih diperbolehkan oleh syariat, maka illat yang kuat mendasari kebolehan praktik pertukaran ribawi yang ditoleransi itu adalah karena faktor adanya hajatun nas. Sementara, illat yang kuat mendasari praktik dilarangnya pertukaran ribawi atau praktik jual beli, adalah karena adanya unsur penindasan (zhulm) dan eksploitatif sebagaimana tercermin dari adh’afan mudha’afah (hampir dua kali kelipatan). Alhasil, muara keduanya ada pada kemaslahatan umat. Wallahu a’lam bis shawab.
Muhammad Syamsudin, Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah-PW LBMNU Jawa Timur
Terpopuler
1
Apa Itu Dissenting Opinion dan Siapa Saja Hakim yang Pernah Melakukannya?
2
Khutbah Jumat: Inspirasi Al-Fatihah untuk Bekal Berhaji ke Baitullah
3
Harlah Ke-74: Ini Asas, Tujuan, dan Lirik Mars Fatayat NU
4
Kajian Lengkap Kriteria Miskin bagi Pekerja dalam Bab Zakat
5
3 Hakim Nyatakan Dissenting Opinion, Paslon 01 dan 03 Terima Putusan MK
6
Kasus DBD Melonjak, Berikut Cara Pencegahannya Menurut Dokter
Terkini
Lihat Semua