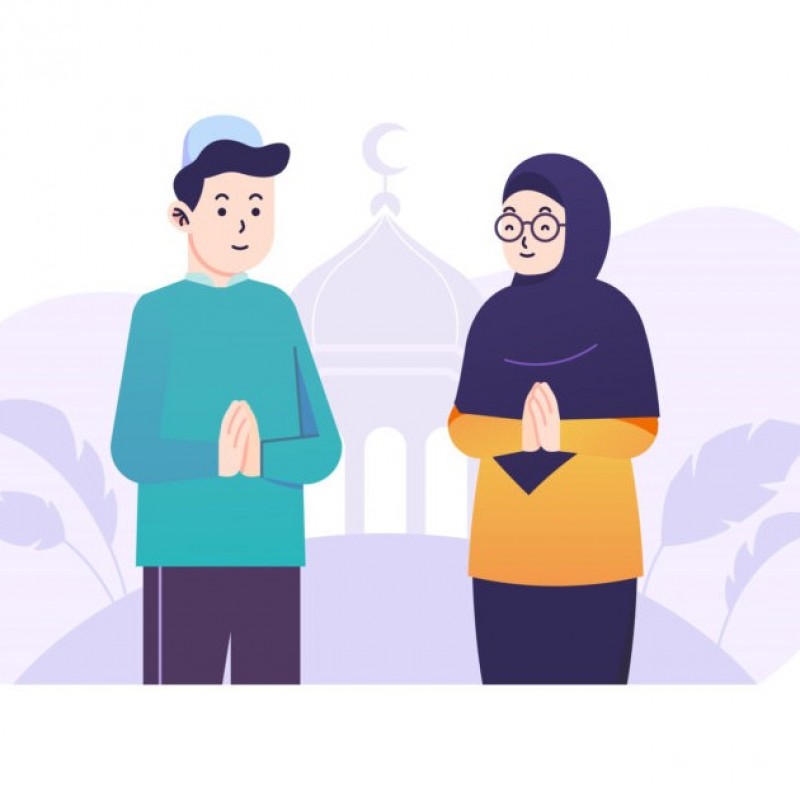Bagaimana Status Kesucian atau Makshum Para Wali Allah?
Jum, 10 Juli 2020 | 13:00 WIB

apakah kesucian para wali serupa dengan derajat kemakshuman seperti status kesucian para nabi (ishmatul anbiya)?
Alhafiz Kurniawan
Penulis
Para wali Allah dipercaya sebagai orang suci yang dekat dengan Allah. Tetapi apakah kesucian mereka yang kita pahami serupa dengan derajat kemakshuman seperti status kesucian para nabi (ishmatul anbiya)? Pertanyaan ini mengemuka dalam kajian tasawuf.
Abul Qasim Al-Qusyairi menjelaskan bahwa hamba-hamba Allah yang mencapai derajat kewalian tidak memiliki kemakshuman seperti derajat kesucian para nabi. Meski demikian, para wali adalah hamba-hamba yang mendapatkan bimbingan, penjagaan, dan pemeliharaan Allah (mahfuzh).
Ketika mereka terjatuh dalam sebuah kekhilafan, Allah segera menyelamatkan mereka. Kekhilafan para wali bukan mustahil. Kekhilafan mereka tidak mencabut status kewalian mereka.
فإن قيل هل يكون الولي معصوماً قيل أما وجوباً، كما يقال في الأنبياء فلا. وأما أن يكون محفوظاً حتى لا يصر على الذنوب إن حصلت هنات أو آفات أو زلات، فلا يمتنع ذلك في وصفهم
Artinya, “Jika ditanya, ‘Apakah wali itu makshum?’ Dijawab, adapun pasti sebagaimana kemakshuman para nabi, tentu tidak. Tetapi wali itu bersifat mahfuzh sehingga ia tidak terjebak dalam dosa secara terus menerus jika terjadi petaka, celaka, atau kegelinciran. Semua itu tidak mencegah pada sifat kewalian mereka,” (Abul Qasim Al-Qusyairi, Ar-Risalah Al-Qusyairiyyah, [Kairo, Darus Salam: 2010 M/1431 H], halaman 191).
Imam Al-Qusyairi mengangkat percakapan Imam Junaid Al-Baghdadi perihal ahli makrifat yang terjebak dalam dosa besar. Imam Junaid menjawab pertanyaan tersebut dengan menerangkan kuasa Allah.
ولقد قيل للجنيد العارف يزني يا أبا القاسم؟ فاطرق ملياً، ثم رفع رأسه وقال وكان أمر الله قدراً مقدرواً
Artinya, “Imam Junaid Al-Baghdadi pernah ditanya, ‘Apakah orang dengan maqam makrifat dapat berzina wahai Abaul Qasim (panggilan untuk Imam Junaid)?’ Ia terdiam dan menundukkan kepala sejenak. Setelah itu ia mengangkat kepala dan membaca Surat Al-Ahzab ayat 38, ‘Keputusan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku,’” (Al-Qusyairi, 2010 M/1431 H: 191).
Terkait hal ini, Ibnu Athaillah pada hikmah pertama Kitab Al-Hikam-nya mengatakan bahwa salah satu tanda ketergantungan pada amal (dalam taqarrub kepada Allah) adalah turunnya harapan ketika terjatuh dalam sebuah dosa.
As-Syarqawi dalam mengomentari hikmah ini menjelaskan bahwa orang-orang dengan status makrifat tidak memandang dirinya sedikitpun sehingga dapat diandalkan. Mereka justru menyaksikan pelaku hakiki adalah Allah. Mereka hanya tempat pengejawantahan kehendak-Nya. (As-Syarqawi, Syarhul Hikam: 3).
Jika tergelincir dalam sebuah dosa, yang mereka saksikan adalah perbuatan dan ketetapan Allah sebagaimana yang mereka saksikan pada pelaksanaan ibadah mereka atau pancaran cahaya ilahi di hati mereka. Mereka sama sekali tidak memandang kekuatan dan daya mereka. Dengan demikian, dua kondisi (terjatuh pada dosa atau pelaksanaan ibadah) bagi mereka sama saja karena mereka tenggelam dalam lautan tauhid.
Rasa takut dan harap para wali Allah tetap proporsional. Sebuah maksiat tidak mengurangi takut mereka kepada Allah. Sedangkan kebaikan dan ibadah mereka tidak menambah harap mereka kepada Allah. Inilah yang disebut derajat makrifat (maqamul ‘irfan). (As-Syarqawi, Syarhul Hikam: 3-4).
Kedudukan kelompok ahli makrifat berbeda dengan kelompok murid dan abid (ahli ibadah) yang bergantung pada amal perbuatan. Karena ketergantungan pada selain Allah, kedua kelompok ini kehilangan harapan kepada Allah ketika melakukan kekhilafan dan merasa besar ketika ibadahnya meningkat. (As-Syarqawi, Syarhul Hikam: 3-4). Wallahu a’lam.
Penulis: Alhafiz Kurniawan
Editor: Abdullah Alawi
Terpopuler
1
Membatalkan Puasa Syawal karena Disuguhi Hidangan saat Bertamu, Bagaimana Hukumnya?
2
Khutbah Jumat: Meraih Pahala Berlimpah dengan Puasa Syawal
3
Hukum Mengulang Akad Nikah karena Grogi
4
Tellasan Topak, Tradisi Perayaan Lebaran Ketupat di Madura pada 8 Syawal
5
Sejarah Awal Berdirinya Pesantren Babakan Ciwaringin Cirebon
6
Indonesia Kalah 2-0 dari Qatar, Suporter Timnas Sebut Wasit Berlebihan Dukung Tuan Rumah
Terkini
Lihat Semua