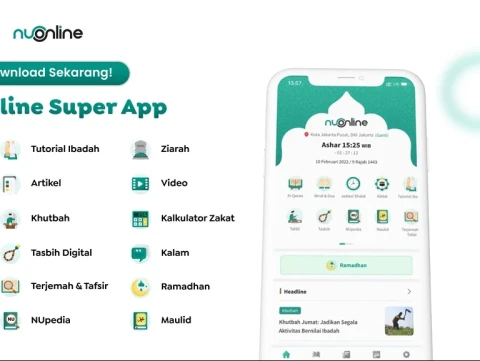Coba kita renungkan sejenak, sudah berapa kali Ramadhan datang lalu pergi meninggalkan kita? Setiap tahun kita menjalani puasa, menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun, pertanyaannya, apa hasil yang benar-benar kita peroleh dari puasa tersebut?
Apakah ia telah membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih taat, dan lebih bertakwa, ataukah ia berlalu begitu saja tanpa meninggalkan bekas yang berarti dalam sikap dan perilaku kita?
Jangan-jangan, puasa yang selama ini kita laksanakan hanyalah rutinitas tahunan yang dikerjakan berulang-ulang, tetapi belum sungguh-sungguh menghadirkan nilai dan perubahan nyata dalam kehidupan kita.
Bahkan bisa jadi, yang kita peroleh dari puasa tersebut hanyalah rasa lapar dan dahaga semata, sebagaimana peringatan Rasulullah SAW:
كَمْ مِنْ صَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ صِيَامِهِ إِلَّا الْجُوعُ
Artinya: “Betapa banyak orang yang berpuasa, namun tidak ada yang ia peroleh dari puasanya selain rasa lapar.” (HR. Ahmad)
Padahal, tujuan utama puasa bukan sekadar menahan diri dari makan dan minum, melainkan untuk menumbuhkan ketakwaan. Hal ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya:
يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ
Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 183).
Ayat tersebut bukan sekadar ayat perintah puasa Ramadhan, akan tetapi juga menjelaskan tujuan atau hikmah di balik disyariatkannya puasa. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Asyur dalam tafsirnya, at-Tahrir Wat Tanwir.
Menurut beliau frasa (لعل) pada kalimat (لَعَلَّكُمْ تَتَّقُوْنَۙ) "agar kamu bertakwa" merupakan mus'taarah yang mempunyai makna (كَي / agar) sebagai isti‘arah tabi‘iyyah, dan adakalanya merupakan tamtsiliyyah (penyerupaan), yaitu dengan menyerupakan keadaan Allah dalam menghendaki terwujudnya ketakwaan melalui pensyariatan puasa seperti orang yang berharap kepada orang lain agar melakukan suatu perbuatan.
Pengertian takwa menurut syariat adalah menjauhi perbuatan maksiat. Puasa menjadi sebab terhindar dari maksiat karena maksiat itu terbagi menjadi dua macam: Pertama, maksiat yang efektif dapat ditinggalkan dengan tafakur atau perenungan, seperti meminum khamar, judi, mencurian, dan merampas. Meninggalkannya dapat terwujud dengan merenungkan janji pahala bagi yang meninggalkannya, ancaman siksa bagi pelakunya, serta nasihat untuk mengambil ibrah atau pelajaran dari keadaan orang lain.
Kedua, maksiat yang bersumber dari dorongan-dorongan tabiat, seperti perbuatan yang timbul dari amarah dan syahwat , yang terkadang sulit ditinggalkan hanya dengan perenungan atau tafakur semata. Maka puasa sebagai sarana untuk menghindarinya, karena puasa menyeimbangkan kekuatan-kekuatan tabi'at yang menjadi pendorong terjadinya maksiat-maksiat tersebut.
Dengan puasa, seorang Muslim derajatnya akan naik dari jurang keterjerumusan materi menuju puncak alam ruhani. Puasa menjadi sarana latihan diri dengan sifat-sifat malaikat dan kebangkitan dari debu kekeruhan sifat-sifat kebinatangan .(Muhammad at-Thahir Asyur, At-Tahrir wa At-Tanwir, [Tunis, Dar-At-Tunisia: 1984 M], juz II, halaman 158).
Oleh karena itu, dapat kita pahami bahwa nilai puasa sejatinya terletak pada sejauh mana puasa tersebut mampu melahirkan ketakwaan dan membentuk perubahan akhlak, sehingga mengantarkan seorang Muslim menjadi pribadi yang lebih baik, lebih bertakwa, dan semakin dekat kepada Allah.
Tujuan mulia ini tidak akan terwujud apabila puasa hanya dikerjakan sebatas sah menurut fikih semata. Lebih dari itu, puasa perlu dihayati dan diamalkan secara menyeluruh dengan menjaga lahir dan batin. Dalam hal ini, al-Imam al-Ghazali memberikan enam tuntunan penting agar puasa benar-benar bernilai dan membekas. Berikut kami ringkaskan enam poin tersebut sebagaimana termaktub dalam kitab Mauizhatul Mu’minin min Ihya’ ‘Ulumid Din:
Pertama, menundukkan pandangan dan menahannya dari memandang segala sesuatu yang tercela dan dibenci, serta dari segala hal yang dapat menyibukkan hati dan melalaikan dari mengingat Allah Ta‘ala.
Kedua, menjaga lisan dari perkataan sia-sia, dusta, ghibah, adu domba, ucapan keji, sikap kasar, pertengkaran, dan perdebatan.
Ketiga, menjaga pendengaran dari mendengarkan segala hal yang dibenci, karena setiap sesuatu yang diharamkan untuk diucapkan, haram pula untuk didengarkan.
Keempat, menahan seluruh anggota tubuh seperti tangan dan kaki dari perbuatan dosa dan hal-hal yang dibenci, serta menjaga perut dari perkara syubhat ketika berbuka. Tidak ada artinya puasa, menahan diri dari makanan halal, lalu berbuka dengan yang haram. Perumpamaan orang yang seperti ini adalah orang yang membangun istana tetapi meruntuhkan sebuah kota.
Kelima, tidak berlebihan dalam mengonsumsi makanan halal saat berbuka hingga perut menjadi penuh. Bagaimana mungkin tujuan puasa yaitu menundukkan musuh Allah dan mematahkan syahwat dapat terwujud, jika seorang yang berpuasa justru mengganti seluruh kekurangan makannya di siang hari saat berbuka, bahkan menambahnya dengan beragam jenis hidangan? Padahal tujuan puasa adalah mengosongkan perut dan melemahkan hawa nafsu, agar jiwa menjadi kuat dalam ketakwaan.
Keenam, setelah berbuka, hendaknya hatinya berada dalam keadaan gelisah, harap-harap cemas karena ia tidak mengetahui apakah puasanya diterima sehingga ia termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah, ataukah ditolak sehingga ia termasuk orang-orang yang dimurkai. Sikap seperti ini seharusnya menyertai setiap ibadah yang telah ia selesaikan. (Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Mauizhatul Mu’minin min Ihya’ ‘Ulumid Din, [Beirut, Darul Kutub al-Ilmiyah: 1995] halaman 61-62).
Dengan demikian, apabila puasa dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukunnya serta disempurnakan dengan adab-adabnya, maka tujuan puasa yang hakiki, yaitu melahirkan ketakwaan, akan benar-benar terwujud. Puasa menjadi sarana transformasi diri yang melatih manusia untuk mengendalikan nafsu terhadap perkara yang halal, agar lebih mampu menahan diri dari yang haram. Dari sinilah tumbuh kemampuan mengontrol diri dan bersikap lurus meskipun tanpa pengawasan manusia, lebih menjaga lisan dan emosi, serta hidup sederhana dalam konsumsi tanpa berlebih-lebihan.
Ustadz Muhamad Hanif Rahman, Dosen Ma'had Aly Al-Iman Bulus dan Pengurus LBM NU Purworejo.