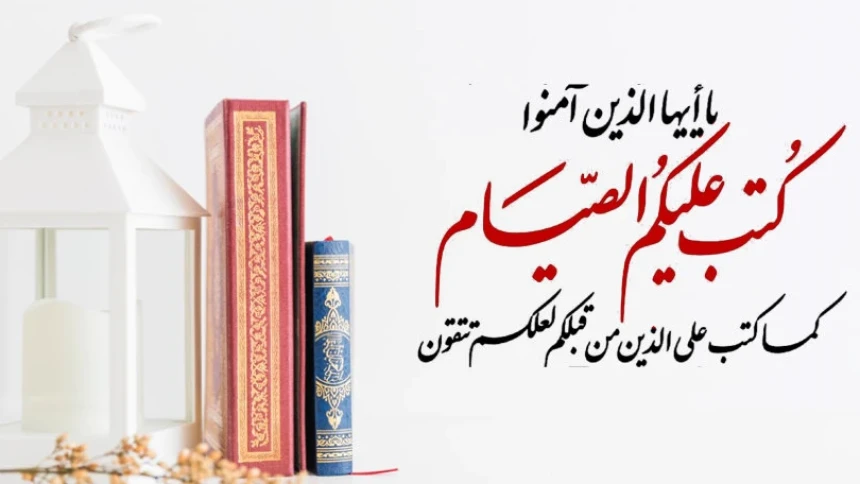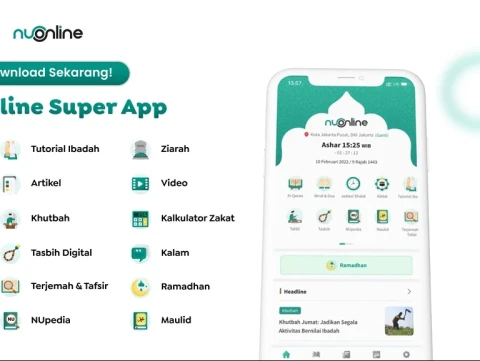Al-Quran mengabarkan kepada kita bahwa kewajiban puasa tidak hanya diberikan kepada umat Rasulullah saw. Para nabi dan umat-umat sebelumnya juga sudah mendapatkannya. Hanya waktu dan praktiknya saja yang berbeda. Ada yang puasa selang sehari seperti puasa Nabi Dawud, ada puasa tanggal 13, 14, 15 setiap bulannya seperti puasa Nabi Adam, ada puasa ‘Asyura setiap tanggal 10 Muharram seperti umat Yahudi.
Kepada Rasulullah saw, kewajiban puasa dimulai pada tahun kedua Hijriah. Semasa hidup beliau sendiri menunaikannya sebanyak sembilan kali. Di masanya pula, penyariatan atau pemberlakuan ibadah puasa mencapai puncak kematangannya.
Namun perlu diketahui, pada awal pemberlakuan ibadah puasa, waktu dan tata cara puasa tidak seperti yang kita kenal sekarang, yakni menahan segala yang membatalkan dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Sebelum itu, ada sejumlah proses dan tahapan di dalamnya. Proses dan tahapan itu tentunya sejalan dengan hikmah dan kasih sayang Allah yang maha lembut, selaku Dzat yang maha mengetahui keadaan para hamba-Nya.
Lebih jelasnya, proses dan tahapan tersebut telah disebutkan oleh Syekh Khalid ibn ‘Abdurrahman dalam kitabnya, As-Shaumu Junnatun, halaman 17 sebagai berikut:
- Sebelum ayat perintah puasa Ramadhan turun, sudah diberlakukan perintah puasa ayyamul bidh setiap bulan hijriah dan puasa ‘Asyura setiap tanggal 10 Muharram. Rasulullah saw senantiasa mendorong para sahabat untuk menunaikan puasa itu. Namun, ketika puasa Ramadhan diwajibkan, beliau tak lagi memerintah mereka, tidak pula melarang. Kefardhuan puasa Ramadhan sebagaimana dimaklumi mulai sejak turun surat Al-Baqarah, “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa,” (QS Al-Baqarah: 183).
- Menjalankan perintah puasa masih diizinkan tidak secara total. Masih ada keringanan berbuka bagi yang mampu asalkan mengeluarkan fidyah. Artinya, yang mau berpuasa, yang tidak mau cukup dengan fidyah. Ketentuan ini mempertimbangkan masih banyaknya sahabat yang belum terbiasa berpuasa, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat, “Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidyah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. (QS Al-Baqarah: 184).
- Keringanan berbuka puasa bagi yang mampu dihapus. Kebolehan berbuka hanya berlaku bagi orang yang sakit dan bepergian jauh, sebagaimana bunyi ayat: “Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain,” (QS Al-Baqarah: 185).
Walhasil, setelah turun ayat di atas, para sahabat yang menyaksikan hilal Ramadhan, wajib berpuasa. Tidak ada lagi keringanan berbuka selama mampu dan tidak sedang bepergian. - Pada awal pensyariatan puasa, seperti yang disinggung At-Thabari, makan, minum, dan hubungan suami-istri pada malam hari tidak diperbolehkan seperti halnya sekarang. Kendati dibolehkan melakukannya hanya sebelum tidur dan sebelum shalat Isya.
Artinya, jika sudah tidur atau sudah shalat Isya di malam hari, ia tidak boleh makan, minum, atau hubungan suami-istri di sisa malam tersebut, hingga menjalani ibadah puasa pada hari berikutnya dan berbuka pada waktu Magrib. (At-Thabari, Tafsir At-Thabari, [Muassasatur Risalah: 2000], juz III, halaman 487).
Ketentuan ini seperti yang ditunjukkan dalam riwayat al-Bara’ ibn ‘Azib. Ia menuturkan, “Jika salah seorang sahabat berpuasa dan datang waktu berbuka, namun ia belum berbuka karena tidur, maka ia tidak lagi boleh makan dan minum pada malam itu hingga siang hari berikutnya dan berbuka di sore hari,” (HR Al-Bukhari).
Ketentuan puasa yang diungkap hadits Al-Bara’ ini tak pelak memberatkan para sahabat, sehingga banyak di antara mereka yang tak mampu menahan diri, dan akhirnya menjadi asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat Al-Quran yang meringankan mereka makan, minum, berhubungan suami-istri pada malam hari, baik sebelum mereka tidur atau setelahnya, baik sebelum mereka shalat isya atau setelahnya.
Beberapa kejadian yang mengantarkan turunnya ayat dimaksud antara lain yang diriwayatkan oleh sahabat Umar. Disebutkan pada suatu malam, Sayyidina ‘Umar bin Khathab berada di tempat Rasulullah saw serta pulang ke rumah cukup malam dan mendapati istrinya sudah terlelap tidur. Rupanya saat itu, Sayyidina ‘Umar ingin bergaul bersama istrinya. Namun, ditolak oleh istrinya karena alasan ia sudah tidur.
Keesokan paginya, Sayyidina ‘Umar kembali menemui Rasulullah saw. dan mengabarkan kejadiannnya semalam. Maka Allah menurunkan ayat, “Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa,” (QS Al-Baqarah: 187).
Riwayat lain menyebutkan menyebutkan bahwa Qais ibn Shirmah Al-Anshari berpuasa. Pada saat berbuka, ia bertanya kepada istrinya, “Apakah kau punya makanan?” Istrinya menjawab, “Tidak! Tapi aku akan mencarikannya untukmu.” Rupanya, karena siang hari itu Qais ibn Shirmah lelah bekerja, matanya tak mampu menahan kantuk. Begitu pulang dan mendapati suaminya sudah tidur, istri Qais berkata, “Celakalah engkau!” Esoknya, Qais tetap berpuasa. Namun pada tengah hari, ia pingsan tak sadarkan diri. Kejadian itu pun disampaikan kepada Rasulullah saw.
- Sejak itu, ditetapkanlah pensyariatan puasa dengan tata cara seperti sekarang ini, yakni menjauhi segala yang membatalkan, baik makan, mainum, maupun bergaul suami-istri, sejak terbit fajar shadiq hingga terbenam matahari. Sedangkan pada malam hari, semua itu diperbolehkan, tanpa ada syarat: setelah atau sebelum tidur, setelah atau sebelum shalat Isya. (Khalid ibn ‘Abdurrahman, 27).
Melalui beberapa proses dan tahapan di atas, maka tetaplah pensyariatan ibadah puasa Ramadhan; wajib dilakukan setiap muslim selama satu bulan, kecuali yang sedang sakit atau bepergian jauh. Semua tahapan dan ketentuan ini tak terlepas dari hikmah, kasih sayang, dan kelembutan Allah kepada hamba-hamba-Nya. Maha benar Allah yang tak menginginkan kesulitan bagi mereka, “Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur,” (QS Al-Baqarah: 185).
Demikian sejarah singkat tentang proses dan tahapan pensyariatan atau pemberlakuan puasa dalam agama Islam. Berkat kemurahan Allah, alhamdulillah, puasa yang kita tunaikan sekarang ini tidak seperti pada awal pensyariatannya. Semoga kita senantiasa diberi kemudahan dan keringanan dalam menjalankannya. Amin.
Ustadz M Tatam Wijaya, Penyuluh dan Petugas KUA Sukanagara-Cianjur, Jawa Barat.