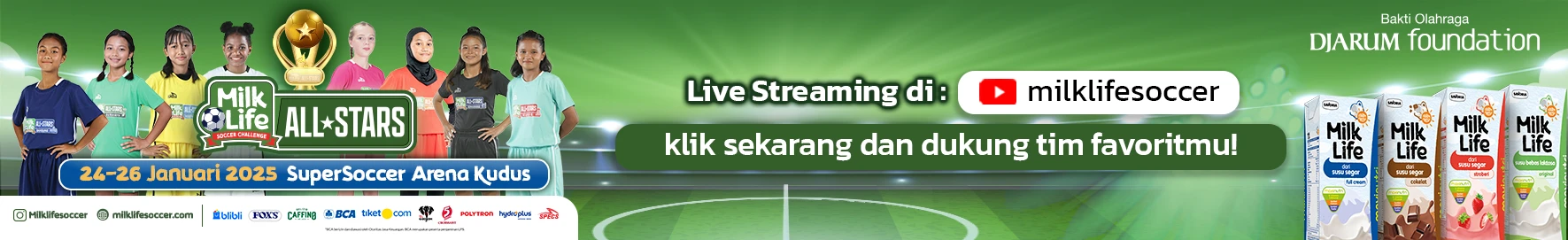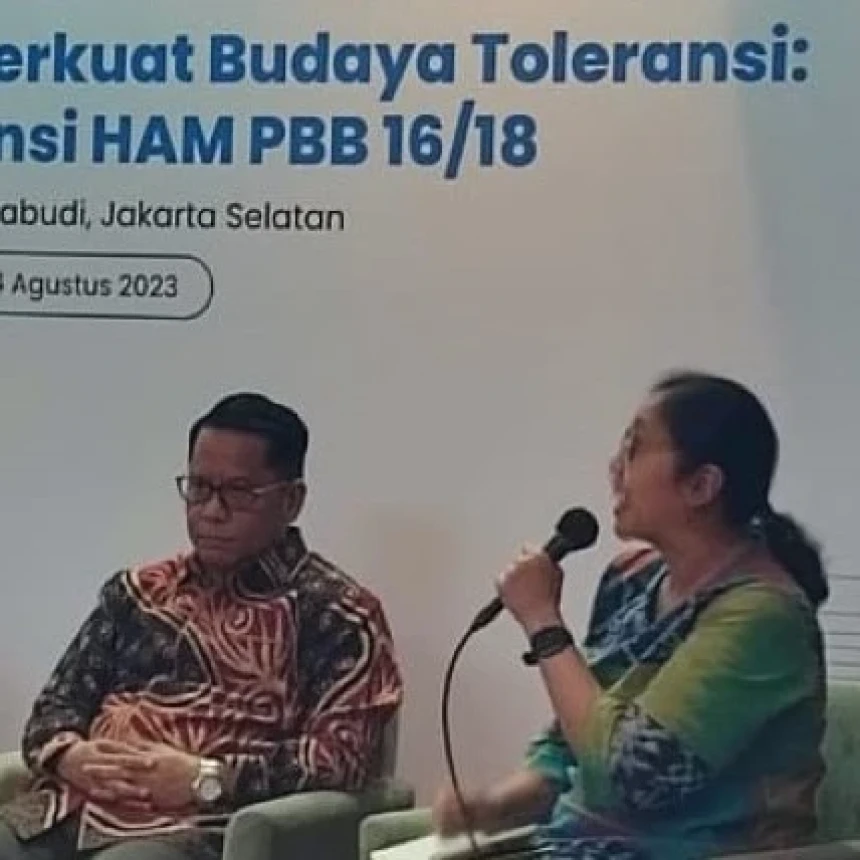Menolak Intoleransi Tanpa Standar Ganda: Tanggapan terhadap Wacana Regulasi Rumah Doa
Rabu, 9 Juli 2025 | 20:04 WIB
Insiden perusakan rumah ibadah umat Kristiani di Sukabumi pada 27 Juni 2025 kembali memunculkan diskusi serius tentang relasi antarumat beragama, kebebasan beribadah, dan peran negara. Dalam opini yang ditulis Abi S. Nugroho yang berjudul Regulasi Rumah Doa, Merukunkan atau Melumpuhkan?di NU Online, diulas bagaimana regulasi rumah doa bisa menjadi alat untuk melindungi hak minoritas—atau sebaliknya, justru memperhalus represi yang terjadi secara struktural.
Tulisan tersebut memiliki keberanian intelektual yang penting: menyentil kenyataan bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas sering kali tidak menyadari privilese sosial yang dimilikinya, dan bagaimana hal itu bisa berdampak pada kelompok lain yang lebih kecil. Namun, tulisan itu juga menyisakan ruang pertanyaan: bagaimana ketika umat Islam berada di posisi minoritas? Apakah suara mereka juga mendapat pembelaan yang sama?
Tanggapan ini ingin memperluas wacana yang sudah dibuka oleh penulis, seraya menegaskan: kita menolak segala bentuk intoleransi—baik yang dilakukan atas nama Islam maupun terhadap umat Islam. Keadilan harus ditegakkan secara universal, tanpa standar ganda, tanpa bergantung pada dominasi jumlah.
Islam dan Prinsip Keadilan untuk Semua
Islam tidak pernah mengajarkan penindasan kepada pemeluk agama lain. Bahkan ketika umat Islam menjadi mayoritas, ajaran Nabi Muhammad saw sangat tegas dalam membela hak orang-orang non-Muslim untuk beribadah dan merasa aman. Dalam Piagam Madinah, kaum Yahudi dan Muslim diakui sebagai satu komunitas politik. Dalam riwayat-riwayat hadits, Nabi saw menegur siapa pun yang menyakiti ahlu zimmah.
Rasulullah saw bersabda: "Barangsiapa menyakiti dzimmi (non-Muslim yang hidup damai dalam wilayah Muslim), maka aku adalah lawannya pada Hari Kiamat." (HR. Abu Dawud)
Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam tidak bersyarat pada status agama, melainkan berlaku universal. Umat Islam sebagai mayoritas di Indonesia semestinya menjadikan ini sebagai pedoman. Bila ada gereja yang dibakar, vihara yang dirusak, atau rumah doa yang diintimidasi, kita tidak bisa tinggal diam atas nama “sensitivitas sosial”.
Namun, keadilan itu juga tidak boleh dibatasi hanya ketika korban adalah non-Muslim. Umat Islam yang menjadi minoritas di daerah tertentu juga berhak mendapat perlindungan yang sama. Ini adalah ruh Islam: menjaga martabat manusia tanpa memandang agama dan jumlah.
Kritik terhadap Regulasi yang Bias Mayoritas
Dalam opininya, Abi S. Nugroho dengan tajam menunjukkan bagaimana regulasi pendirian rumah ibadah—seperti PBM 2006—sering kali berfungsi bukan sebagai pelindung hak, melainkan sebagai alat kontrol sosial yang bias terhadap kelompok mayoritas. Syarat administratif seperti persetujuan 60 warga sekitar dan rekomendasi FKUB tampak demokratis, namun dalam praktiknya sering membuka ruang intimidasi dan penolakan terselubung.
Kita harus mengakui bahwa dalam konteks Indonesia, bias mayoritas itu kerap merugikan kelompok minoritas keagamaan, termasuk umat Kristiani, Konghucu, Hindu kecil, atau kelompok kepercayaan lokal. Di sinilah kritik penulis menjadi relevan: negara tidak cukup hanya jadi “penengah”, tetapi harus tegas sebagai pelindung hak konstitusional warga negara untuk menjalankan ibadah, terlepas dari tekanan mayoritas.
Namun penting pula diingat: kritik terhadap regulasi ini tidak boleh berubah menjadi kecurigaan terhadap agama mayoritas itu sendiri—yakni Islam. Sering kali, intoleransi bukan datang dari ajaran agama, melainkan dari tafsir kekuasaan, sentimen massa, atau kepentingan politik lokal.
Lebih lanjut, kita tidak boleh terjebak pada narasi seolah umat mayoritas di Indonesia secara kolektif menindas. Dalam banyak kasus, masyarakat Muslim pun terbagi antara yang toleran dan yang mudah terprovokasi. Yang dibutuhkan bukan generalisasi, tapi reformasi aturan dan budaya hukum yang berpihak pada semua—bukan mayoritas atau minoritas semata.
Maka benar jika dikatakan bahwa regulasi rumah ibadah perlu dibenahi. Namun, pembenahan itu tidak cukup hanya dengan prosedur baru. Ia harus mencerminkan keberpihakan moral pada keadilan substantif, bukan sekadar kedamaian administratif.
Umat Islam Juga Korban Intoleransi: Jangan Diam Bila Terjadi Ketimpangan Balik
Kritik terhadap intoleransi memang sering diarahkan pada kelompok Islam mayoritas. Tapi ini tidak berarti bahwa umat Islam sendiri bebas dari menjadi korban—terutama ketika mereka menjadi minoritas.
Di berbagai daerah Indonesia, kasus-kasus penolakan terhadap pembangunan masjid juga terjadi: di Flores dan NTT, umat Islam kerap kesulitan membangun masjid dengan alasan yang mirip: keberatan warga sekitar. Di Papua, beberapa komunitas Muslim mengeluhkan penolakan kegiatan keagamaan seperti takbir keliling, pembangunan pesantren, atau azan dengan pengeras suara. Bahkan di beberapa kota besar seperti Manado atau Bali, pembangunan masjid kadang menemui hambatan sosial yang tidak kalah serius.
Sayangnya, kasus-kasus ini jarang mendapat perhatian media sebesar kasus penolakan gereja di Jawa Barat. Maka, bila kita ingin menegakkan keadilan secara universal, suara Muslim minoritas juga harus didengar dan diperjuangkan.
Di sinilah pentingnya konsistensi moral. Bila kita membela gereja yang dipersekusi di daerah Muslim, maka kita pun harus membela masjid yang ditolak di daerah non-Muslim. Tidak boleh ada standar ganda. KH Abdurrahman Wahid (Gus Dur) mengatakan, “Keadilan tidak boleh hanya berdiri untuk mereka yang disukai, dan diam ketika yang terzalimi adalah lawan."
Umat Islam tidak boleh membenarkan intoleransi yang dilakukan atas nama mayoritas. Tapi umat Islam juga tidak boleh diam ketika diperlakukan tidak adil di tempat lain. Keadilan itu bulat, tidak bisa dipotong-potong atas nama siapa mayoritas di suatu tempat.
Menuju Regulasi yang Adil bagi Semua Iman
Kita semua setuju: regulasi rumah ibadah perlu ada, tapi bukan untuk membatasi iman, melainkan untuk menjamin hak-hak spiritual seluruh warga negara. Dan regulasi itu harus berlaku adil bagi semua, baik di Aceh yang mayoritas Muslim, maupun di Bali yang mayoritas Hindu; di Manado, Papua, maupun Jawa Barat.
Regulasi yang adil seharusnya:
1. Berbasis hak konstitusional, bukan izin sosial.
2. Menempatkan negara sebagai pelindung, bukan perantara mayoritas.
3. Tidak memperumit kelompok kecil atau rumah ibadah sederhana.
4. Memastikan FKUB bukan forum dominasi, tetapi mediasi setara.
Bila umat Islam merasa berhak membangun masjid di Flores, maka umat Kristiani pun berhak membangun gereja di Bekasi. Ukurannya bukan jumlah, tapi hak sebagai warga negara. Kita tidak bisa menuntut keadilan kalau tidak siap memberikannya kepada orang lain.
Karena itu, semangat membenahi regulasi rumah doa seharusnya tidak dilihat sebagai ancaman terhadap umat Islam, tapi sebagai peluang untuk menunjukkan kematangan iman, keadilan sosial, dan kebesaran jiwa Islam dalam hidup bersama.
Islam Bukan Sekadar Agama Mayoritas, Tapi Rahmat untuk Semua
Menjadi mayoritas dalam jumlah tidak berarti otomatis menjadi pemilik kebenaran. Dalam sejarah Islam, kekuatan justru lahir dari keadilan terhadap yang lemah, bukan dari penaklukan terhadap yang berbeda. Islam yang agung bukan yang gemar membungkam, tetapi yang membebaskan hati manusia untuk menemukan Tuhan secara sadar dan damai.
Kita harus mulai melepaskan mentalitas curiga, seolah setiap rumah doa yang bukan milik kita adalah ancaman. Kita juga harus menghentikan kecenderungan merasa terzalimi, padahal kita sedang memegang kekuasaan sosial dan politik. Menjadi mayoritas adalah tanggung jawab besar untuk berlaku lebih adil, bukan lebih dominan.
Namun pada saat yang sama, suara umat Islam yang menjadi minoritas juga harus diangkat dengan semangat yang sama. Karena bagi Islam, memperjuangkan keadilan itu bukan karena "siapa yang dizalimi", tetapi karena kezaliman itu sendiri harus dilawan.
Seperti dikatakan oleh Gus Dur: "Yang minoritas bukan untuk ditoleransi, tapi untuk dijamin haknya. Karena mereka bukan tamu, tetapi pemilik sah republik ini."
Maka, kita menyambut niat baik Kementerian Agama untuk menyusun regulasi baru soal rumah doa—asal tidak menjadi jebakan formalisme baru. Yang kita perlukan adalah keadilan yang hidup, bukan birokrasi yang membungkam. Perlindungan yang aktif, bukan kontrol yang membatasi.
Baca Juga
Wajah Multikulturalisme Pesantren
Islam tidak datang untuk membentuk republik yang hanya cocok bagi Muslim, melainkan untuk memperindah kehidupan bersama dalam keadilan. Dan inilah misi rahmatan lil ‘ālamīn yang seharusnya kita hidupi bersama: menolak intoleransi dari siapa pun, melindungi yang kecil tanpa takut pada mayoritas, dan menjaga agar rumah ibadah—dalam bentuk apa pun—tetap menjadi rumah bagi hati yang mencari Tuhan.
Ahmad Chuvav Ibriy, Pengasuh Ponpes Al-Amin Mojowuku Kedamean Gresik, anggota Komisi Fatwa, Hukum dan Pengkajian MUI Kabupaten Gresik, Jawa Timur