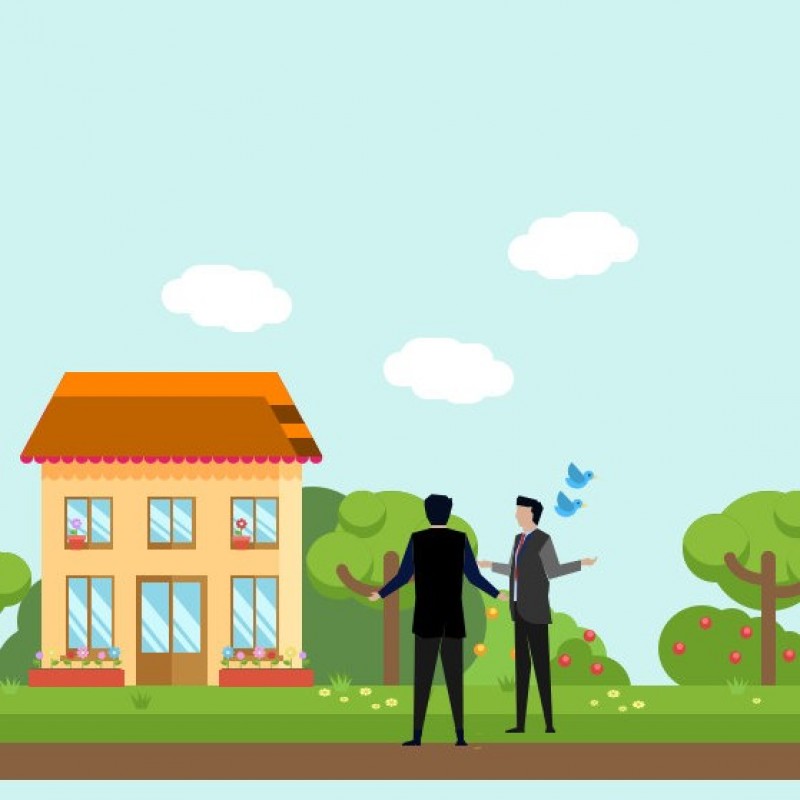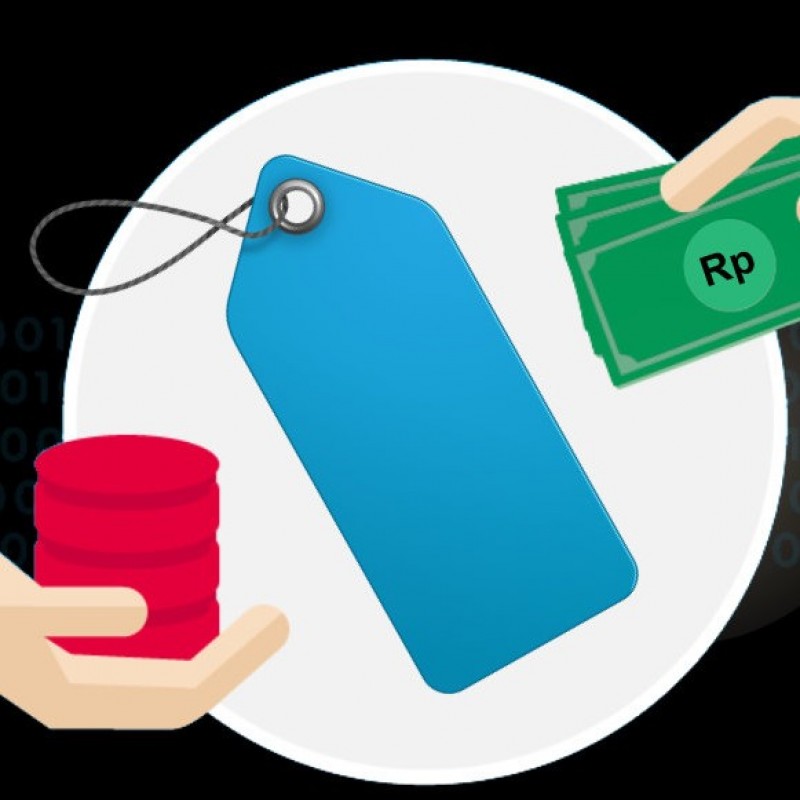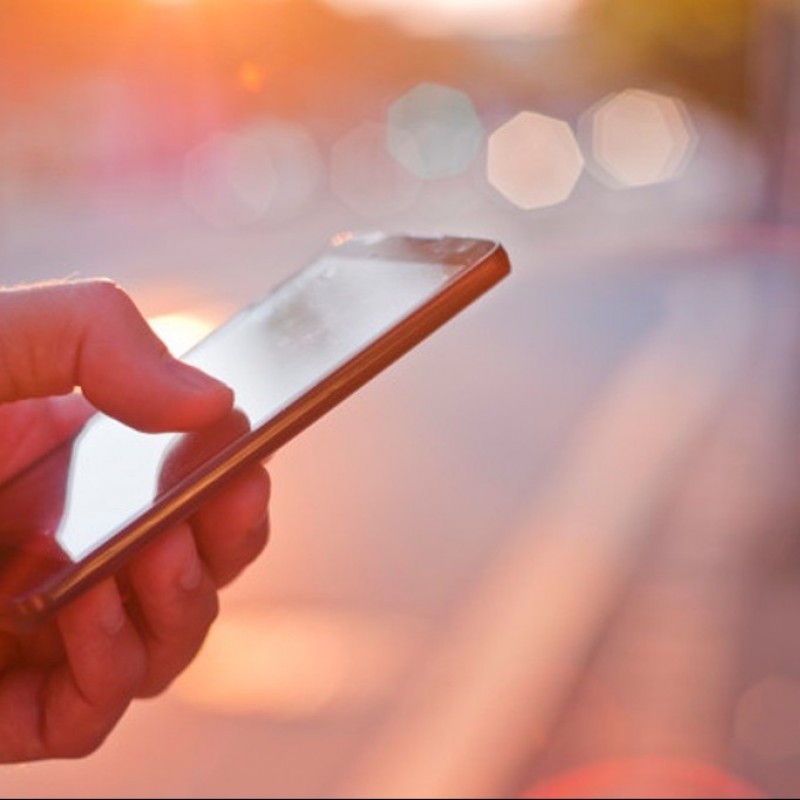Bolehkah Menjual Tanah yang Dijadikan Jaminan Kredit di Perbankan?
NU Online · Selasa, 13 Oktober 2020 | 16:30 WIB

Ketika seorang nasabah mengajukan kredit, umumnya pihak perbankan meminta sebuah aset untuk dijadikan sebagai jaminan. Apa status barang jaminan ini secara fiqih?
Muhammad Syamsudin
Kolomnis
Mungkin pembaca sering menemui kasus atau keraguan tentang boleh tidaknya menjual tanah yang sudah menjadi jaminan kredit di perbankan. Dan salah satunya adalah penanya yang mengirimkan surat elektronik ke penulis.
Sebelum kita masuk ke analisis hukum, ada baiknya kita mencermati terlebih dulu sejumlah alasan yang dijadikan latar belakang (awjah) para nasabah tersebut dalam menjual tanah atau aset lain yang sudah dijadikan penjaminan kredit terhadap perbankan.
Berdasarkan hasil penelusuran dari beberapa jurnal penelitian, peneliti mendapati adanya beberapa motif penjualan aset jaminan ini oleh nasabah, antara lain:
- Harga tanah yang dijadikan jaminan lebih mahal dari uang yang dipinjam konsumen dari bank
- Jika tanah itu diserahkan begitu saja (disita) oleh pihak perbankan, maka konsumen lebih banyak kehilangan harta dibanding jika tanah itu dijual sendiri olehnya, lalu hasil penjualannya dipergunakan untuk menutup/melunasi utangnya.
- Terkadang ada motif kejahatan, misalnya pelaku hendak lari dari tanggung jawab melunasi kewajibannya terhadap perbankan. Itu sebabnya, dalam lembar hukum positif negara terdapat pasal tentang fidusia yang berperan untuk menjerat para nasabah yang mangkir.
Dari ketiga ketiga alasan ini, motif terakhir merupakan praktik yang secara jelas hukumnya: tidak diperbolehkan dalam syariat, sebab unsur penggelapan (tadlis).
Adapun untuk motif pertama dan motif kedua, dalam hal ini kita akan coba uraikan dengan mempertimbangkan sisi akad yang dibangun antara nasabah kredit terhadap perbankan lewat akad relasi akad yang berlaku atas perkreditan tersebut.
Status Barang Jaminan Kredit Perbankan
Ketika seorang nasabah mengajukan kredit perbankan, maka umumnya pihak perbankan meminta sebuah aset untuk dijadikan sebagai jaminan. Hal semacam ini umum berlaku dalam beberapa perbankan konvensional.
Jika dalam perbankan syariah, keberadaan aset ini sebagai yang dibeli dulu oleh perbankan dengan praktik akad jual beli dengan janji akan dibeli lagi oleh penjualnya. Akad yang dipergunakan adalah akad bai’ bi al-wafa. Disebut bai’ bi al-wafa, karena akad ini identik dengan jual beli terhadap objek yang dijadikan jaminan pelunasan kredit.
Jika nasabah berhasil melunasi tanggungannya, maka barang yang dijadikan jaminan kembali kepada penjualnya. Namun, sebaliknya, jika nasabah tidak bisa melunasi utangnya, maka pihak kreditur (perbankan) bisa melelang aset yang sudah dibelinya untuk menutup utang nasabah, yang sejatinya telah berubah menjadi aset perbankan itu sendiri, sebab sudah dibeli. Akan tetapi, yang dibutuhkan oleh perbankan (selaku pelaksana jasa keuangan) adalah tidak berupa barang.
Setiap perbankan senantiasa membutuhkan aset dalam bentuk likuiditas, yaitu aset yang mudah dicairkan. Dan keberadaan aset ini harus ada dalam bentuk uang, dan tidak dalam bentuk barang.
Jika mencermati bagaimana akad bai’ bi al-wafa’ ini dilaksanakan, maka sejatinya kita bisa menangkap pesan bahwa seolah objek barang yang menjadi perantara antara nasabah dan perbankan tersebut, hakikatnya adalah termasuk jaminan kepercayaan atas dilunasinya utang (tautsiqah). Alhasil, dalam versi Syafi’iyah, akad bai’ bi al-wafa’ ini sebenarnya merupakan turunan dari akad gadai. Bolehlah kita sebut sebagai rahn hukman (secara substansi serupa gadai).
Meskipun pelaksanaannya melewati proses akad jual beli, namun karena hukum kepemilikan sempurnanya (milkun tamm) memiliki keeratan relasi dengan penebusan (pelunasan utang/wafa’u al-dain), maka secara tidak langsung akad tersebut adalah akad rahn (gadai).
Alhasil, barang jaminan kredit itu menempati derajat barang yang digadaikan (marhun). Sebagai barang gadai, maka segala ketentuan yang berlaku atasnya adalah mengikuti akad gadai (rahn)/versi Syafiiyah.
Hal-Hal yang berlaku atas Barang Gadai
Gadai, secara syara’ didefinisikan sebagai:
جعل عين مالية وثيقة بدين يستوفى منها عند تعذر الوفاء
“Menjadikan suatu barang fisik hartawi sebagai akad jaminan kepercayaan atas suatu utang yang akan dilunasi dengannya ketika pihak yang berutang merasa kesulitan untuk melunasinya” (Fathu al-Qarib al-Mujib, juz 1, halaman 172)
Oleh karena fisik barang tersebut berlaku sebagai jaminan pelunasan atas suatu utang, maka menjual barang jaminan hukumnya adalah tidak sah.
فبيع المرهون بغير إذن المرتهن لا يصح
“Menjual barang gadai tanpa seizin pihak pegadaian hukumnya adalah tidak sah” (al-Bayan fi al-Fiqh al-Imam Al-Syafi’i, jilid 6, h. 166)
Bagaimana jika utang itu lebih kecil dari harga barang yang digadaikan?
Al-Umrany menyampaikan:
وإن كان الدين المرهون به أقل من قيمة الرهن بيع من الرهن بقدر دين المرتهن، وكان للبائع أن يرجع في الباقي منها؛ لأنه لا حق لأحد فيما بقي منها، وإن لم يمكن بيع بعض الرهن بحق المرتهن إلا ببيع جميع الرهن، فبيع جميع الرهن وقضي حق المرتهن من ثمن الرهن، وبقي من الثمن بعضه
“Apabila utang gadai lebih kecil dari harga barang gadai itu sendiri, maka barang gadai dijual menurut kadar utang penggadai kepada pegadaian. Penjual bisa meminta kembali sisa dari hasil penjualan dikurangi utangnya, karena sisa tersebut tidak ada hak bagi seorang pun yang boleh menerima. Dan apabila pegadaian tidak mungkin untuk menjual sebagian dari barang yang digadaikan melainkan harus dijual semuanya, maka barang itu boleh untuk dijual seluruhnya, lalu pegadaian mengambil hak pemenuhan utangnya dari sebagian harga barang gadai itu, sehingga tersisa sebagian yang lain dari sisa penjualan yang diberikan kepada pihak penggadai” (al-Bayan fi al-Fiqh al-Imam Al-Syafi’i, jilid 6, h. 166).
Meski demikian, pendapat ini muaranya tetap sama, yaitu barang jaminan utang (barang gadai) adalah tidak sah dijual tanpa seizin pihak pegadaian (perbankan). Apabila hal itu dilakukan, maka pihak pegadaian/perbankan bisa mengambil kembali barang yang digadaikan secara paksa, khususnya apabila pihak penggadai (nasabah) mangkir dari kewajibannya melunasi utangnya.
Sebab, penjualan barang gadai (barang jaminan utang) tanpa seizin pihak bank adalah tidak sah (batal). Dengan kata lain, adanya jual beli adalah sama dengan tidak adanya (wujuduhu ka’adamihi).
Lain halnya, apabila setelah transaksi penjualan, kemudian pihak penggadai (nasabah kredit) segera melunasi utangnya di perbankan. Alasannya, ada atau tidak adanya penjualan barang jaminan oleh nasabah, pada akhirnya barang itu akan dijual juga oleh pihak pegadaian (bank) khususnya bila terjadi keterlambatan pelunasan.
Penjualan barang gadai yang harganya lebih mahal dibanding utang gadai yang diterima pihak nasabah, menjadi satu alasan bahwa sebagian dari barang tersebut adalah masih milik sempurna nasabah. Akan tetapi, karena barang itu merupakan barang milik bersama antara nasabah dan pegadaian, maka penjualan seluruhnya adalah dibolehkan, namun dengan catatan, pihak nasabah harus segera menutup tanggungannya di bank. Bila tidak, maka pihak perbankan bisa membatalkan akad jual belinya, mengingat secara fisik, barang tersebut telah dijadikan jaminan. Wallahu a’lam bish shawab.
Muhammad Syamsudin, S.Si., M.Ag, Peneliti Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU Jawa Timur
Terpopuler
1
Inilah Niat Puasa Asyura Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
2
10 Muharram Waktu Terjadinya 7 Peristiwa Penting Para Nabi
3
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
4
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
5
Doa-Doa Pilihan di Hari Asyura, Dapat Hindarkan dari Matinya Hati
6
Khutbah Jumat: Keistimewaan Berbakti Kepada Kedua Orang Tua
Terkini
Lihat Semua