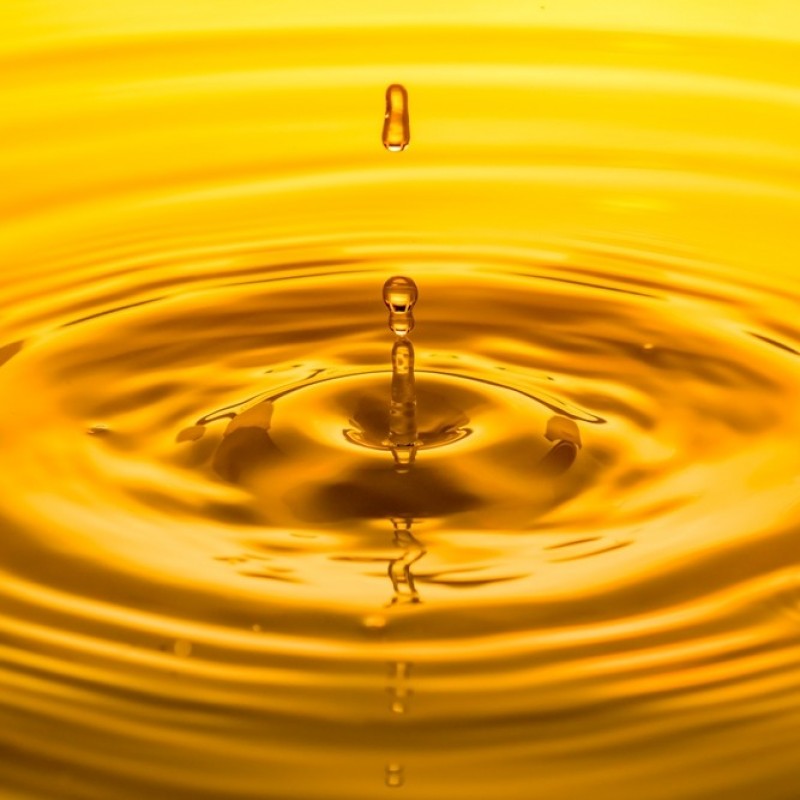Menahan-nahan supaya Tidak Batal Wudhu, Benarkah Sikap Itu?
NU Online · Selasa, 30 Juni 2020 | 08:00 WIB
Muhammad Ishom
Kolomnis
Nggantung wudhu adalah istilah yang biasa kita dengar untuk merujuk seseorang bahwa ia menjaga wudhunya agar tidak batal akibat hadats kecil yang dialaminya. Hadats kecil bisa karena telah buang hajat seperti kencing dan buang air besar, kentut, tidur, bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan mahram, dan sebagainya.
Terkadang terjadi orang-orang yang membiasakan diri nggantung wudhu bersikap canggung dalam interaksinya dengan lawan jenis yang bukan mahram termasuk suami/istrinya sendiri. Nggantung wudhu adalah baik selama dilakukan secara wajar, namun dalam kasus-kasus tertentu bisa kurang baik. Misalnya, seorang istri atau suami yang sedang nggantung wudhu merasa tidak nyaman ketika pasangan hidupnya mendekat padanya. Seketika ia mengambil jarak agar wudhunya tidak batal dengan menghindari persentuhan kulit dengan pasangannya.
Dalam memberikan layanan kepada pasangan hidup seperti mengambilkan makanan atau lainnya, seorang istri atau suami kadang melakukannya setengah hati karena khawatir wudhunya akan batal jika terjadi persentuhan kulit. Sikap seperti ini bisa menjauhkan kehangatan hubungan antara suami/istri dengan pasangan hidupnya. Padahal bersikap hangat dan romantis terhadap pasangan hidup merupakan hal yang dilakukan Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam.
Kasus lain, misalnya, seorang penjual di sebuah toko bersikap caggung dalam memberikan susuk/jujul (uang kembalian) kepada pembeli karena khawatir akan batal wudhunya akibat persentuhan kulit dengan lawan jenis. Uang kembalian ia serahkan kepada pembeli dengan tangan yang ceikthang-cekithing (ditahan-tahan antara “iya” dengan “tidak”) seolah-olah tangan sang pembeli terdapat najis yang harus dihindari. Secara fiqih hal ini bisa dipahami tetapi secara akhlak tentu kurang baik karena terkesan kurang ramah dalam melayani pembeli. Apalagi ada adagium bahwa pembeli adalah raja yang harus dilayani dan dihormati dengan baik.
Secara fiqih sikap-sikap seperti itu bisa dipahami, tetapi secara akhlak tentu kurang baik karena terkesan kurang sopan atau kurang hangat dalam bermuamalah kepada pasangan hidupnya. Suami-istri sangat dianjurkan untuk saling membantu dan melayani secara wajar sebagai wujud cinta kasih dan tanggung jawab masing-masing atas pasangannya.
Pertanyaannya, seperti apakah makna yang benar menjaga wudhu atau nggantung wudhu itu? Apakah dengan menjaga diri dari hadats kecil agar tidak batal wudhunya dalam jangka lama sebagaimana umumnya dipahami banyak orang selama ini? Ataukah ada makna lain yang lebih sesuai dan wajar dilihat dari segi akhlak dan kesehatan?
Pertanyaan itu bisa ditemukan jawabannya dalam kitab karangan Allamah Sayyid Abdullah bin Alawi al-Haddad berjudul Risâlatul Mu‘âwanah wal Mudzâharah wal Muwâzarah (Dar Al-Hawi, 1994, hal. 79-80) yang menasihatkan tentang pentingnya pembiasaan memperbarui wudhu dalam rangka memelihara kebersihan lahir dan batin sebagai berikut:
ـ(وعليك) بتجديد الوضوء لكل فريضة واجتهد أن لا تزال على طهارة، وجدد الوضوء كلما أحدثت؛ فإن الوضوء سلاح المؤمن ومتى كان السلاح حاضراً لم يتجاسر العدو على الدنو منك.
Artinya: “Hendaknya Anda membiasakan memperbarui wudhu setiap kali shalat fardhu. Usahakanlah Anda selalu dalam keadaan suci (berwudhu). Perbaruilah wudhu Anda setiap kali berhadats (batal wudhu), sebab wudhu adalah senjata orang mukmin. Selama senjata itu siap, tak seorang musuh pun berani mendekat.”
Dari kutipan di atas, dapat diketahui bahwa kita dianjurkan untuk senantiasa memperbarui wudhu setiap kali wudhu kita batal karena alasan apapun. Ini artinya kita bukan dianjurkan untuk menjaga wudhu atau nggantung wudhu dengan cara menahan diri agar tidak batal dalam rentang waktu lama. Menahan seperti ini sesungguhnya tidak baik karena dapat mengganggu kesehatan. Misalnya, menahan kencing dalam waktu lama dapat mengakibatkan infeksi saluran kencing. Menahan buang air besar dapat mengakibatkan pembesaran usus yang berdampak buruk pada jantung, dan sebagainya.
Dalam hubungannya dengan akhlak bermuamalah, nggantung wudhu dapat mempengaruhi interaksi kita dengan orang lain termasuk terhadap suami/istri kita sendiri sebagaimana telah disinggung di atas. Nggantung wudhu memang kedengarannya baik tetapi sebetulnya bermasalah sebab bisa mengurangi keintiman dan kehangatan terhadap pasangan hidup. Padahal keintiman dan kehangatan sangat penting untuk menjaga keharmonisan hubungan suami-istri. Kedua hal ini lebih besar manfaatnya dari pada upaya kita untuk sekedar nggantung wudhu yang ternyata hal ini tidak memiliki dasar yang kuat.
Sebagaimana telah disebutkan dalam kutipan di atas, Sayyid Abdullah al-Haddad juga menyatakan bahwa wudhu adalah senjata orang mukmin. Selama senjata itu siap, tak seorang musuh pun berani mendekat. Maka ibarat pedang, barang siapa sering berwudhu berarti ia sering mengasah pedangnya sehingga senjata itu sangat tajam dan menakutkan. Apalagi dalam keadaan terhunus, tentu setan-setan tidak akan berani mendekat. Demikian pula manusia-manusia pengikut setan juga tidak akan berbuat macam-macam kepadanya karena setan sebagai sumber godaan tidak berani membujuk mereka.
Sedemikian besar manfaat pembiasaan memperbarui wudhu dalam kaitannya dengan kesucian dan perlindungan diri dari setan, maka orang yang hendak melaksanakan shalat fardhu dianjurkan memperbarui wudhunya meski belum batal. Orang shalat menahan kentut dengan alasan apa pun, misalnya supaya tetap nggantung wudhu hukumnya makruh sebab bisa mengganggu pikiran atau kekhusyukan dalam shalatnya. Ia justru sebaiknya melepaskan kentutnya di tempat yang tepat, lalu segera memperbarui wudhunya.
Jadi yang sebaiknya kita lakukan dalam kaitannya dengan wudhu adalah pembiasaan memperbarui wudhu setiap kali batal dan bukannya menjaga diri dengan cara menahan-nahan supaya tetap nggantung wudhu. Inilah makna yang lebih tepat dalam kaitannya dengan anjuran untuk selalu menjaga diri dari hadats kecil.
Muhammad Ishom, dosen Fakultas Agama Islam Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta.
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Meraih Keutamaan Bulan Muharram
2
Koordinator Aksi Demo ODOL Diringkus ke Polda Metro Jaya
3
5 Fadilah Puasa Sunnah Muharram, Khusus Asyura Jadi Pelebur Dosa
4
Khutbah Jumat: Memaknai Muharram dan Fluktuasi Kehidupan
5
Khutbah Jumat: Meraih Ampunan Melalui Amal Kebaikan di Bulan Muharram
6
5 Doa Pilihan untuk Hari Asyura 10 Muharram, Lengkap dengan Latin dan Terjemahnya
Terkini
Lihat Semua