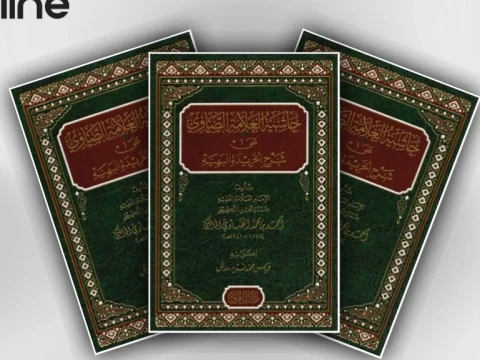Makkah hari ini adalah pusat spiritual umat Islam dunia. Ka’bah berdiri sebagai poros peribadatan global, mengikat jutaan manusia dalam satu arah dan satu tujuan penghambaan. Kota ini identik dengan keteraturan ritual, kesucian ruang, dan disiplin tauhid.
Namun, gambaran itu sepenuhnya berbeda jika kita menengok Makkah sebelum kelahiran Islam. Pada fase pra-Islam, Makkah adalah kota dengan lanskap keagamaan yang cair, bercampur, bahkan kontradiktif. Tauhid masih dikenal, tetapi tidak lagi murni. Warisan Nabi Ibrahim tetap dijaga, namun bercampur dengan praktik-praktik keagamaan yang menyimpang.
Sejarawan Muslim mencatat, masyarakat Makkah sesungguhnya berangkat dari ajaran hanifiyah, agama tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim dan diwariskan melalui Nabi Ismail. Akan tetapi, seiring berlalunya generasi, ajaran itu mengalami distorsi.
Syekh Muhammad Sa’id Ramadhan al-Buthi menggambarkan proses ini sebagai hukum sejarah yang berulang: ketika jarak zaman memanjang, kebodohan merayap, dan para pembuat mitos mengambil alih ruang keagamaan, maka kebenaran bercampur dengan kebatilan.
Dari proses panjang inilah lahir apa yang dikenal sebagai masa jahiliyah. Sebuah fase ketika masyarakat Makkah hidup dalam keragaman keyakinan yang secara bertahap menjauh dari tauhid. Setidaknya, terdapat empat corak kepercayaan utama yang hidup berdampingan di Makkah pra-Islam.
Simak penjelasan Syekh Ramadhan al-Buthi berikut:
فلما امتدت بهم القرون وطال عليهم الأمد، أخذوا يخلطون الحق الذي توارثوه بكثير من الباطل الذي تسلل إليهم، شأن سائر الأمم والشعوب عندما يغشاها الجهل ويبعد بها العهد ويندسّ بين صفوفها المشعوذون والمبطلون. فدخل فيهم الشرك واعتادوا عبادة الأصنام وتسللت إليهم التقاليد الباطلة والأخلاق الفاحشة، فابتعدوا بذلك عن ضياء التوحيد وعن منهج الحنيفية وعمت بينهم الجاهلية التي رانت عليهم أمدا من الدهر، ثم انقشعت عنهم ببعثة محمد عليه الصلاة والسلام
Artinya: “Ketika generasi demi generasi terus berlalu dan masa yang panjang menimpa mereka, mereka mulai mencampuradukkan kebenaran yang mereka warisi dengan banyak kebatilan yang menyusup ke dalam kehidupan mereka. Hal itu sebagaimana terjadi pada umat dan bangsa lain ketika kebodohan meliputi mereka, jarak zaman semakin jauh, dan para dukun serta pembawa kesesatan menyelinap di tengah-tengah mereka. Maka masuklah kemusyrikan di kalangan mereka, mereka pun terbiasa menyembah berhala.
Tradisi-tradisi batil dan akhlak-akhlak yang keji pun meresap ke dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, mereka menjauh dari cahaya tauhid dan dari manhaj agama yang lurus (hanif), lalu merajalelalah di tengah mereka masa jahiliah yang menutupi mereka dalam waktu yang sangat lama. Kemudian semua itu tersingkap dengan diutusnya Muhammad.” (Al-Buthi, Fiqhus Sirah, [Damaskus: Darul Fikr, 1426H] hal. 37)
4 Kepercayaan Masyarakat Makkah Pra-Islam
1. Menyembah Berhala
Rapuhnya pegangan terhadap tauhid menjadi celah awal masuknya penyimpangan teologis di Makkah. Ketika ajaran hanif yang diwariskan Nabi Ibrahim tidak lagi dipahami secara utuh, masyarakat menjadi mudah menerima praktik keagamaan baru, meski bertentangan dengan prinsip keesaan Tuhan.
Sejarah mencatat, penyembahan berhala di Makkah tidak lahir dari keresahan massa, melainkan dari inisiatif seorang tokoh elite Quraisy: Amr bin Luhay. Ia dikenal sebagai figur terpandang, pemilik wibawa sosial, dan rujukan keagamaan. Justru karena otoritas itulah, langkah-langkahnya kelak membawa dampak luas.
Dalam sebuah perjalanan ke wilayah Syam, Amr menyaksikan kaum ‘Amaliq memuja patung-patung yang mereka yakini memiliki kekuatan supranatural, mendatangkan hujan, memberi kemenangan, dan menjamin kemakmuran. Bagi Amr, praktik itu tidak tampak sebagai kesesatan, melainkan sebagai bentuk religiositas yang sah. Syam, bagaimanapun, dipandang sebagai tanah para nabi.
Ibnu Hisyam meriwayatkan bagaimana Amr, dengan penuh keyakinan, meminta sebuah berhala untuk dibawa ke tanah Arab. Permintaan itu dikabulkan. Sebuah patung bernama Hubal diboyong ke Makkah, ditegakkan, lalu dipromosikan sebagai sesembahan. Dari satu patung itulah, sebuah tradisi baru bermula.
Keputusan Amr tidak berdiri sendiri. Ia diterima, ditiru, dan dilembagakan. Ka’bah, yang semula menjadi simbol tauhid, perlahan dipenuhi berhala. Setiap kabilah menghadirkan sesembahannya sendiri. Penyembahan patung pun menjadi praktik umum, diwariskan lintas generasi, dan akhirnya dianggap sebagai bagian dari agama leluhur.
Kisah ini memperlihatkan satu pelajaran penting dalam sejarah agama: penyimpangan sering kali tidak datang melalui penolakan terhadap Tuhan, melainkan melalui reinterpretasi yang keliru tentang cara mendekat kepada-Nya. Dari Makkah pra-Islam, sejarah mencatat bahwa berhala pertama tidak ditegakkan oleh orang awam, melainkan oleh mereka yang dipercaya memahami agama.
Simak penjelasan Ibnu Hisyam berikut:
قال ابن هشام: حدثني بعض أهل العلم: أن عمرو بن لحي خرج من مكة إلى الشام في بعض أموره، فلما قدم مآب من أرض البلقاء، وبها يومئذ العماليق وهم ولد عملاق ويقال عمليق بن لاوذ بن سام بن نوح، رآهم يعبدون الأصنام، فقال لهم: ما هذه الأصنام التي أراكم تعبدون؟ قالوا له: هذه أصنام نعبدها، فنستمطرها فتمطرنا، ونستنصرها فتنصرنا، فقال لهم: أفلا تعطونني منها صنما، فأسير به إلى أرض العرب، فيعبدوه؟ [١] فأعطوه صنما يقال له هبل، فقدم به مكة، فنصبه وأمر الناس بعبادته وتعظيمه
Artinya: “Ibnu Hisyam berkata: telah menceritakan kepadaku sebagian ahli ilmu, bahwa ‘Amr bin Luhay keluar dari Makkah menuju Syam untuk suatu keperluannya. Ketika ia tiba di Ma’ab, sebuah wilayah di negeri Balqa’, yang pada waktu itu dihuni oleh kaum ‘Amaliq, keturunan ‘Imlaq, dan ada yang mengatakan ‘Imliq bin Laudz bin Sam bin Nuh, ketika itu ‘Amr melihat mereka menyembah berhala.
Ia pun berkata kepada mereka, “Apakah berhala-berhala yang aku lihat kalian sembah ini?” Mereka menjawab, “Ini adalah berhala-berhala yang kami sembah. Kami memohon hujan kepadanya, lalu hujan pun turun kepada kami. Dan kami memohon pertolongan kepadanya, maka ia memberi kami pertolongan.”
Ia berkata kepada mereka, “Tidakkah kalian memberikan kepadaku satu berhala darinya, agar aku membawanya ke negeri Arab sehingga mereka menyembahnya?” Maka mereka pun memberinya sebuah berhala yang bernama Hubal. Ia lalu membawanya ke Makkah, menegakkannya, dan memerintahkan manusia untuk menyembah serta mengagungkannya.” (Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam, [Mesir, Maktabah al-Babiy, 1375H], jilid 1, hal. 77)
2. Mengagungkan Batu Kerikil
Selain menyembah patung berhala, masyarakat Makkah pra-Islam juga menaruh kesakralan pada batu dan kerikil. Praktik ini sekilas tampak sederhana, bahkan nyaris remeh. Namun justru dari kebiasaan inilah kita melihat bagaimana sebuah simbol penghormatan dapat berubah menjadi objek pemujaan.
Ibnu Ishaq mencatat bahwa tradisi ini berawal dari sikap hormat terhadap Tanah Haram. Orang-orang Makkah yang bepergian ke luar kota untuk berdagang atau mencari penghidupan membawa sebongkah batu dari sekitar Ka‘bah. Batu itu menjadi penanda ikatan batin dengan pusat ibadah yang mereka tinggalkan.
Setibanya di tempat singgah, batu tersebut diletakkan dengan penuh hormat. Mereka lalu mengelilinginya sebagaimana thawaf di sekitar Ka‘bah. Pada tahap ini, batu belum disembah. Ia hanya simbol, pengganti sementara bagi Ka‘bah yang jauh dari jangkauan.
Namun, sejarah jarang berhenti pada niat awal. Kebiasaan itu berlangsung lintas generasi, dan maknanya pun bergeser. Batu tidak lagi sekadar pengingat, melainkan mulai diperlakukan sebagai pusat ritual. Bahkan, kesakralan tidak lagi dibatasi pada batu dari Tanah Haram. Batu apa pun yang dianggap indah atau mengagumkan dapat diangkat menjadi objek pemujaan.
Pergeseran generasi mempercepat distorsi makna. Generasi berikutnya melupakan asal-usul tradisi ini dan kehilangan kesadaran tauhid yang dulu menjadi landasannya. Yang tersisa hanyalah ritual tanpa ingatan sejarah.
Pada titik inilah ajaran lurus Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tergantikan oleh praktik-praktik baru yang menyimpang. Benda mati mengambil alih ruang sakral, dan penyembahan terhadap simbol menggeser penghambaan kepada Tuhan. Dalam lanskap keagamaan Makkah pra-Islam, batu dan kerikil pun menjadi bagian tak terpisahkan dari ritual sehari-hari—sebuah pelajaran sejarah tentang betapa mudahnya kesalehan simbolik menjelma menjadi kesesatan teologis. (Ibnu Hisyam, Sirah Ibnu Hisyam, hal. 77).
3. Yahudi dan Nasrani
Tidak berhenti pada praktik penyembahan berhala dan batu, lanskap keagamaan Makkah pra-Islam juga diwarnai oleh keberadaan komunitas Ahlulkitab, baik Yahudi maupun Nasrani.
Sebagian dari mereka masih berpegang pada ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, serta memiliki pengetahuan keagamaan yang bersumber dari kitab-kitab suci mereka. Dalam tradisi tersebut, para pendeta dan rahib bahkan diyakini telah mengenal ciri-ciri serta masa kemunculan seorang nabi akhir zaman dari bangsa Arab.
Pengetahuan inilah yang membuat mereka kerap menyampaikan kabar akan datangnya seorang nabi bernama Ahmad yang membawa ajaran tauhid Nabi Ibrahim. Sebagaimana ditegaskan dalam kutipan tersebut, keyakinan itu tidak hanya tersimpan dalam teks kitab mereka, tetapi juga menjadi dasar sikap dan wacana keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Baihaqi yang bersumber dari Ibnu Ishaq:
وكانت الأحبار والرهبان من أهل الكتابين، هم أعلم برسول الله، صلى الله عليه وآله وسلم، قبل مبعثه، وبزمانه الذي يترقب فيه- من العرب، لما يجدونه في كتبهم من صفته، وما أثبت فيما عندهم من اسمه، وبما أخذ عليهم من الميثاق له، في عهد أنبيائهم وكتبهم، في اتباعه، فيستفتحون به على أهل الأوثان من أهل الشرك، ويخبرونهم أن نبيا يبعث [ (1) ] بدين إبراهيم عليه السلام اسمه: أحمد، صلى الله عليه وآله وسلم، يجدونه كذلك في كتبهم، وعهد أنبيائهم.
Artinya: “Dari Ibnu Ishaq, ia berkata: para pendeta dan rahib dari kalangan Ahli Kitab merupakan pihak yang paling mengetahui tentang Rasulullah sebelum beliau diutus, termasuk masa kemunculannya yang dinantikan dari kalangan bangsa Arab, karena mereka menemukan keterangan tentang sifat-sifat beliau, penetapan namanya, serta perjanjian untuk mengikutinya dalam kitab-kitab mereka dan dalam ajaran para nabi mereka; dengan pengetahuan itu mereka meminta kemenangan atas para penyembah berhala dari kalangan kaum musyrik dan memberitakan bahwa akan diutus seorang nabi yang membawa agama Ibrahim As bernama Ahmad, sebagaimana mereka dapati keterangan tersebut dalam kitab-kitab dan perjanjian para nabi mereka.” (Al-Baihaqi, Dalailun Nubuwwah, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyah, 1405H], jilid 2, hal. 74)
4. Mengagungkan Malaikat
Selain berhala dan benda-benda mati, sebagian masyarakat Makkah pra-Islam juga terjerumus pada keyakinan kosmologis yang lebih subtil namun tak kalah problematis. Mereka membayangkan adanya hubungan kekerabatan antara Allah dan bangsa jin, sebuah imajinasi teologis yang lahir dari pencampuran mitologi lokal dengan konsep ketuhanan.
Dalam keyakinan itu, Allah digambarkan memiliki pasangan dari kalangan jin perempuan. Dari hubungan inilah, menurut mereka, lahirlah para malaikat yang dianggap berjenis kelamin perempuan. Al-Qur’an merekam dan sekaligus membantah keyakinan ini dalam Surat Ash-Shaffat ayat 158:
وَجَعَلُوْا بَيْنَهٗ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَبًاۗ وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ اِنَّهُمْ لَمُحْضَرُوْنَۙ ١٥٨
Artinya; Mereka menjadikan (hubungan) nasab antara Dia dan jin. Sungguh, jin benar-benar telah mengetahui bahwa mereka (kaum musyrik) pasti akan diseret (ke neraka),
Para mufasir menjelaskan bahwa istilah jin dalam ayat ini tidak merujuk pada makhluk yang dikenal dalam pengertian umum, melainkan kepada malaikat, disebut demikian karena sifat mereka yang tidak kasat mata.
Wahbah az-Zuhaili mencatat bahwa kaum musyrik, khususnya dari kabilah Kinanah dan Khuza‘ah, meyakini malaikat sebagai anak-anak perempuan Allah. Keyakinan itu dibungkus dengan kisah mitologis: Allah dilukiskan melamar para pemimpin jin, lalu dinikahkan dengan perempuan-perempuan terbaik dari kalangan mereka.
(وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجِنَّةِ نَسَباً) أي جعل المشركون بين الله وبين الجن وهم هنا الملائكة صلة نسب، فقالوا: الملائكة بنات الله، وسموا جنا لإجتنانهم واستتارهم عن الأبصار. والقائل بهذه المقالة كنانة وخزاعة، قالوا: إن الله خطب إلى سادات الجن، فزوجوه من سروات بناتهم، فالملائكة بنات الله من سروات بنات الجن، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا.
Artinya: “(Dan mereka menjadikan antara Dia (Allah) dan antara jin suatu hubungan nasab) maksudnya, kaum musyrik beranggapan adanya hubungan kekerabatan antara Allah dan jin, yang dimaksud dengan jin di sini adalah para malaikat. Mereka mengatakan bahwa malaikat adalah anak-anak perempuan Allah. Para malaikat disebut jin karena sifat mereka yang tersembunyi dan tidak tampak oleh penglihatan mata.
Pihak yang mengemukakan keyakinan ini adalah kabilah Kinanah dan Khuza‘ah. Mereka beranggapan bahwa Allah melamar kepada para pemimpin jin, lalu para pemimpin tersebut menikahkan-Nya dengan perempuan-perempuan terbaik dari kalangan putri mereka. Maka, menurut anggapan itu, para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah yang berasal dari putri-putri terbaik bangsa jin. Mahasuci Allah dan Maha Tinggi Dia dari segala yang mereka katakan dengan ketinggian yang setinggi-tingginya.” (Az-Zuhaili, Tafsirul Munir, [Damaskus, Darul Fikr, 1991] jilid 23, hal. 150).
Keyakinan semacam ini memperlihatkan bagaimana konsep ketuhanan diperlakukan secara antropomorfis, Tuhan digambarkan dengan relasi biologis layaknya manusia. Dalam konstruksi semacam itu, malaikat tidak lagi dipahami sebagai makhluk yang tunduk sepenuhnya kepada kehendak Tuhan, melainkan sebagai entitas keluarga ilahi yang memiliki kedudukan khusus.
Islam datang untuk membongkar imajinasi teologis ini dari akarnya. Al-Qur’an menegaskan kemahasucian Allah dari segala bentuk nasab, relasi biologis, dan pembagian jenis kelamin. Dengan penegasan tersebut, Islam memutus rantai mitologi yang menjerat keimanan masyarakat Makkah dan mengembalikan konsep ketuhanan pada kemurnian tauhid.
Dari keyakinan ini, sejarah memberi pelajaran penting: ketika akal religius kehilangan disiplin wahyu, maka Tuhan tidak lagi dipahami sebagaimana adanya, melainkan dibentuk sesuai imajinasi manusia sendiri.
Kepercayaan masyarakat Makkah sebelum Islam memperlihatkan sebuah lanskap keagamaan yang kompleks dan berlapis. Tauhid warisan Nabi Ibrahim masih dikenali, namun tidak lagi dipahami secara utuh. Di sekelilingnya tumbuh beragam praktik dan keyakinan, dari penyembahan berhala dan pengagungan benda-benda alam, hingga konstruksi kosmologis tentang malaikat.
Dalam konteks sejarah, kondisi inilah yang menjadi latar sosial dan keagamaan bagi kemunculan Islam. Kehadiran Islam tidak muncul di ruang hampa, tetapi berinteraksi dengan keyakinan-keyakinan yang telah hidup sebelumnya, meluruskan, menata ulang, dan memberi arah baru bagi kehidupan keagamaan masyarakat Makkah.
------------
Muhaimin Yasin, Alumnus Pondok Pesantren Ishlahul Muslimin Lombok Barat dan Pegiat Kajian Keislaman