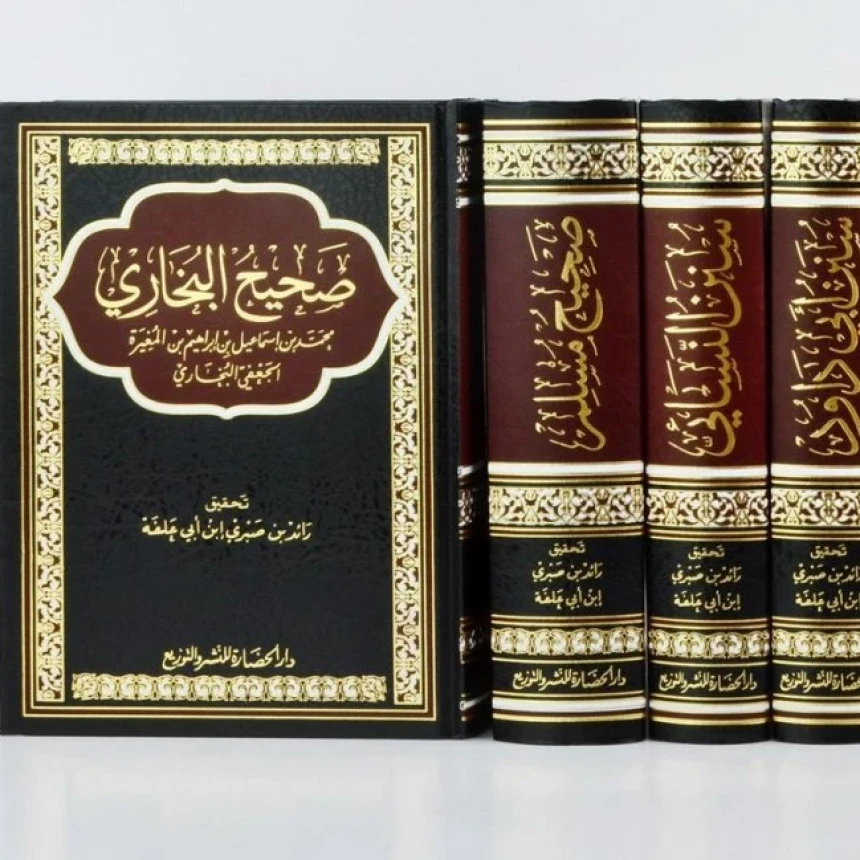Amien Nurhakim
Penulis
Hadits bagi umat muslim sangatlah penting eksistensinya. Di masa sekarang, umat Islam sering bertanya soal ‘dalil’ di setiap aktivitas, terutama yang dinilai ibadah, meskipun terkadang sebenarnya yang mereka lihat adalah tradisi dan budaya setempat yang dipadukan dengan ajaran Islam.
Dikarenakan kita sudah memasuki era digital dan pencarian informasi sangat mudah diakses di internet, pada proses penilaian dan justifikasi, tidak jarang kita menemukan hadits-hadits yang dinilai lemah atau dalam istilah ilmu hadits adalah dha’if.
Hadits dha’if merupakan hadits yang belum memenuhi syarat hadits hasan. Hadits hasan sendiri dalam pandangan Ibnu Hajar adalah hadits yang sanadnya bersambung dari satu rawi ke rawi yang lain, para perawinya memiliki sifat ‘adl meskipun sebagian dari mereka kualitas dhabt (kemampuan periwayatan) yang dimiliknya lebih rendah dari perawi shahih, lalu pada sanad maupun matan tidak terdapat syadz (kejanggalan) maupun ‘illat (cacat). (Mahmud ath-Thahhan, Taysir Mushthalahil Hadits, [Riyadh: Maktabah al-Ma’arif, 2004], hal. 58)
Ketika melihat hadits dha’if dalam suatu amalan keuatamaan (fadha’il) atau tradisi keagamaan dan kebudayaan, beberapa orang memilih sikap untuk langsung menolak begitu saja, bahkan sebagian lagi memilih untuk mencaci dan berkata buruk pada orang yang menyampaikan hadits tersebut.
Padahal, boleh jadi redaksi hadits yang dia dengar dan dinilai dha’if memiliki kemungkinan-kemungkinan lain setelah diteliti lebih lanjut. Misalnya, hadits yang ia hukummi dha’if ternyata memang belum pernah ia dengar, sedangkan dalam satu kitab tertentu hadits tersebut dinilai shahih.
Kemungkinan lainnya adalah ternyata ada riwayat-riwayat lain yang lafaznya sama, namun diriwayatkan dari jalur lain, sehingga derajatnya naik menjadi hadits hasan. Atau kemungkinan lainnya, yaitu hadits yang dinilai dha’if tersebut memiliki hadits penguat yang semakna.
Kemungkinan-kemungkinan di atas boleh jadi muncul ketika hadits yang dinilai dha’if diteliti lebih lanjut. Kendati demikian, tidak menutup kemungkinan juga hadits dha’if yang diteliti lebih lanjut juga menampilkan bukti bahwa memang hadits tersebut dha’if, bahkan parah dha’ifnya.
Ahmad bin Hanbal pernah mengatakan kurang lebih “Hadits, selama tidak bertentangan dengan kitab atau sunnah, meskipun tidak diperkuat oleh keduanya (Al-Quran dan hadits), dan jika penafsirannya tidak keluar dari ijma’ umat, maka ia layak diterima dan diamalkan. Bagaimana mungkin hadits dhaif dianggap lebih rendah dari akal dan qiyas?" (Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, [Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004], hal. 161).
Perkataan Ahmad bin Hanbal di atas bukan berarti beliau menolak qiyas sama sekali. Hanya saja, ketika ditemukan adanya sumber lain seperti hadits yang belum diketahui lebih lanjut kualitasnya, maka ia lebih diterima dibandingkan menggunakan qiyas. (Muslim Zainuddin, Konstruksi Pemikiran Hukum Islam Imam Ahmad ibn Hanbal: Pendekatan Sejarah Sosial Hukum Islam, [Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, 2023], hal. 100).
Waki’ bin Jarrah, guru Imam asy-Syafii pernah menuturkan, ”Tidak pantas seseorang [buru-buru] menghukumi hadits [yang ia dapati] bahwa hadits ini batil, sebab hadits lebih banyak [dari yang ia kira]."
Disebutkan dalam suatu kisah, seseorang menyebutkan hadits di hadapan az-Zuhri, kemudian orang itu berkata,
”Kami belum pernah mendengar ini!”
Az-Zuhri berkata, “Apakah semua hadits Rasulullah SAW telah kamu dengar?”
“Tidak.” Jawab orang itu.
Az-Zuhri bertanya lagi, “Apakah dua pertiganya pernah kamu dengar?”
Orang itu menjawab, “Tidak juga.”
Az-Zuhri bertanya lagi, “Apakah setengahnya?”
Orang itu pun terdiam. Az-Zuhri menegurnya, “Anggap saja hadits yang kamu pertanyaakan ini bagian dari hadits yang belum kamu dengar!” (Muhammad Jamaluddin al-Qasimi, Qawa’idut Tahdits, [Beirut: Muassasah ar-Risalah, 2004], hal. 171).
Al-Hasyimi dalam Qowaidut Tahdits halaman 160 menjelaskan, ada 5 sikap yang dapat kita lakukan ketika melihat hadits dha’if, yaitu:
Pertama, tidak langsung meyakini bahwa hadits tersebut adalah pasti palsu. Kedua, boleh jadi si penyampai riwayat menyampaikannya dengan ketulusan tanpa maksud untuk menyebarkan hadits yang lemah, semuanya murni karena ketidaktahuannya.
Ketiga, hadits-hadits yang lemah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadits tidak wajib ditolak, boleh jadi ada indikasi pendukung, baik secara lafaz maupun makna dari hadits-hadits lainnya, atau bahkan dari makna ayat Al-Quran secara general.
Keempat, kita diperintahkan oleh Allah untuk berprasangka baik (husnuzan), dilarang dari banyak berprasangka, dan dilarang banyak berprasangka buruk (su'uzan).
Kelima, kita tidak dapat mencapai kebenaran kecuali melalui pengamatan dan penelitian. Boleh jadi hal itu tidak dapat dilakukan semua orang muslim, sehingga mereka terpaksa mengikuti dan mempercayai dengan prasangka baik atas riwayat-riwayat yang dibawa oleh para perawi.
Sebagai penutup, penting bagi kita untuk bersikap bijak dalam menilai hadits dha'if. Lima sikap yang telah diuraikan dapat menjadi panduan yang cukup berguna di era teknologi digital dalam menghadapi berbagai informasi terkait hadits. Wallahu a’lam
Ustadz Amien Nurhakim, Penulis Keislaman NU Online dan Dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas PTIQ Jakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Menghapus Sekat Sektarian di Tengah Umat
2
Orang Wajib Zakat Fitrah Tapi Juga Boleh Menerima?
3
Kultum Ramadhan: Menjadi Manusia yang Bermanfaat bagi Sesama
4
Perang Iran dan Israel-AS Berdampak Global, Ketua Umum PBNU Desak Perdamaian
5
Standar Ganda Sekutu dalam Perang Israel-AS vs Iran
6
Larangan Menjadikan Orang Meninggal sebagai Bahan Lelucon
Terkini
Lihat Semua