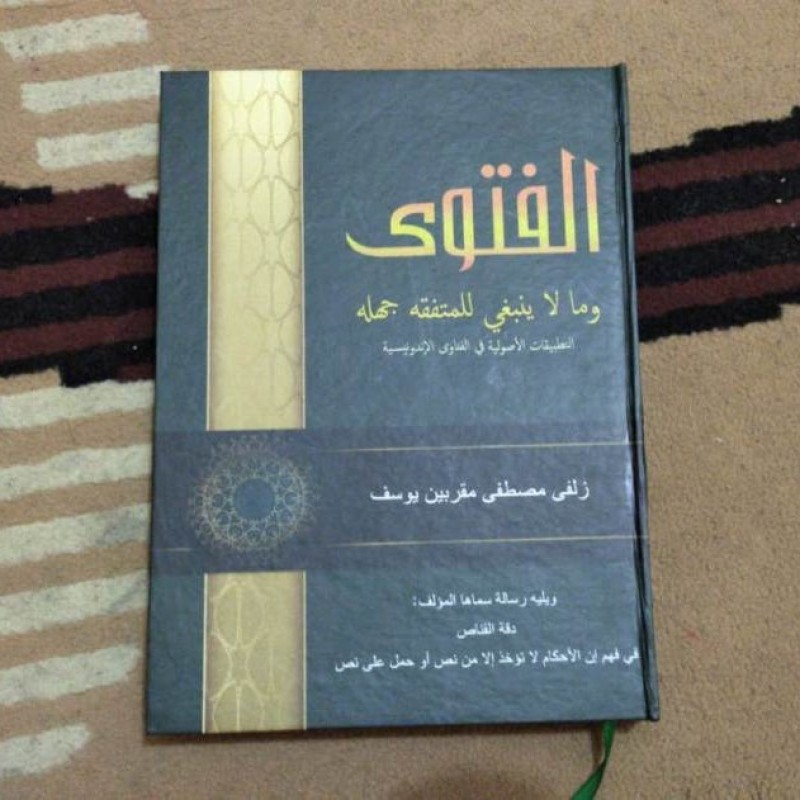Mencabut Fatwa yang Keliru: Sebuah Teladan Kejujuran Intelektual Ulama Terdahulu
NU Online · Kamis, 8 April 2021 | 10:15 WIB

Bila kebetulan salah, sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan kejujuran ilmiah, maka haruslah menarik kembali fatwa tersebut. (reviversgalleria.com)
Ahmad Dirgahayu Hidayat
Kolomnis
Dalam beberapa kesempatan, guru kami di Ma’had Aly Situbondo, KH Afifuddin Muhajir, menyampaikansebuah kaidah bahwa seorang mujtahid boleh salah dalam produk, namun harus benar dalam proses. Seorang ulama dalam kapasitasnya sebagai mujtahid yang menggali hukum, baik min an-nushush(Al-Qur’an dan hadist), maupun min ghairian-nushush(seperti maqashidasy-syari’ah), haruslah merujuk pada kaidah ijtihad di atas.
Kaidah ini berawal dari sebuah hadisttentang ganjaran pahala bagi setiap yang berijtihad. Dua pahala bagi yang ijtihadnya benar, dan satu pahala bagi yang ijtihadnya salah. Setidaknya, pahala karena ia telah berupaya.Itu juga berarti bahwa amal ijtihad merupakan suatu pekerjaan yang mulia. Jangankan kebenaran yang dihasilkan, salah pun tetap diapresiasi.
Isu mutakhir yang membanjiri pelbagai media, baik cetak maupun online, akhir-akhir ini, adalah isu tentang vaksin Covid-19 produk AstraZeneca.Hal ini berawal dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam fatwanya yang dikeluarkan pada (16/3)lalu. Di sana disebutkan, pada bagian kedua tentang ketentuan hukum vaksin AstraZeneca bahwa menggunakannya hukumnya haram karena dalam proses pembuatan vaksin tersebut memanfaatkan tripsin pada babi.
Gegernya, berujung pada hasil keputusan Bahtsul Masail yang diadakan oleh Lembaga Bahtsul Masail Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LBM PBNU) pada kamis (25/3) sore. Saat itu, kegiatan tersebut tidak hanya dihadiri oleh kalangan fukaha saja. Tetapi juga dihadiri oleh Risman Abudaeri, Direktur AstraZeneca Indonesia, Penny Kusumastuti Lukito, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia(BPOM RI), dan Aluicia Anita Artarini, dalam kapasitasnya sebagai peneliti di Vaksin Merah Putih.
Dalam presentasinya yang disampaikan Anita, menyimpulkan bahwa vaksin produk AstraZeneca bebas dari tripsin babi. Mengingat, tahapan produksi yang dilakukan oleh Oxford-AstraZenecatidak sedikit pun menggunakan tripsin hewani, melainkan dari jenis tumbuhan jamur. Hal ini juga dikuatkan oleh pengakuan direktur AstraZeneka sendiri, Risman Abudaeri.
Dari sini, Bahtsul Masail kali itu memutuskan bahwa vaksin AstraZeneca adalah vaksin yang suci, karenanya, halal secara mutlak untuk disuntikkan. Bahkan, Kiai Afifuddin menyampaikan, dibuat dari bahan najis sekalipun, dengan teori istihalah, bisa menjadi suci. Apalagi memang dari bahan yang suci. Dan, rumusan tersebut disepakati oleh sekalian peserta Bahtsul Masail. Melihat perkembangan isu seputar vaksin AstraZeneca sampai saat ini, sepertinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat, wajib menarik fatwanya kembali dan mengikuti hasil Bahtsul Masail tersebut, bila memang belum dilakukan.
Mengingat, fatwa yang dikeluarkan oleh MUI pusat dalam hal ini, bisa disebut sebagai produk pemikiran intelektual yang tidak tuntas. Mereka menilai sesuatu tidak berdasarkan realitas yang ada. Tentu, fatal sekali dalam kaca mata kajian ilmiah.
Sebenarnya, peristiwa ini adalah hal biasa dalam dunia ijtihad, sebagaimana yang telah dijelaskan di awal. Baik salah atau benar, tetap akan diganjar pahala. Namun, bila kebetulan salah, sebagai bentuk pertanggungjawaban intelektual dan kejujuran ilmiah, maka haruslah menarik kembali fatwa tersebut. Ihwal ini, sering sekali kita temukan dalam berbagai literasi klasik.Itu artinya, secara tidak langsung para ulama terdahulu sedang meneladankan sikap ilmiah (mauqif ‘ilmi) kepada generasi setelahnya.
Kitab Hasyiah I’anathut Thalibin (juz 2, hal. 383), Imam Abu Bakr Utsman bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi (1300 H), menyebutkan:
وفي البجيرمي: وأما الدخان الحادث الآن المسمى بالتتن-لعن الله من أحدثه-فإنه من البدع القبيحة. فقد أفتى شيخنا الزيادي أولا بأنه لا يفطر لأنه إذ ذاك لم يعرف حقيقته، فلما رأى أثره بالبوصة التي يشرب بها رجع وأفتى بأنه يفطر. اه
Artinya, “Dalam Kitab Al-Bujairamiy (dijelaskan), asap (rokok) sebagaimana yang kita kenal dewasa ini, di mana dibuat dari tembakau, termasuk satu bidah yang buruk. Dahulu, guru kita imam Az-Ziyadi berpendapat bahwa mengisap rokok (saat berpuasa), tidak membatalkan puasa.Sayangnya, waktu itu ia belum memahami hakikat rokok yang dihukuminya. Karena itu, ketika telah menyaksikan sendiri bekas dari tanaman tembakau yang dihisap ini, segera ia menarik fatwanya dan mengikuti pendapat bahwa rokok dapat membatalkan puasa.”
Jadi, tradisi menarik kembali fatwa yang dikeluarkan adalah hal lumrah dikalangan ulama salafuna as-shalih. Peristiwa serupa juga pernah terjadi antara dua imam besar, Muhammad bin Idris As-Syafi’i dan Sufyan bin Sa’id As-Tsauri. Di mana, mereka berdebat tentang status kesucian kulit bangkai yang telah disamak. Awalnya, Imam Syafi’i berpendapat, kulit bangkai selamanya tidak bisa suci, walau telah disamak. Berbeda dengan Imam Sufyan As-Tsauri yang berpendapat sebaliknya.
Namun, di akhir debat, setelah masing-masing merenungi ulang pendapatnya, segera Asy-Syafi’i menarik fatwanya, dan mengikuti pendapat Imam Sufyan. Demikian juga dengan Imam Sufyan yang menarik pendapatnya, dan beralih ke fatwa Imam Syafi’i yang pertama. Perdebatan ini sudah diurai dalam tulisan saya sebelumnya. Belajar dari Perdebatan Imam Syafi’i dan Sufyan Ats-Tsauri
Dari peristiwa booming yang menimpa Indonesia kali ini, ada beberapa pelajaran penting yang dapat kita ambil, terutama bagi para santri di tengah masyarakat nantinya. Pertama, dalam berfatwa atau mengeluarkan satu hukum, kendati hal sekecil apapun, tidaklah cukup hanya dengan memahami teks-teks Al-Qur’an dan hadist (fahman nushush). Tetapi juga harus memahami konteks suatu peristiwa secara matang (fahmal waqi’). Ini bukanlah hal baru yang jarang diketahui, tetapi prinsip yang sering kali diabaikan.
Kedua, tidak terburu-buru dalam memutuskan hukum. Prinsip ini bertali kelindan erat dengan yang pertama karena ini termasuk salah satu faktor penyebab kegagalan dalam memahami konteks atau masalah. Dalam ilmu logika (manthiq), ini dikenal dengan istilah at-tasarru’ fil hukmi (terlalu mudah menghukumi), yang mana dibahas dalam bab asbabul khatha’ fit tafkir (faktor-faktor kesalahan berpikir).
Semoga tulisan singkat ini dapat mencerahkan. Wallahu a’lam.
Ahmad Dirgahayu Hidayat, alumnus sekaligus pengajar di Ma’had Aly Situbondo.
Terpopuler
1
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
2
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
3
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
6
KH Ahmad Chalwani Ungkap Makna Spiritual yang Terkandung dalam Deretan Angka 17-8-45
Terkini
Lihat Semua