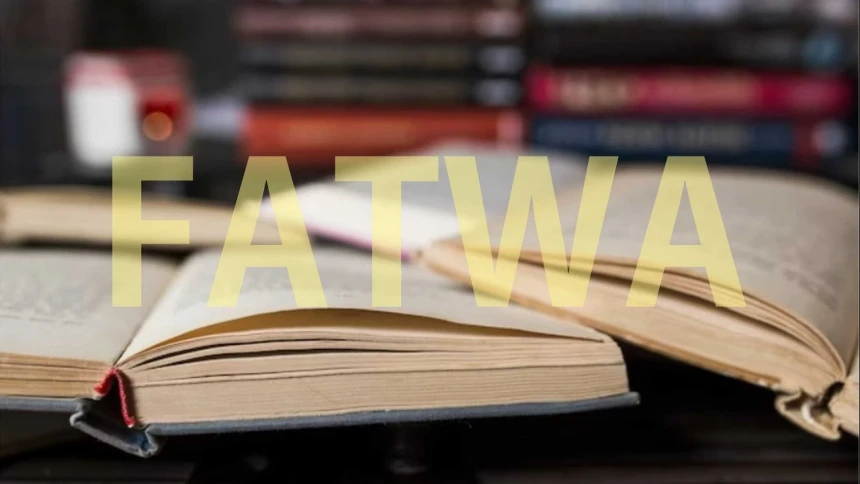Mufti, Mustafti, dan Adab-adab dalam Berfatwa
NU Online · Kamis, 7 September 2023 | 22:00 WIB
Sunnatullah
Kolomnis
Imam Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syaraf an-Nawawi (wafat 676 H) dalam salah satu kitab karyanya, Majmu’ Syarhil Muhadzdzab, juz I, halaman 40, menjelaskan secara panjang lebar dan detail perihal adab yang berkaitan dengan fatwa, mufti dan mustafti. Berkaitan dengan ini ia menuliskan satu bab khusus dengan tema Adâbul fatwâ wal mufti wal mustafti (etika berfatwa, pemberi fatwa, dan peminta fatwa).
Namun sebelum menjelaskan etika-etika tersebut, ia mengingatkan kepada semua umat Islam bahwa fatwa bukanlah persoalan yang sudah dan bisa dilakukan oleh siapa saja. Menurut ulama yang memiliki otoritas fatwa dalam mazhab Syafi’i itu, berfatwa merupakan perbuatan agung dan mulia yang bisa mendatangkan banyak pahala, juga bisa mendatangkan banyak dosa. Jika fatwanya benar, tentu akan berpahala. Jika tidak, maka ini yang akan menjadi penyebab dosa.
Berikut ini akan penulis jelaskan adab-adab mufti, mustafti, dan berfatwa sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya.
Adab Mufti (Orang yang berfatwa)
Pertama, jika ada orang yang lebih berilmu, maka harus mempersilakan orang tersebut untuk menyampaikan fatwa. Jika tidak ada, barulah ia berfatwa tentang hukum yang ingin disampaikan.
Kedua, jika terdapat dua fatwa, dan fatwa yang pertama ditarik (ruju’), maka tidak boleh bagi mufti dan orang-orang yang meminta fatwa untuk mengamalkan fatwa pertama yang telah ditarik tersebut.
Ketiga, haram hukumnya bagi mufti untuk menganggap remeh (tasahul) perihal fatwa, bahkan juga haram kepada orang lain meminta fatwa pada orang tersebut. Termasuk dari menganggap remeh perihal fatwa adalah terburu-buru untuk menjawab suatu hukum sebelum benar-benar paham pada persoalan yang ditanyakan.
Keempat, tidak boleh berfatwa ketika dirinya sedang dalam keadaan kurang baik, seperti dalam marah, bersedih, sangat bahagia, sangat lapar dan dahaga, bosan, cemas, sakit parah, dan setiap keadaan yang bisa menjadikan hati dan pikirannya tidak tenang. Tidak berfatwa dalam keadaan-keadaan ini, kecuali benar-benar yakin bahwa fatwanya tidak akan keluar dari kebenaran.
Kelima, mufti harus benar-benar piawai dan menguasai secara mendetail perihal fatwa yang sedang ia sampaikan, dan tidak boleh baginya mengambil upah (ujrah) atas fatwa yang disampaikan, kecuali jika benar-benar tidak memiliki pemasukan sama sekali.
Keenam, tidak boleh berfatwa tentang sumpah (aiman) dan pengakuan (iqrar) jika tidak benar-benar paham terhadap bahasa di daerah orang yang bertanya.
Ketujuh, tidak boleh berfatwa dengan mengutip pendapat dari kitab-kitab yang tidak kredibel dan terpercaya.
Kedelapan, jika berfatwa perihal suatu kejadian yang baru, kemudian datang lagi kejadian baru yang sama, maka boleh baginya untuk langsung menjawab dengan fatwa yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Hanya saja, menurut pendapat yang lebih sahih, sebaiknya ia memikirkan kembali fatwanya.
Kesembilan, mufti tidak boleh sekadar menjawab “persoalan ini masih diperselisihkan ulama, persoalan ini terdapat tiga pendapat, persoalan ini masih memiliki tiga riwayat dan lain sebagainya”, karena hal itu pada hakikatnya bukanlah keinginan jawaban dari orang yang meminta fatwa, akan tetapi mufti harus benar-benar menentukan mana pendapat yang paling kuat dari sekian banyak pendapat yang ada.
Baca Juga
Fatwa dan Fatwa
Adab Mustafti (Orang yang meminta fatwa)
Pertama, setiap orang yang belum sampai pada derajat mujtahid, maka ia adalah mustafti. Karena mustafti, maka wajib baginya untuk menanyakan semua permasalahan-permasalahan baru yang sedang terjadi kepada orang yang memiliki kapasitas fatwa, bahkan jika tidak ditemukan mufti di daerahnya, wajib untuk mencarinya keluar.
Kedua, tidak boleh sembarang orang dijadikan mufti, namun harus benar-benar mencari tahu tentang orang yang memiliki kapasitas untuk berfatwa.
Ketiga, orang awam diperbolehkan untuk meminta fatwa kepada siapa saja, baik ulama yang bermazhab Syafi’i, Hanafi, Maliki, maupun Hanbali. Hanya saja, menurut pendapat yang disahihkan oleh Imam al-Qaffal, orang awam tetap harus memilih satu mazhab dari empat mazhab yang ada.
Keempat, jika terdapat fatwa yang berbeda-beda dalam satu hukum, maka ia boleh memilih sebagai berikut: (1) memilih yang lebih berhati-hati; (2) boleh memilih yang lebih ringan; (3) harus benar-benar pilah-pilih dalam menentukan pilihan fatwa yang diikuti, mulai dari melihat yang lebih berilmu dan lebih wira’i; (4) bertanya pada mufti yang lain, kemudian mengikuti pendapat yang sama dengannya; dan (5) boleh memilih salah satu dari keduanya, dan ini merupakan pendapat yang lebih sahih menurut Imam Abu Ishaq asy-Syirazi dan Imam Khatib al-Baghdadi.
Kelima, jika di suatu tempat hanya terdapat satu mufti, maka wajib bagi yang lain untuk mengikuti fatwanya.
Keenam, jika sudah terdapat fatwa, kemudian muncul persoalan baru yang sama, maka ada dua pendapat; (1) cukup mengamalkan fatwa yang ada tanpa perlu bertanya kembali; dan (2) harus bertanya kembali, karena bisa saja terdapat perubahan hukum tentangnya.
Ketujuh, harus meminta fatwa sendiri, atau mengutus orang lain yang dapat dipercaya.
Kedelapan, mustafti harus sopan kepada mufti. Ia tidak boleh mendebat ketika sudah mendapatkan jawaban, juga tidak boleh isyarah dengan tangan di hadapan muftinya.
Kesembilan, orang awam tidak perlu menanyakan dalil perihal jawaban yang disampaikan oleh mufti.
Adab Fatwa
Pertama, mufti harus benar-benar menjelaskan fatwanya dengan sangat rinci dan detail, sekira orang yang meminta fatwa benar-benar paham dan tidak ada kejanggalan sedikit pun, kemudian barulah ia meringkasnya menjadi lebih sedikit dan lebih simpel,
يَلْزَمُ الْمُفْتِى أَنْ يُبَيِّنَ الْجَوَابَ بَيَانًا يُزِيْلُ الْاِشْكَالَ ثُمَّ لَهُ الْاِقْتِصَارُ عَلىَ الْجَوَابِ
Artinya, “Wajib bagi mufti menjelaskan jawaban dengan penjelasan yang luas, sekira bisa menghilangkan kejanggalan (dari penanya), berulah ia boleh meringkas jawabannya.”
Kedua, tidak boleh bagi seorang mufti menjawab sekadar dengan apa yang diketahuinya saja. Jika persoalan yang ada memiliki celah atau motif yang lain, maka katakanlah, “Jika kasusnya begini, maka jawabannya begini. Jika kasusnya begitu, maka jawabannya begitu”.
Ketiga, jika orang yang meminta fatwa merupakan orang yang sulit paham, maka mufti harus ramah dan sabar untuk menjelaskannya hingga penanya benar-benar paham. Sungguh hal ini merupakan pahala yang sangat besar.
Keempat, hendaknya mufti benar-benar merenungkan pertanyaan dengan perenungan yang mendalam, khususnya pada akhir pertanyaan, karena kunci pertanyaan ada pada akhirnya. Jika ditemukan kata yang tidak jelas, maka hendaknya mufti bertanya pada penanya.
Kelima, dianjurkan untuk membacakannya kepada semua orang-orang yang hadir saat itu, kemudian membahasnya dengan tenang dan bijak, sekalipun dengan orang yang tidak selevel atau muridnya. Hal ini merupakan kebiasaan ulama salaf. Kecuali jika pertanyaan tersebut tidak layak untuk disampaikan kepada khalayak umum, penanya akan malu, atau akan menimbulkan mafsadah.
Keenam, mufti harus menulis fatwanya dengan tulisan yang jelas dan normal, serta tidak ada yang terlalu tipis dan terlalu tebal. Mufti juga harus menulisnya dengan renggang baris yang sama. Kalimat yang ditulis harus jelas, benar susunannya, dan bisa memahamkan. Sebagian ulama menganjurkan untuk tidak mengganti pulpen atau model tulisannya, karena untuk menghindari pemalsuan.
Ketujuh, dianjurkan berdoa ketika hendak berfatwa. Diriwayatkan, bahwa Imam Makhul dan Malik tidak pernah berfatwa sampai ia membaca hauqâlah (lâ haula walâ quwata illâ billâh). Dianjurkan juga untuk membaca ta’awudz (a’ûdzu billâhi minas syaithanir rajîm) kemudian membaca basmalah, membaca hamdalah, dan shalawat kepada nabi, kemudian ditambah dengan bacaan “rabbisy rahli shadri”. Dan, di akhir fatwanya juga dianjurkan membaca wabillâhit taufiq atau wallahu a’lam.
Kedelapan, sebaiknya mufti meringkas jawabannya agar bisa dipahami oleh semua orang, seperti contoh: “hukum yang dibahas ini adalah halal, haram, boleh atau tidak boleh”.
Kesembilan, tidak dilarang jika mufti menyampaikan dalil dan hujah atas fatwa yang disampaikannya. Imam as-Shamiri berkata: "tidak perlu menyampaikan dalil jika berfatwa pada orang awam, dan harus menyebutkan dalil jika berfatwa pada orang berilmu".
Kesepuluh, jika berfatwa tentang ilmu kalam (Tauhid), maka seyogyanya tidak perlu membahas dengan rinci dan mendalam, bahkan seharusnya tidak membawa orang yang bertanya atau orang awam tenggelam dalam pembahasan ilmu tersebut. Cukup baginya menjelaskan tentang pokok-pokok iman saja. Dan, jika ada yang memiliki keyakinan yang salah tentang Tuhan, maka cukup meluruskannya saja kesalahan dan kesesatannya.
Kesebelas, jika terdapat ahli fiqih (faqih) yang bertanya tentang tafsir Al-Qur’an, maka lihat dulu, jika pertanyaannya berkaitan dengan hukum fiqih, seperti maksud dari shalat wustha, quru’, dan uqdatun nikah, maka boleh untuk menjawabnya. Jika tidak berhubungan dengan hukum fiqih, maka selayaknya memasrahkan kepada orang yang ahli tentangnya.
Itulah beberapa adab-adab atau etika fatwa, orang yang berfatwa, dan orang yang meminta fatwa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ Syarhil Muhadzdzab, cetakan Darul Kutub Ilmiah, juz I, halaman 40-54. Semoga bermanfaat. Walahu a’lam.
Sunnatullah, Pengajar di Pondok Pesantren Al-Hikmah Darussalam Durjan Kokop Bangkalan Jawa Timur.
Terpopuler
1
Orang Wajib Zakat Fitrah Tapi Juga Boleh Menerima?
2
Perang Iran dan Israel-AS Berdampak Global, Ketua Umum PBNU Desak Perdamaian
3
Standar Ganda Sekutu dalam Perang Israel-AS vs Iran
4
Cendekiawan Malaysia Syed Naquib Alatas Meninggal Dunia dalam Usia 94 Tahun
5
Kuasa Hukum Sebut Keterangan Ahli KPK Justru Menguatkan Dalil Praperadilan Gus Yaqut
6
Tarawih 8 atau 20 Rakaat? Inilah Cara Bijak Menyikapinya
Terkini
Lihat Semua