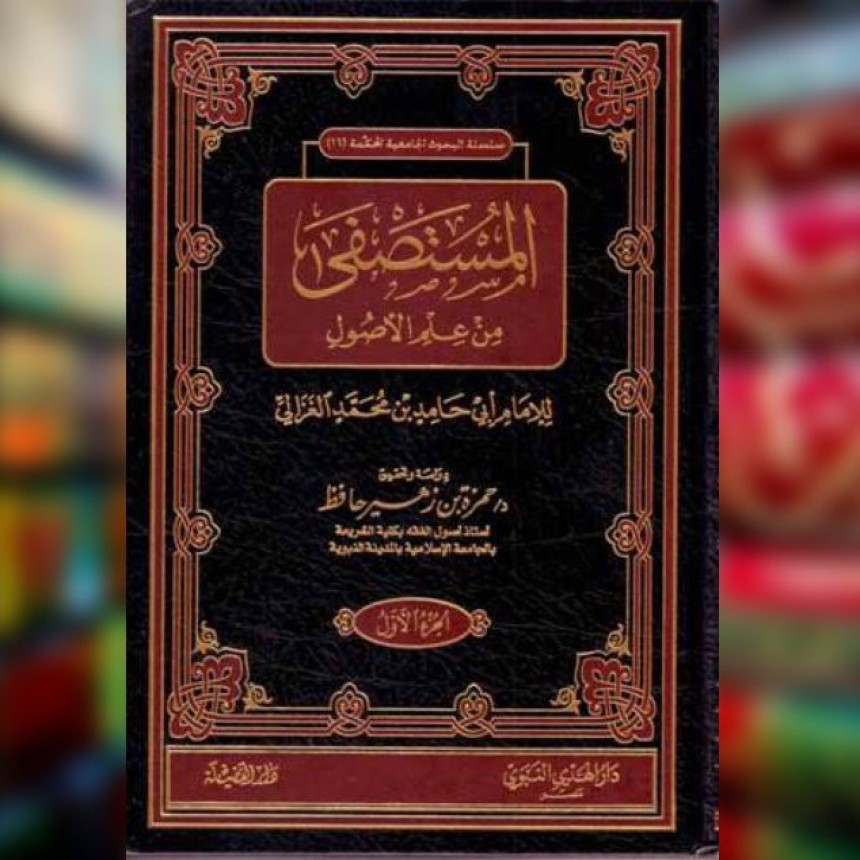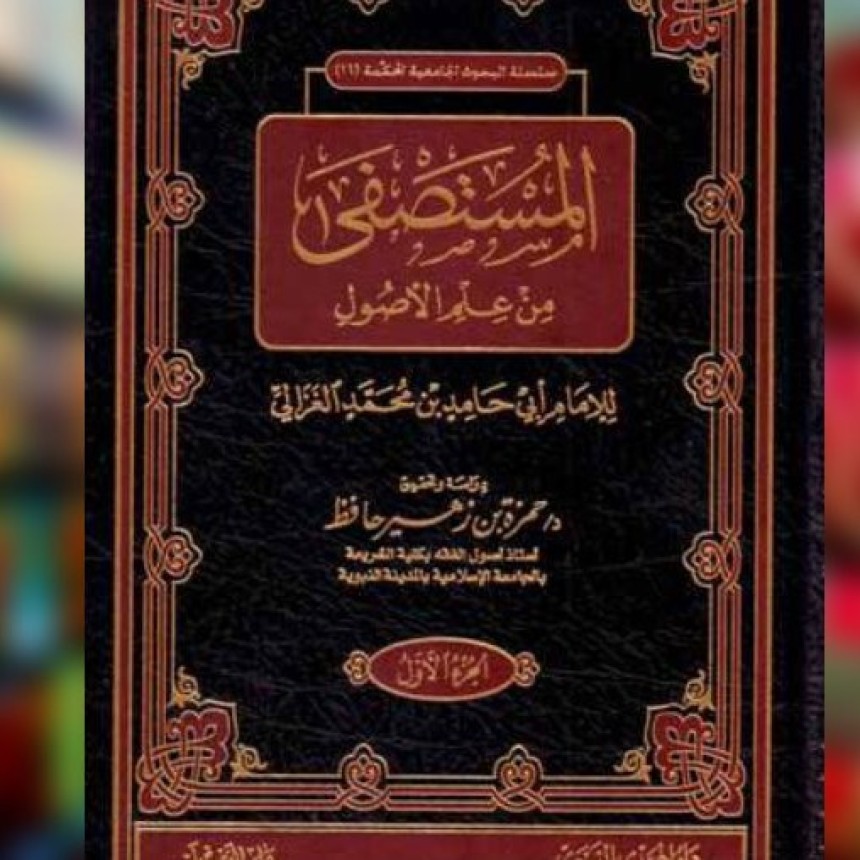Perubahan Fatwa karena Tahqiqul Manath yang Berbeda
NU Online · Selasa, 22 Februari 2022 | 17:00 WIB
Muhammad Faeshol Muzammil
Kolomnis
Penerapan hukum (tanzīlul ḥukm) atau fatwa bisa terjadi perbedaan dan perubahan jika tashawwur atas maḥkūm ‘alaih atau obyek terdapat perbedaan dan perubahan. Perbedaan pengetahuan sebagai hasil ijtihad atas obyek terjadi disebabkan dua hal. Pertama, perbedaan atau perubahan perangkat yang menghasilkan pengetahuan. Artinya, obyek yang diteliti sama dan tidak berubah, tapi perangkat untuk mengetahuinya yang berbeda atau berubah. Keduanya adalah hasil ijtihad tahqiqul manath. Perbedaan fatwa bukan disebabkan hasil ijtihad atas dalil-dali syariat atau fiqih sebagai konsep, melainkan disebabkan perbedaan hasil ijtihad tahqiqul manath. Tarjih mana yang paling kuat, bukan berdasar kekuatan dalil, namun berdasar kelengkapan, keakuratan dan ketelitian data tentang obyek. Beberapa contoh telah disebutkan dalam tulisan sebelumnya. Berikut tiga contoh lain di mana perubahan fatwa harus dilakukan karena ada perubahan hasil ijtihad tahqiqul manath.
Pertama, tentang hukum binatang belut. Perbedaan fatwa tentang belut juga bersumber dari perbedaan hasil ijtihad tahqiqul manath yang berbasis pengetahuan inderawi (hissiyyah). Ketika konsep “hidup di dua alam” disepakati, maka munculnya perbedaan fatwa bersumber pada perbedaan tashawwur atas hakekat belut dan pola hidupnya. Tashawwur yang dimenangkan adalah hasil penelitian yang paling lengkap, akurat dan teliti. Dalam hal ini, Syaikh Muhammad Mukhtar bin ‘Atharid Al-Jawi (wafat 1930 M) telah melakukan penelitian langsung; dengan musyahadah atas hakekat belut dan pola hidupnya, lalu menuangkannya dalam risalah as-Ṣawā’iqul Muḥriqah lil Awhāmil Kādzibah fī Bayāni Hillil Belut war Raddi ‘alā Man Harramah (Petir Pembakar Asumsi-Asumsi Dusta; Penjelasan Kehalalan Belut dan Bantahan bagi Mereka yang Mengharamkannya). Syaikh Muhammad Mukhtar, ulama asli Bogor yang mengajar di Masjidil Haram membantah ulama yang menyimpulkan bahwa belut termasuk hewan yang hidup di dua alam; di air dan di lumpur. Kesimpulan oleh beliau disebut dengan wahm.
Penelitian akurat atau tahqiq beliau lakukan dengan mengamati secara langsung pola hidup belut, yaitu tempat menetap, tempat tidur dan tempat mencari makan, serta menguji ketidakmampuan hidup lama di lumpur dan ketiadaan di tanah yang kering. Penelitian menunjukkan bahwa belut adalah hewan yang hanya hidup di air. Saat berada di lumpur, belut sekedar lewat atau berkubang yang tidak berlangsung lama. Seperti halnya hewan darat (bebek misalnya) yang mandi di air, bukan berarti hidup di dua alam [halaman 7-8].
Kedua, tentang pakaian thailasan. Thailasan adalah kain panjang seperti ridā’ namun dipakai untuk menutup kepala tanpa dililit; sedangkan ridā’ dipakai di pundak; dan yang dililitkan di kepala disebut ‘imāmāh. Thailasan belum ada pada zaman Rasulullah sahallahu ‘alaihi wasallam. Sahabat Jubair bin Muth’im adalah yang pertama memakainya di Madinah. Banyak ulama menghukumi makruh sebab thailasan ini pakaian khas atau menjadi simbol komunitas Yahudi. Memakainya berarti tasyabbuh atau menyerupai kaum kafir. (Hasyiyah Bujairami ‘alal Iqna’, juz IV, halaman 366 dan Fatawas Subki, juz II, halaman 403).
Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani (wafat 1449 M) menjelaskan, thailasan di zamannya tidak lagi menjadi pakaian khas komunitas Yahudi, maka hukumnya berubah menjadi boleh. Imam Izzuddin ibni Abdissalam (wafat 1262 M) memasukkannya sebagai bid’ah mubāḥah. Suatu perkara yang semula menjadi ciri khas suatu masyarakat (dengan konotasi negatif) bisa jadi di suatu waktu berubah menjadi baik, bahkan meninggalkannya dapat menjatuhkan harga diri (murūah). (Fathul Bari, juz X, halaman 274-275).
Faktanya memang thailasan telah menjadi simbol keulamaan masyarakat muslim saat itu. Dalam banyak masyarakat, tidak memakainya dapat menurunkan harga diri.
Imam Ibnu Hajar Al-Haitami (wafat 1567 M) dalam Tuhfatul Muhtaj mempunyai pandangan sedikit berbeda. Menurutnya, thailasan dilihat dari aspek pemakaiannya terbagi menjadi dua macam. Pertama, menutupi kepala, lalu salah satu atau kedua sisinya diselempangkan sehingga menutupi leher dan kedua ujungnya diletakkan di bawa pundak (katif). Thailasan yang dipakai seperti ini hukumnya sunnah karena dilakukan Rasulullah. Inilah yang dalam hadis-hadis disebut taqannu’. Sementara yang kedua adalah thailasan yang dipakai dengan tanpa diselempangkan, melainkan dengan membiarkan kedua ujungnya jatuh di kedua lengan tangan atau dua sisi tubuh. Yang kedua ini hukum asalnya makruh karena menjadi ciri khas komunitas Yahudi. (Tuhfatul Muhtaj, juz III, halaman 41-42).
Ketiga, masalah da’āwī kādzibah (pengakuan dusta yang harus ditolak). Imam Suyuthi (wafat 1505 M) dalam kitab Al-Asybah wan Nadhair menjelaskan bahwa da’āwī kādzibah adalah pengakuan yang berisi perkara mustahil seperti seorang yang berada di Makkah mengaku telah menikahi perempuan di Bashrah di hari kemarin. Pengakuan ini dianggap dusta sebab di zaman itu waktu untuk menempuh perjalanan antara Makkah dan Bashrah, Irak (kurang lebih 1500 km) paling cepat 3 minggu. “Tidak mungkin” di sini menurut hukum kebiasaan, bukan dalam ranah hukum akal atau syariat. KH. MA Sahal Mahfudh Kajen (wafat 2014 M) dalam Anwarul Bashair, memberi ta’liq dengan mengutip penjelasan gurunya, KH. Zubair Dahlan Sarang (wafat 1969 M) “peristiwa tersebut mustahil pada zaman awal (dahulu), tapi tidak pada zaman sekarang sebagaimana telah jelas diketahui” (Anwarul Bashair, halaman 598).
Contoh pertama termasuk perubahan fatwa yang harus diambil karena tashawwur yang berbeda. Hakikat belut dan pola kehidupannya sebagai obyek, sama dan tidak berubah namun perangkat pengetahuan yang digunakan berbeda dan lebih akurat sehingga menghasilkan tashawwur yang lebih akurat. Sementara contoh kedua dan ketiga, perubahan fatwa disebabkan adanya perubahan obyek.
Memang, thailasan dan pengakuan orang Makkah tersebut jika dilihat dalam pengetahuan inderawi tidak ada yang berubah. Namun karena hukumnya ditentukan konteks kebiasaan masyarakat maka hakikat keduanya telah mengalami perubahan. Thailasan pada zaman Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dinilai sudah tidak mengandung illat tasyabbuh, dan pengakuan orang Makkah tersebut saat ini sudah tidak mustahil lagi seperti yang ditegaskan Kiai Zubair.
Jika dirujukkan pada macam-macam nadhariiyah yang disebutkan Imam Ghazali (baca “Tahqiqul Manath menurut Imam Ghazali Bagian II”) maka contoh pertama termasuk ijtihad tahqiqul manath dalam ranah nadhariyyah hissiyyah, sementara kedua dan ketiga masuk nadhariyyah ‘urfiyyah. Wallahu a’lam.
Ustad Muhammad Faeshol Muzammil, Wakil Ketua LBM PWNU Jawa Tengah, Muhadlir Ma'had Aly Pesantren Maslakul Huda.
Terpopuler
1
Kultum Ramadhan: Keutamaan 10 Malam Terakhir dan Cara Mendapatkan Lailatul Qadar
2
Menurut Imam Ghazali, Lailatul Qadar Ramadhan 1447 H Akan Jatuh pada Malam Ke-25
3
Khutbah Jumat: Hikmah Zakat Fitrah, Menyucikan Jiwa dan Menyempurnakan Ibadah
4
Khutbah Jumat: Urgensi I’tikaf di Masjid 10 Malam Terakhir Ramadhan
5
Lafal Doa Malam LaiLatul Qadar, Lengkap dengan Latin dan Terjemah
6
Khutbah Jumat: Puasa, Al-Qur’an, dan 5 Ciri Orang Bertakwa
Terkini
Lihat Semua