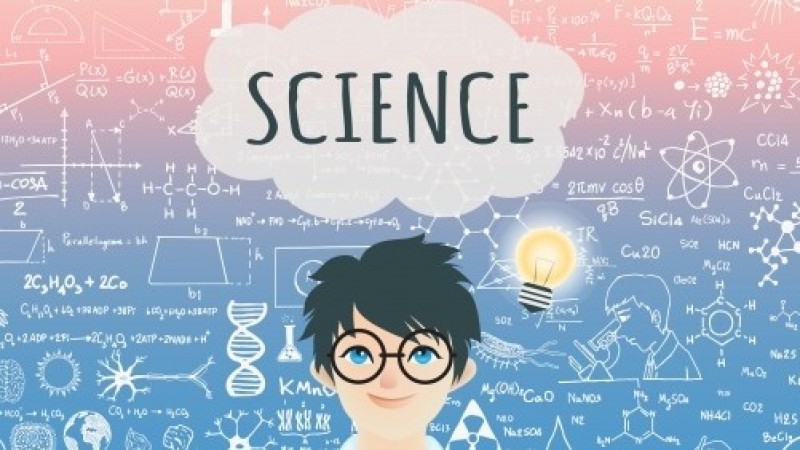Di tengah perkembangan sains yang sangat cepat, pandangan Ibnu Rusyd mengenai sains sangat menarik dikemukakan, di antaranya karena beberapa faktor. Pertama, pandangan sains cendikiawan muslim abad pertengahan layak ditelusuri kembali. Kedua, di tangan para cendekiawan muslim sains berkembang tanpa persoalan bersamaan dengan semangat kebergamaan. Ketiga, Ibnu Rusyd menjadi kunci utama dalam pewarisan peradaban—yang dalam istilah Philip K. Hitti disebut sebagai peralihan panggung peradaban—dari Islam ke dunia barat. Hal terakhir ini dibuktikan setidaknya dengan penerjemahan kitab al-Fashlul Maqâl karya Ibnu Rusyd ke dalam bahasa Inggris, yang saat ini dikenal sebagai bahasa dunia ilmu pengetahuan.
Kajian faktor kedua inilah yang menjadi fokus dalam tulisan ini. Mempelajari ontologi ilmu (sains) Ibnu Rusyd menjadi sangat menarik, karena merupakan hal yang berbeda dengan konsep sains di mata barat saat ini.
Sains menurut Ibnu Rusyd
Ibnu Rusyd berpandangan, hakikatnya sains merupakan cara pembuktian (atau penguatan) terhadap kebenaran dan keberadaan Tuhan (al-Fashlul Maqâl). Dalam pandangan Ibnu Rusyd, alam diciptakan oleh Tuhan berdasarkan hukum-hukum yang berlaku dan mengitarinya, yaitu hukum kausalitas atau sebab-akibat. Alam diciptakan dengan potensi yang diletakkan Tuhan kepadanya, seperti api yang berpotensi membakar dan sebagainya (al-Kasyfu ‘an Manâhij Adillah). Mengingkari adanya keteraturan dalam bingkai kausalitas adalah suatu kebodohan. (Tahâfutut Tahâfut).
Lebih lanjut Ibnu Rusyd menjelaskan, pengetahuan manusia terhadap hukum-hukum alam disebut sebagai hikmah, dan tugas ilmuwan adalah menemukan hukum-hukum alam tersebut sebagai pengetahuan filosofis yang dapat diraihnya (al-Kasyfu). Al-Qur’an sendiri menjelaskan bahwa ‘Orang yang diberikan karunia hikmah merupakan manusia yang telah diberikan kebaikan yang banyak.’ (QS. al-Baqarah: 269).
Di dalam kajian morfologis, memang kita melihat bahwa kata ‘hukum’ di dalam bahasa Arab memiliki akar kata yang sama dengan kata ‘hikmah.’ Keduanya merupakan bentuk derivasional dari kata kerja ‘hakama’. Tepatnya, keduanya adalah bentuk masdar (verbal noun) dari kata tersebut dalam suatu sighat: hakama-yahkumu-hukman (hikmatan). Kata hukum atau hikmah dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai: (1) suatu pengetahuan yang meyakinkan; dan/atau (2) pengetahuan kebijaksanaan.
Dari sini kita mengetahui, pada dasarnya pandangan Ibnu Rusyd terhadap sains (ilmu alam) sangat berbeda dengan pandangan para filsuf barat, seperti Auguste Comte misalnya. Ibnu Rusyd, sebagaimana pandangan para filsuf skolastik abad pertengahan memandang sains sebagai pelayan dan penguat agama. Hal ini sebagai implikasi langsung dari paradigma sains yang ia pegang, bahwa pada dasarnya sains adalah suatu usaha untuk mengetahui hukum-hukum alam di dalam rangka pembuktian adanya (eksistensi) Tuhan Sang Pencipta.
Sains menurut Barat
Hal ini tentu saja sangat berbeda dengan pendapat para pemikir barat seperti Auguste Comte. Comte menjelaskan sains sebagai keberlanjutan (progress) dari agama dalam hal usaha manusia mencari kebenaran. (Stephen Tong, 1980).
Dalam pandangan Comte, mulanya manusia dikuasai oleh ‘misteri’ fenomena alam. Dalam tahap ini maka manusia dikuasai oleh alam dan merasa takut padanya. Selanjutnya, ia berusaha mencari sandaran atas apa yang tak dapat kuasainya. Pada tahap inilah menurutnya agama muncul dan berkembang. Lalu manusia secara naluriah ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada alam. Tahap ini disebutnya sebagai tahap filsafat metafisika. Tahap berikutnya adalah tahap dimana manusia mulai dewasa dan mengetahui apa yang sebenarnya terjadi pada alam. Bahkan manusia telah menguasai dan dalam beberapa hal dapat mengendalikan alam.
Tahap inilah yang disebut Comte sebagai tahap perkembangan ilmu pengetahuan (scientific). Pada tahap terakhir ini ia menilai, manusia telah cukup dewasa dan tidak lagi takut terhadap alam. Dalam tahap ini pula maka agama sudah tidak lagi diperlukan. (Stepen Tong, 1980).
Kesimpulan
Di sinilah kita melihat bahwa pandangan terhadap sains dalam dunia Islam dan Barat menjadi berbeda. Di satu sisi, cendikiawan muslim—sebagaimana abad pertengahan—memandang ilmu sebagai penguat agama. Islam memberikan ruang dan iklim yang cukup baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Said Aqil Siradj (1995) menjelaskan bahwa epistemology burhany sebagaimana semangat Al-Qur’an dan dipraktikkan dalam peradaban Yunani telah dipahami dan dikerjakan dengan baik oleh para cendikiawan muslim pada abad pertengahan itu.
Di sisi lain, sains di dunia barat saat ini berkembang menjadi sangat sekuler dalam bingkai apa yang disebut sebagai ‘bebas nilai’. Wallahu a'lam.
R. Ahmad Nur Kholis, Ketua LBM MWC NU Ngajum dan Dosen Filsafat Pendidikan Islam di STAI Nahdlatul Ulama Malang.