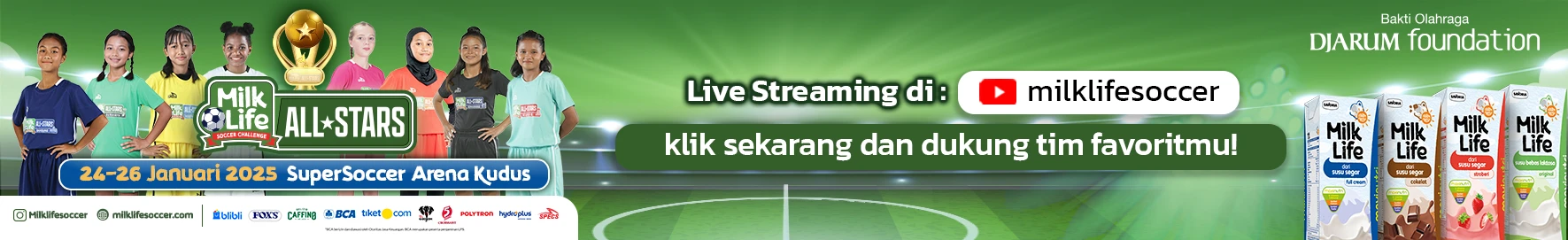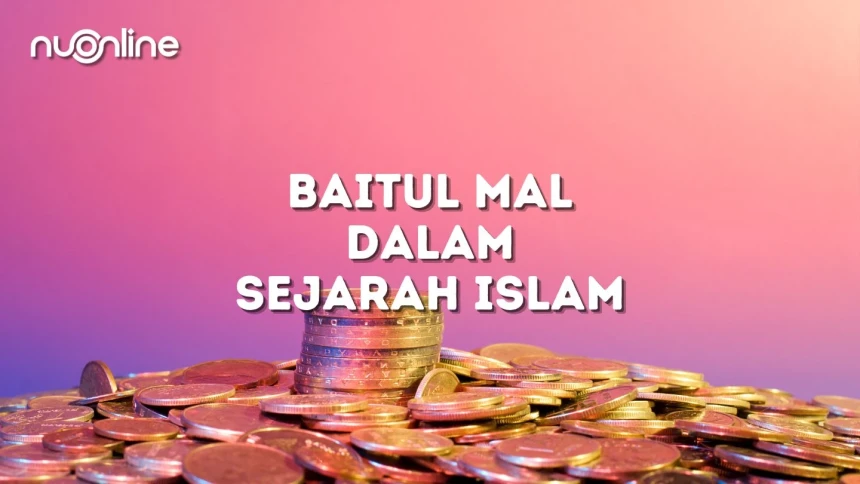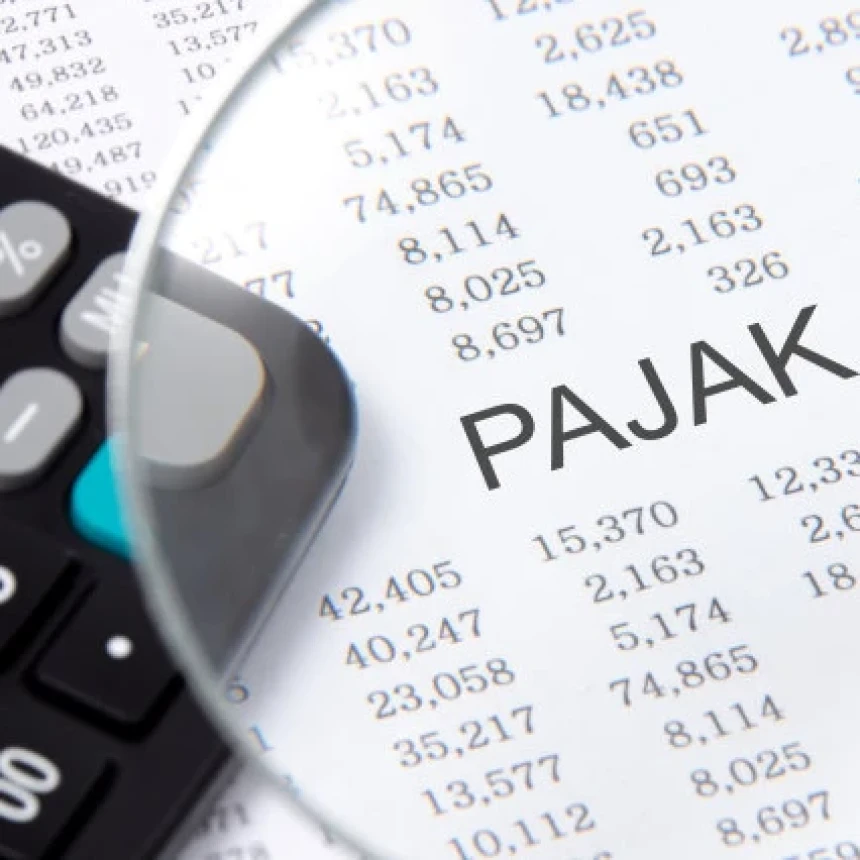Baitul Mal dan Pengelolaan Keuangan Publik dalam Sejarah Islam
Jumat, 6 September 2024 | 19:00 WIB
Peran efektif negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi Islam termasuk pengelolaan keuangan
publik. Pengelolaan keuangan publik merupakan aktivitas manusia yang mengatur sejumlah harta negara untuk kepentingan-kepentingan publik atau warga negara.
Dengan demikian, suksesnya pengelolaan keuangan publik merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan negara untuk kesejahteraan warganya.
Perkembangan ekonomi Islam saat ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah pemikiran ekonomi Muslim di masa lalu. Adalah suatu keniscayaan bila pemikir Muslim berupaya untuk membuat solusi atas segala persoalan hidup di masanya dalam perspektif yang dimiliki.
Oleh karena itu, penting untuk mengkaji praktik pengelolaan keuangan publik oleh Rasulullah saw. dan para Khulafaur Rasyidin serta prinsip-prinsip yang dapat diambil dari mereka.
Pengelolaan Keuangan Publik Masa Rasulullah
Sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, kota tersebut berada dalam kekacauan tanpa pemimpin atau penguasa yang berdaulat. Ekonominya lemah dan bergantung sepenuhnya pada hasil pertanian. (P3EI, Ekonomi Islam, [Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008], hal. 486).
Salah satu inovasi revolusioner yang diperkenalkan oleh Rasulullah SAW saat memimpin Madinah adalah pembentukan lembaga keuangan publik yang disebut Baitul Mal.
Lembaga ini berperan sebagai pusat penyimpanan dan pengelolaan dana negara, dengan tujuan utama memastikan transparansi dalam penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pengeluaran (expenditure) untuk kesejahteraan umat (welfare-oriented).
Baitul Mal tidak hanya bergantung pada zakat sebagai sumber pendapatan. Sumber pendapatan lain yang dikelola oleh lembaga ini meliputi kharaj (pajak tanah), zakat, khums (seperlima dari rampasan perang), jizyah (pajak bagi non-Muslim), serta berbagai bentuk penerimaan lainnya, seperti kaffarah (denda tebusan).
Beragamnya sumber pendapatan ini memungkinkan Baitul Mal menjalankan kebijakan fiskal yang lebih luas dan strategis untuk mendukung kestabilan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat.
Pada masa Rasulullah SAW, Baitul Mal berlokasi di Masjid Nabawi, yang juga berfungsi sebagai kantor pusat pemerintahan. Hal ini terjadi karena pada masa awal Islam, jumlah harta yang masuk belum begitu besar dan segera didistribusikan untuk kepentingan umat Muslim serta digunakan untuk mendukung administrasi negara.
Oleh karena itu, belum ada kebutuhan mendesak untuk membangun lokasi khusus bagi Baitul Mal, karena fungsi utamanya telah terintegrasi dalam kehidupan masyarakat Madinah. (Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, [Jurnal Ekonomi Syariah, vol. 1, no.1, Maret 2016], hal. 97-98)
Pengelolaan Keuangan Publik Masa Khulafaur Rasyidin
Pembahasan tentang pengelolaan keuangan publik pada masa Khulafaur Rasyidin merupakan topik penting dalam sejarah awal Islam. Pada masa ini, terjadi peralihan signifikan dari fanatisme kesukuan menuju pemerintahan Islam yang lebih terstruktur, sekaligus menjadi penentu arah perkembangan setelah masa kenabian.
Setiap Khulafaur Rasyidin memiliki pendekatan yang unik dalam tata kelola keuangan. Abu Bakar, misalnya, mengambil tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang menolak kewajiban syariat, seperti zakat. Umar bin Khathab mengelola Baitul Mal dengan penuh kehati-hatian, sementara Utsman memilih untuk tidak menerima gaji sebagai khalifah dari Baitul Mal. Ali bin Abi Thalib mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal secara adil ke provinsi-provinsi seperti Madinah, Bashrah, dan Kufah.
1. Masa Abu Bakar Ash-Shiddiq
Dua tahun periode Abu Bakar memegang tampuk pemerintahan diawali dengan menyelesaikan problem keuangan publik. Beliau terjun langsung memerangi orang-orang yang murtad, nabi palsu, dan orang-orang yang enggan membayar zakat. (As-Suyuti, Tarikhul Khulafa, [Beirut: Darul Fikr, t.t], hal. 67-71).
Abu Bakar dengan tegas melanjutkan kebijakan ekonomi yang pernah diterapkan oleh Rasulullah. Ia memastikan perhitungan dan pengumpulan zakat dilakukan dengan akurat. Hasil zakat tersebut kemudian disalurkan melalui Baitul Mal dan segera didistribusikan, sehingga tidak ada yang tersisa dalam waktu lama. (Muhammad Abdul Karim, Sejarah Pemikiran dan Peradaban Islam, [Yogyakarta: Bagaskara. 2012], hal. 79).
Pada tahun kedua kepemimpinannya (12 H/633 M), Abu Bakar memperluas peran Baitul Mal. Baitul Mal tidak hanya berfungsi sebagai pengelola harta umat, tetapi juga sebagai tempat penyimpanan harta negara.
Sebagai bentuk implementasi, Abu Bakar menyiapkan tempat khusus di rumahnya, berupa karung atau kantong, untuk menyimpan harta yang dikirimkan ke Madinah. Sistem ini berlangsung hingga beliau wafat pada tahun 13 H/634 M (Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, hal. 98).
Sepanjang masa pemerintahannya, zakat selalu didistribusikan tepat waktu tanpa meninggalkan sisa. Bahkan, saat menjelang wafatnya, hanya satu dirham yang tersisa di perbendaharaan negara. Karena sumber pendanaan negara semakin menipis, Abu Bakar menggunakan kekayaannya sendiri untuk membiayai keperluan negara. (P3EI, Ekonomi Islam, hal. 491)
2. Masa Umar bin Khathab
Selama memerintah, Umar bin Khathab memelihara Baitul Mal secara hati-hati. Terkadang, selain menyimpannya di Baitul Mal, Umar menyisihkan seperlima dari harta rampasan perang untuk dibagikan secara langsung pada kaum Muslimin. Mengenai banyaknya, beliau hanya menerima pemasukan sesuai syariat dan mendistribusikannya kepada yang berhak menerimanya.
Kejujuran Umar dalam mengelola Baitul Mal dijelaskan dalam salah satu pidatonya yang dicatat penulis sejarah dan ahli tafsir bernama lbnu Kasir (700-774 H/1300-1373 M), tentang hak seorang khalifah dalam Baitul Mal.
Sang Khalifah berkata, “Tidak dihalalkan bagiku dari harta milik Allah ini melainkan dua potong pakaian musim panas dan sepotong pakaian musim dingin, serta uang yang cukup untuk kehidupan sehari-hari seorang di antara orang-orang Quraisy biasa. Dan aku adalah seorang biasa seperti kebanyakan kaum Muslimin.” (Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, hal. 99).
Ada beberapa aspek penting terkait kebijakan keuangan negara pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab, antara lain:
a. Baitul Mal
Pada masa Khalifah Umar, Baitul Mal dikelola dengan baik dan sistem administrasinya tertata rapi, seiring dengan peningkatan drastis pendapatan negara. Harta di Baitul Mal tidak dihabiskan sekaligus; sebagian dialokasikan sebagai cadangan untuk keperluan darurat, pembayaran gaji tentara, dan kebutuhan masyarakat lainnya.
b. Kepemilikan Tanah
Khalifah Umar memutuskan bahwa tanah-tanah yang diperoleh dalam peperangan (fai) harus dipertahankan sebagai aset negara, bukan didistribusikan kepada individu.
c. Zakat dan ‘Ushr
Menurut laporan Abu Ubaid, Umar membuat kebijakan berbeda terkait zakat madu. Madu yang berasal dari pegunungan dikenakan zakat 1/20, sementara madu dari ladang dikenakan zakat 1/10.
d. Sedekah oleh Non-Muslim
Pada masa Khalifah Umar, non-Muslim umumnya tidak diwajibkan membayar sedekah kecuali Bani Taghlib, suku Arab Nasrani yang seluruh kekayaannya berupa ternak. Umar menetapkan jizyah bagi mereka, namun mereka menolak membayar jizyah dan setuju untuk membayar sedekah ganda sebagai gantinya.
e. Mata Uang
Ketidaksamaan bobot dan nilai dirham menyebabkan kebingungan di masyarakat. Untuk mengatasinya, Umar menetapkan standar berat 1 dirham perak sebesar 14 qirat atau 70 grain barley.
f. Klasifikasi Pendapatan Negara
Pada masa Umar, pendapatan negara di Baitul Mal dibagi menjadi empat kategori:
- Zakat dan ‘Ushr: Diperoleh dari kaum Muslimin dan didistribusikan kepada delapan golongan (ashnaf). Kelebihan dana disimpan di Baitul Mal pusat untuk kemudian dibagikan kembali.
- Khums dan Sedekah: Dana ini diberikan kepada fakir miskin dan untuk mendukung kesejahteraan tanpa diskriminasi.
- Kharaj, Fai, Jizyah, ‘Ushr, dan Sewa Tanah: Pendapatan ini diperoleh dari non-Muslim dan digunakan untuk pembayaran pensiun, dana bantuan, serta kebutuhan operasional, termasuk militer.
- Pendapatan Lain-lain: Dana ini digunakan untuk membayar pekerja, mendukung anak-anak terlantar, dan kebutuhan sosial lainnya.
g. Pengeluaran
Pengeluaran negara pada masa Khalifah Umar diprioritaskan untuk pembayaran pensiun bagi mereka yang tergabung dalam militer, baik Muslim maupun non-Muslim, termasuk pensiun bagi pegawai sipil (P3EI, Ekonomi Islam, hal. 491-496).
3. Masa Utsman bin Affan
Pada masa kepemimpinan Utsman, pejabat perbendaharaan yang ditempatkan di wilayah kekuasaan Islam bersifat independen, sehingga mereka memiliki otoritas penuh untuk mengontrol pengeluaran dana para pejabat dan gubernur di wilayah masing-masing.
Pernah terjadi perselisihan antara Sa‘d bin Abi Waqqash, Gubernur Kufah yang terkenal kuat namun boros, dengan Ibnu Mas‘ud, pejabat perbendaharaan di Kufah. Utsman akhirnya memutuskan untuk memecat Sa‘d karena dinilai terlalu boros dalam mengelola keuangan.
Sebagai khalifah, Utsman menggunakan dana Baitul Mal untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Utsman sendiri tidak pernah mengambil gaji dari Baitul Mal. Setiap hari Jumat, ia berusaha memerdekakan budak serta menjamin kehidupan janda dan anak yatim piatu. (Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, hal. 101-102)
4. Masa Ali bin Abi Thalib
Pada masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib, kondisi Baitul Mal dikembalikan ke posisinya semula. Ali, yang juga menerima santunan dari Baitul Mal, sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir, hanya mendapatkan jatah pakaian yang sangat sederhana, bahkan hanya mampu menutupi tubuhnya hingga separuh kakinya, sering kali penuh tambalan.
Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan Baitul Mal ke provinsi-provinsi seperti Madinah, Bashrah, dan Kufah. Untuk pertama kalinya, ia mengadopsi sistem distribusi mingguan. Pada hari itu, seluruh penghitungan selesai, dan perhitungan baru dimulai setiap hari Sabtu. (Ririn Noviyanti, Pengelolaan Keuangan Publik Islam Perspektif Historis, hal. 103).
Dari penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pengelolaan keuangan publik pada masa Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin dilakukan dengan bijaksana dan penuh kehati-hatian. Mereka menjauhkan diri dari pemborosan yang bisa merugikan rakyat di bawah kepemimpinan mereka.
Kisah ini bukan hanya lembaran sejarah, tetapi juga pelajaran berharga bagi para pemimpin saat ini. Semoga kita semua terinspirasi untuk mengelola keuangan publik dengan lebih bijak dan bertanggung jawab. Semoga bermanfaat dan membawa inspirasi bagi kita semua. Amin. Wallahu a'lam.
Ustadz M. Ryan Romadhon, Alumni Ma’had Aly Al-Iman Bulus Purworejo, Jawa Tengah