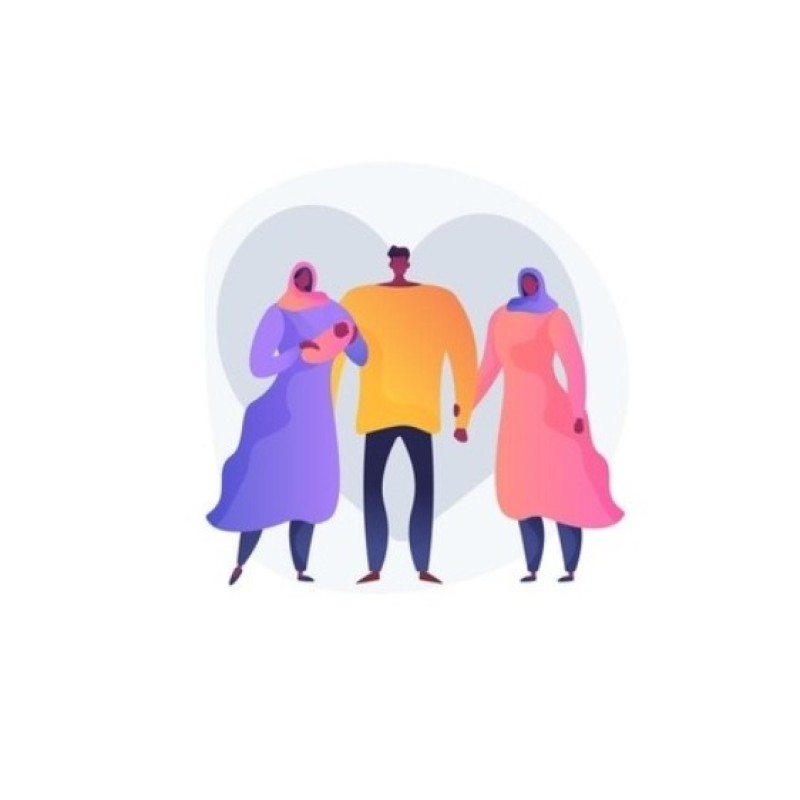Kisah Khalifah Al-Manshur yang Gagal Izin Poligami ke Istri
NU Online · Ahad, 4 September 2022 | 22:00 WIB

Khalifah Al-Manshur memanggil Imam Abu Hanifah untuk menjelaskan hukum poligami di depan istrinya. (Ilustrasi: ilmfeed.com)
Muhamad Abror
Penulis
Rumah tangga Abu Ja’far al-Manshur atau lebih dikenal Al-Manshur rupanya sedang tidak baik-baik saja. Ia dan istrinya sedang ada masalah. Keduanya tidak akur. Usut punya usut, ternyata khalifah kedua dari Dinasti Abbasiyah ini ingin berpoligami. Sang istri keberatan, namun sang khalifah terus merengek meminta persetujuan. Jadilah kerenggangan antara keduanya.
Hingga sekali waktu keduanya mengundang Imam Abu Hanifah ke istana untuk melakukan mediasi. Mereka sangat menaruh hormat kepada ulama yang satu ini. Kita kenal, Abu Hanifah merupakan ulama besar pendiri salah satu aliran fiqih yang masih eksis sampai sekarang, Madzhab Hanafi. Kedatangan Abu Hanifah sebenarnya sangat diharapkan Al-Manshur agar memberi jawaban yang mendukung rencana poligaminya.
“Wahai Abu Hanifah, Harrah (nama istri khalifah) tidak sependapat denganku. Berilah penjelasan untuk menyelesaikan masalah ini,” pinta Al-Manshur kepada Abu Hanifah.
“Katakan saja apa masalahnya, wahai Amirul Mu’minin,” Abu Hanifah mempersilakan.
“Emm, begini. Berapakah batas istri yang boleh dinikahi satu orang laki-laki?” tanya Al-Manshur.
“Empat,” jawab Abu Hanifah singkat.
“Jika memperistri hamba sahaya, berapa batasannya?”
“Kalau itu tidak ada batasan. Silakan berapa saja.”
“Jika ada orang yang tidak setuju dengan aturan ini, bagaimana hukumnya?”
“Ya jelas tidak boleh.”
“Baik, kalau begitu saya paham.”
Al-Manshur tampak sumringah mendapat jawaban itu. Ia merasa penjelasan Abu Hanifah mendukung rencana poligaminya. Ia pun berbisik kepada sang istri, “Kau dengar sendiri kan jawaban Syekh (Abu Hanifah) tadi?”
Belum sempat sang istri menimpali, Abu Hanifah melanjutkan jawabannya yang belum selesai. “Tapi dengarkan dulu wahai Amirul Mu’minin. Saya belum selesai. Ini semua berlaku hanya bagi laki-laki yang mampu berbuat adil. Jika belum mampu atau khawatir tidak bisa, maka ia hanya boleh memiliki satu istri.” Abu Hanifah kemudian mengutip firman Allah berikut,
فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً
Artinya, “Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.” (QS An-Nisa [4]: 3)
“Kita harus tetap berpegang teguh pada aturan-aturan yang telah Allah tetapkan,” pungkas Abu Hanifah.
Al-Manshur pun terdiam cukup lama. Sementara Abu Hanifah lekas keluar dari istana. (Abdul Aziz al-Badri, Al-Islam Bainal Ulama wal Hukama, 2011: 91-92)
Dari sikap Abu Hanifah ini dapat diambil hikmah bahwa seorang ulama harus memiliki independensi dan ketegasan dalam berprinsip. Kendati di hadapan seorang pejabat negara tertinggi, Abu Hanifah tidak gentar untuk memberikan jawaban yang benar meski tidak sesuai dengan keinginan sang khalifah.
Jalaluddin as-Suyuthi melaporkan, pada masa pemerintahan Al-Manshur inilah beberapa ulama besar betul-betul diuji independensinya. Mereka tidak mau diperalat atau menjadi ‘boneka pemerintah’. Kelak, Abu Hanifah beserta kedua ulama lainnya, Abdul Hamid bin Ja’far dan Ibnu ‘Ajlan harus rela meregang nyawa sebab mendukung pemberontakan terhadap khalifah yang tidak adil. (As-Suyuthi, Tarikhul Khualafa, 2017: 169).
Syarat Adil dalam Poligami
Dalam Islam, mampu berlaku adil kepada semua istri merupakan syarat mutlak dalam berpoligami. Baik adil dalam memberi nafkah, memberi jatah giliran, dan kebutuhan-kebutuhan rumah tangga lainnya. Syarat adil ini tidak berlaku dalam urusan kesetaraan perasaan cinta dan sayang bagi semua istri karena hal itu di luar batas kemampuan suami sebagai manusia pada umumnya. Hal ini berdasarkan firman Allah ta’ala berikut,
وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْٓا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاۤءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۗوَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا
Artinya, “Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.” (QS A-Nisa [4]: 129)
Hanya saja, penting kita perhatikan catatan Wahbah az-Zuhaili terkait hal ini. Poligami hanya boleh dilakukan jika betul-betul dalam kondisi darurat. Kemudian, Az-Zuhaili menegaskan bahwa sebenarnya rumah tangga ideal dalam Islam adalah hanya dengan memiliki satu istri (monogami). Poligami merupakan solusi terakhir yang tidak sesuai dengan prinsip dasar rumah tangga.
Berikut penulis kutipkan paparan Az-Zuhaili di bawah ini:
إن نظام وحدة الزوجة هو الأفضل وهو الغالب وهو الأصل شرعاً، وأما تعدد الزوجات فهو أمر نادر استثنائي وخلاف الأصل، لا يلجأ إليه إلا عند الحاجة الملحة، ولم توجبه الشريعة على أحد، بل ولم ترغب فيه، وإنما أباحته الشريعة لأسباب عامة وخاصة
Artinya, “Monogami merupalan sistem perkawinan paling utama. Sistem monogami ini lazim dan asal/pokok dalam syara’. Sedangkan poligami adalah sistem yang tidak lazim dan bersifat pengecualian. Sistem poligami menyalahi asal/pokok dalam syara’. Model poligami tidak bisa dijadikan tempat perlindungan (solusi) kecuali keperluan mendesak karenanya syariat Islam tidak mewajibkan bahkan tidak menganjurkan siapapun untuk melakukan poligami.
Syariat Islam hanya membolehkan praktik poligami dengan sebab-sebab umum dan sebab khusus,” (Az-Zuhaili, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, 1985: juz 7, halaman 169). Wallahu a’lam.
Ustadz Muhamad Abror, penulis keislaman NU Online, alumnus Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon dan Ma'had Aly Saidusshiddiqiyah Jakarta
Terpopuler
1
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
2
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
3
KH Thoifur Mawardi Purworejo Meninggal Dunia dalam Usia 70 tahun
4
Amalan Mengisi Rebo Wekasan, Mulai Mandi, Shalat, hingga Yasinan
5
Kuasa Hukum Rakyat Pati Mengaku Dianiaya hingga Disekap Berjam-jam di Kantor Bupati
6
Ramai Kritik Joget Pejabat, Ketua MPR Anggap Hal Normal
Terkini
Lihat Semua