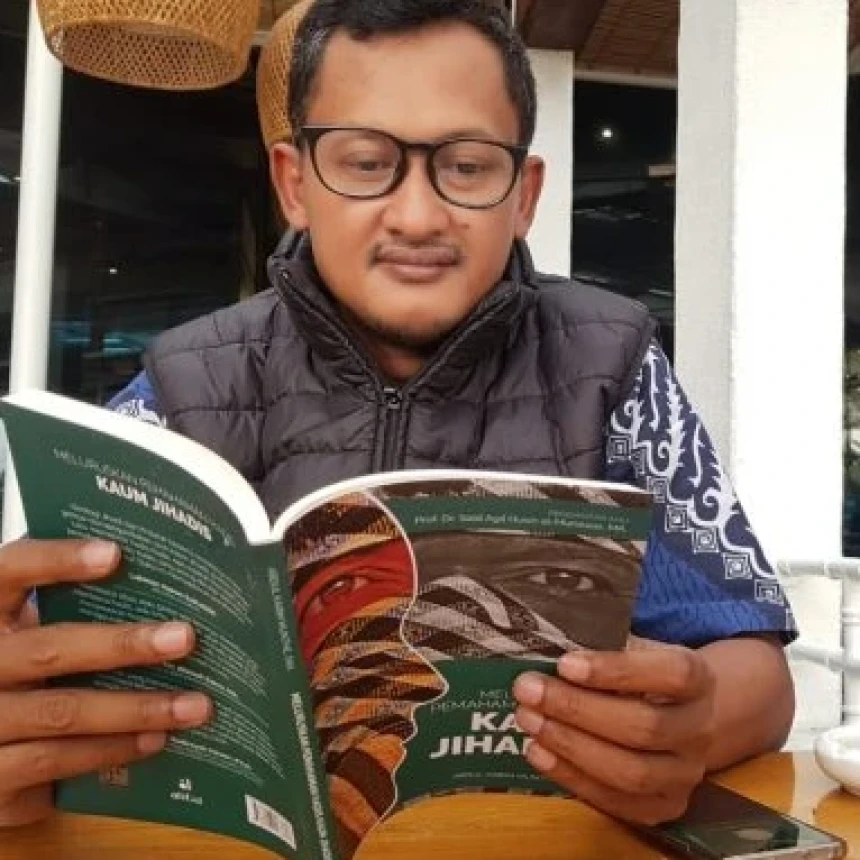Fatwa Memilih Paslon Tertentu, Bagaimana Etikanya?
NU Online · Senin, 12 Februari 2024 | 23:59 WIB
Amien Nurhakim
Penulis
Beberapa waktu lalu kita dihadapkan pada fatwa-fatwa yang muncul dari sebagian ulama di Indonesia tentang kewajiban memilih paslon tertentu. Fenomena ini nyatanya bukan hal baru. Pada pemilu 2019 pun kita mendapatkan fenomena serupa.
Apabila kita melihat definisi fatwa sendiri, urusan memilih pasangan capres-cawapres dapat dikategorikan sebagai perbuatan mukallaf dan dapat dipintakan fatwanya. Hal ini didasarkan pada definisi fatwa itu sendiri, yaitu ‘memberi informasi terkait hukum syara’, atau menjawab pertanyaan terkait hukum syara’ suatu perbuatan (Wahbah az-Zuhayli, Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami, [Damaskus: Darul Khayr, 2006], jilid II, hal. 377).
Dengan definisi di atas, maka relasi fatwa berkaitan dengan hukum perbuatan para mukalaf yang timbul akibat suatu peristiwa atau suatu hukum syara’ yang ditanyakan pada seorang mujtahid, ahli fiqih atau pun pelajar ilmu fiqih yang memahami hukum kasus tersebut. Syekh Wahbah berkata:
والإفتاء بيان لحكم اللَّه تعالى في أمور الدِّين، ويصدر عن العالم بشرع اللَّه تعالى، وهذا العالم إما أن يكون مجتهدًا لبيان الأحكام من أدلتها، وإما فقيهًا في اصطلاح الأوائل، وهو المجتهد، وإما متبعًا لمذهب بأن يعرف أحكام الفقه في المذهب مع أدلتها، وإما أن يكون متفقهًا، وهو من درس الفقه في مذهب ما، وعرف أحكامه، ثم يبيّنها للناس، وهم المستفتون أو المقلدون.
Artinya: “Fatwa adalah penjelasan tentang hukum Allah di bidang agama, dan dikeluarkan oleh seorang ulama yang mengetahui hukum agama, ulama tersebut bisa jadi seorang mujtahid yang dapat menjelaskan hukum berdasarkan dalil-dalilnya, atau ahli fiqih dalam terminologi ulama awal, yaitu seorang mujtahid, atau muttabi’ dalam satu mazhab, yang dia mengetahui hukum-hukum fiqih dalam mazhab tersebut beserta dalil-dalilnya, atau dia adalah ‘mutafaqqih’, yaitu orang yang mempelajari ilmu fiqih mazhab tertentu, mengetahui hukum-hukumnya, kemudian menjelaskannya kepada orang-orang yang meminta fatwa atau muqallid.” (Wahbah az-Zuhayli, Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh al-Islami, jilid II, hal. 377).
Apabila merujuk kepada penjelasan atas Undang-undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum, Pemilihan Umum merupakan sarana demokrasi guna mewujudkan sistem pemerintahan negara yang berkedaulatan rakyat. Pemerintah negara yang dibentuk melalui Pemilihan Umum itu adalah yang berasal dari rakyat, dijalankan sesuai dengan kehendak rakyat dan diabdikan untuk kesejahteraan rakyat.
Artinya tiap individu di negara kita memiliki hak untuk memilih siapapun paslonnya. Kendati demikian, dalam kacamata Islam, memilih capres-cawapres termasuk af’al mukallaf atau perbuatan kaum Muslimin yang diperhitungkan hukumnya.
Hal ini menjadikan umat Islam banyak mempertimbangkan siapa paslon yang akan dipilihnya. Sebab khawatir salah memilih dan akan berimbas pada tanggung jawabnya, maka ‘fatwa politik’ atau fatwa untuk memilih paslon tertentu pun dipinta kepada tokoh-tokoh yang dianggap otoritatif.
Menanggapi fenomena ini, dalam berfatwa tentu seseorang yang dinilai cukup kredibel pendapat dan pemikirannya di tengah masyarakat – dalam konteks masyarakat Indonesia dalam hal agama adalah kiai atau ustadz – harus mengikuti adab dan etika yang baik dalam mengeluarkan fatwa. Baik fatwa tersebut dikeluarkan secara individu maupun kolektif.
Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab al-Wajiz fi Ushulul Fiqh menjelaskan adab-adab seorang mufti, yaitu:
Baca Juga
Fatwa dan Fatwa
Pertama, mengedepankan takwa kepada Allah dalam mengeluarkan fatwa. Sebab fatwa bukanlah sembarang keputusan. Selain itu, orang yang berfatwa juga tidak boleh mengeluarkan fatwa karena keserakahan terhadap suatu jabatan, posisi tertentu atau gengsi, atau bahkan karena takut kepada penguasa. Ia harus meniatkan ijtihadnya sebagai bentuk pengabdian kepada Allah.
Kedua, orang yang mengeluarkan fatwa harus memiliki sifat-sifat kesalehan berupa taat pada agama dan hukum, memiliki perangai dan akhlak yang baik dan dapat diteladani serta tidak berbuat perkara yang menjatuhkan wibawanya.
Ketiga, orang yang berfatwa juga harus memiliki keilmuan dan pengetahuan yang luas, kesabaran, dan ketenangan. Dalam hal fatwa politik, tentunya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan kriteria pemimpin yang baik dalam sistem negara yang dianut harus dimiliki.
Keempat, orang yang mengeluarkan fatwa harus memiliki sifat wara’ dan kepatuhan pada agama yang terlihat secara lahiriah, di mana orang-orang mengakui bahwa dirinya sesuai dengan sifat tersebut. Sifat wara’ tentu akan membuat dirinya berhati-hati dalam berfatwa serta menjauhi harta yang tidak jelas status kehalalannya.
Kelima, orang yang berfatwa harus merupakan ahli hukum yang jiwanya berakal sehat, yang berakal budi, yang berakhlak dan berakal sehat, waspada terhadap apa yang disodorkan kepadanya, jauh dari lalai karena takut terjerumus ke dalam tipu muslihat dan jerat para penanya.
Keenam, tidak boleh mengeluarkan fatwa di saat kondisi psikologisnya tidak stabil, yaitu ketika dalam kondisi di mana hatinya sibuk dengan sesuatu yang menghalanginya untuk fokus. Kondisi demikian biasa terjadi saat marah, lapar, haus, sedih, gembira parah, ngantuk, bosan, jenuh karena cuaca, sakit, dan lain sebagainya.
Ketujuh, orang yang mengeluarkan fatwa harus bersikap lemah lembut dalam memahami pertanyaan.
Kedelapan, individu atau instansi yang bertugas mengeluarkan fatwa harus memiliki independensi dan kemerdekaan dalam berkehendak, serta keberanian sehingga tidak ada pihak-pihak yang dapat mengintervensinya dalam berfatwa.
Demikianlah penjelasan terkait dengan etika dan adab dalam berfatwa yang penting untuk dibaca siapapun yang kiranya berpotensi mengeluarkan atau dipintakan fatwa, baik dalam perihal agama maupun urusan dalam kehidupan manusia pada umumnya. Wallahu a’lam
Ustadz Amien Nurhakim, Musyrif Pesantren Darussunnah Jakarta
Terpopuler
1
Khutbah Jumat: Hikmah Zakat Fitrah, Menyucikan Jiwa dan Menyempurnakan Ibadah
2
Kapan Lebaran 2026? Berikut Data Hilal 1 Syawal 1447 H oleh LF PBNU
3
Khutbah Jumat: Urgensi I’tikaf di Masjid 10 Malam Terakhir Ramadhan
4
Khutbah Jumat: Puasa, Al-Qur’an, dan 5 Ciri Orang Bertakwa
5
KPK Resmi Tahan Gus Yaqut atas Tuduhan Korupsi Kuota Haji
6
Aktivis KontraS Andrie Yunus Disiram Air Keras Usai Hadiri Siniar
Terkini
Lihat Semua