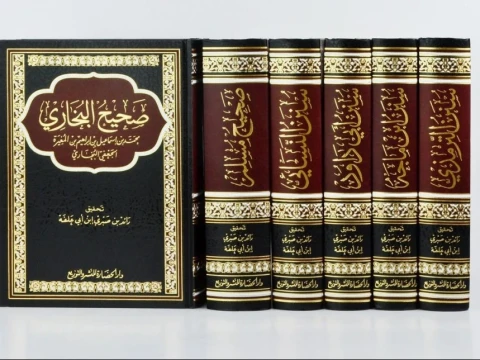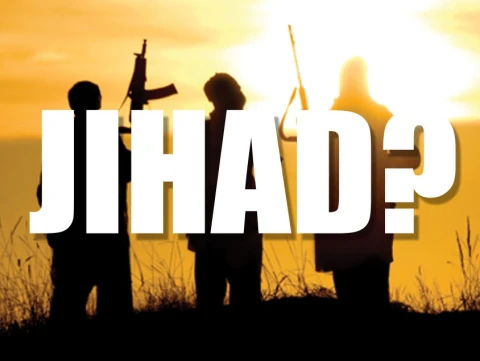Haji merupakan salah satu rukun Islam dan perintah yang wajib dilakukan oleh umat muslim. Kendati demikian, pada kenyataannya tidak semua orang Islam mampu melaksanakan ibadah haji karena beberapa faktor, baik berkaitan dengan fisik maupun finansial. Allah berfirman dalam Al-Quran:
وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًاۗ
Artinya: “(Di antara) kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, (yaitu bagi) orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana.” (QS Ali Imran: 97).
Berdasarkan ayat di atas, para sahabat menafsirkan istitha’ah atau kemampuan seseorang yang harus terpenuhi saat hendak melaksanakan ibadah adalah kemampuan ongkos dan kendaraan. (Syekh Wahbah az-Zuhaili, at-Tafsir al-Munir, [Beirut: Darul Fikr, 1418], jilid IV, hal. 15).
Adapun Kementerian Agama dalam buku Tuntunan Manasik Haji dan Umrah menjelaskan kemampuan haji (istitha’ah) juga berkaitan dengan kesehatan fisik dan juga mental. (Kementerian Agama RI, Tuntunan Manasik Haji dan Umrah, halaman 5).
Haji sendiri hukumnya wajib bagi seorang muslim yang mampu melakukannya minimal seumur hidup sekali, sebagaimana penuturan Syekh Sulaiman Bujairimi. (Al-Bujairimi, Bujairimi ‘alal Khatib, [Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, 1996], jilid III, halaman 179-180).
Dengan adanya syarat-syarat ukuran kemampuan haji bagi umat muslim yang hendak melaksanakannya, maka ibadah haji menjadi bentuk ritual yang sangat istimewa kedudukannya bagi umat Islam. Setiap muslim yang tidak mampu banyak memanjatkan doa agar ‘dipanggil’ ke hadapan Baitullah atau Ka’bah, sebagai bentuk kepasrahan terhadap kuasa Allah Ta’ala.
Kendati demikian, kita tidak dapat menafikan boleh jadi ada individu-individu dari kalangan muslim yang tidak begitu menginginkan haji dengan beragam alasan meskipun dirinya mampu. Ketiadaan kehendak ini bukan semata-mata karena tertahan oleh sesuatu, tetapi memang dirinya tidak menginginkan pergi menunaikan kewajiban haji.
Penulis pernah mendengar seorang khatib mengutip sebuah hadits yang menjelaskan apabila seorang muslim dinilai telah mencapai istitha’ah atau kemampuan haji, namun dalam seumur hidupnya tidak ada keinginan untuk berhaji maka dirinya boleh jadi wafat dalam agama Yahudi atau Nasrani. Berikut haditsnya:
مَنْ لَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ الْحَجِّ حَاجَةٌ ظَاهِرَةٌ أَوْ سُلْطَانٌ جَائِرٌ أَوْ مَرَضٌ حَابِسٌ فَمَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ فَلْيَمُتْ إِنْ شَاءَ يَهُودِيًّا وَإِنْ شَاءَ نَصْرَانِيًّا
Artinya, “Siapa pun tidak terhalang untuk melakukan haji oleh suatu hajat yang jelas atau oleh penguasa yang lalim atau penyakit yang menahannya, kemudian ia meninggal dan belum melakukan haji, bisa jadi ia meninggal dalam keadaan sebagai Yahudi atau sebagai Nasrani.” (HR Ad-Darimi dan Al-Baihaqi dalam al-Sunan al-Kabir).
Kajian sanad hadits
Terkait kualitas hadits tersebut, Al-Mubarakfuri dalam Tuhfatul Ahwadzi menjelaskan bahwa ada dua orang perawi yang dinilai dha’if di kalangan kritikus hadits. Pertama, Laits merupakan perawi yang dha’if, sedangkan yang kedua adalah Syarik, dia merupakan perawi yang buruk hafalannya dan kerap menyelisihi Sufyan ats-Tsauri. (Al-Mubarakfuri, Tuhfatul Ahwadzi, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.], jilid III, hal. 457).
Asy-Syawkani dalam Naylul Awthar membahas hadits di atas dengan paparan yang cukup detail dalam bab “Melaksanakan Haji Tanpa Menunda-nunda”. Ia melampirkan hadits lain dengan lafaz yang berbeda dari Sunan at-Tirmidzi, yaitu:
عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَلَكَ زَادًا وَرَاحِلَةً تُبَلِّغُهُ إِلَى بَيْتِ اللَّهِ وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَنْ يَمُوتَ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ { وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا }
Artinya, “Diriwayatkan dari ‘Ali, ia berkata, ‘Rasulullah saw bersabda, ‘Siapa pun yang memiliki bekal dan kendaraan yang cukup untuk dijadikan bekal ke Baitullah, namun dia tidak pergi haji, aku tidak peduli jika dia mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Karena Allah berfirman dalam kitab-Nya: 'Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah’.” (HR at-Tirmidzi).
Dalam riwayat lanjutan, At-Tirmidzi mengonfirmasi kualitas sanad hadits yang diriwayatkannya, “Hadits ini merupakan hadits gharib yang tidak kami ketahui kecuali melalui sanad ini, bahkan pada sanadnya terdapat cacat. Hilal bin Abdullah majhul dan Harits seorang yang didha'ifkan dalam haditsnya.” Demikianlah ungkap asy-Syaukani. (Asy-Syaukani, Naylul Awthar, [Mesir: Darul Hadits, 1993], jilid IV, hal. 337).
Al-Baihaqi sendiri mengomentari bahwa sanad hadits tersebut tidaklah kuat, hanya saja hadits tersebut memiliki riwayat pendukung dari perkataan ‘Umar. Artinya riwayat pendukung tersebut bukan berasal dari hadits Nabi, namun perkataan sahabat. (Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kabir, [Kairo, Markaz Hijr: 2011], jilid IX, halaman 227).
Terkait dengan perkataan ‘Umar yang dimaksud oleh al-Baihaqi, Ibnu Hajar al-‘Asqalani melampirkan perkataan ‘Umar yang memiliki sanad yang shahih dibandingkan hadits di atas, yaitu:
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنَّ أَبْعَثَ رِجَالًا إِلَى هَذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَّةٌ فَلَمْ يَحُجَّ، فَيَضْرِبُوا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَا هُمْ بمسلمين، ما هم بمسلمين
Artinya, “Saya bertekad untuk mengutus beberapa orang ke berbagai penjuru negeri ini, untuk memeriksa siapa diantara mereka yang memiliki harta, namun dia tidak berhaji, kemudian mereka diwajibkan membayar jizyah. Mereka bukan bagian dari kaum muslimin! mereka bukan bagian dari kaum muslimin!” (Ibnu Hajar al-‘Asqalani, Talkhishul Habir, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1989], jilid II, hal. 488).
Adapun terkait dengan substansi hadits tersebut, Al-Baihaqi mengomentari, boleh jadi yang dimaksud dari hadits di atas adalah seseorang yang tidak melaksanakan haji, seraya meyakini bahwa haji tidak memiliki implikasi apapun. Yakni, jika ditinggalkan tidak mendapat dosa, dan jika dilaksanakan tidak mendapat pahala. (Al-Baihaqi, Syu’abul Iman, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1410], jilid III, hal. 430).
Dengan demikian, penjelasan Al-Baihaqi merujuk pada segelintir orang yang tidak meyakini kewajiban haji sebagai rukun Islam kelima. Sehingga penyerupaan dengan Yahudi maupun Nasrani merujuk kepada ketiadaan pengakuan terhadap pilar Islam yang kelima.
Senada dengan penjelasan al-Baihaqi, Ibnu Rajab dalam Jami’ul ‘Ulum wal Hikam menjelaskan bahwa sikap ‘Umar tersebut didasarkan pada keyakinannya bahwa orang muslim yang mampu namun tidak mau berhaji sama seperti ahli kitab. Efeknya, ‘Umar menetapkan atas mereka pungutan jizyah sebagaimana halnya yang diterapkan kepada ahli kitab. (Ibnu Rajab al-Hanbali, Jami’ul ‘Ulum wal Hikam, [Suriah: Darus Salam, 2004], jilid I, hal. 113).
Berbeda kasus dengan orang yang mampu melaksanakan haji, kemudian bertekad melaksanakannya namun ternyata maut menjemputnya, maka harus ada orang yang menjadi badal haji baginya. Namun apakah ia wafat dalam keadaan berdosa atau tidak, maka para ulama terbagi kepada 3 pendapat sebagaimana dipaparkan dalam al-Majmu’ syarh al-Muhadzdzab, sebagaimana berikut:
- Pendapat yang paling sahih yang dipegang oleh mayoritas ulama Irak, dan dikutip oleh al-Qadhi Abu Tayyib dan lainnya sebagai kesepakatan, adalah bahwa dia mati dalam keadaan berdosa.
- Pendapat kedua menyatakan bahwa dia tidak berdosa karena ulama Syafi’iyyah telah memutuskan bahwa penundaan itu diperbolehkan.
- Pendapat ketiga menyatakan bahwa apabila dia sudah tua, maka berdosa, sedangkan jika masih muda maka tidak. Alasannya, karena orang tua dianggap telah lalai padahal potensi mereka mendekati wafat lebih dekat. (Al-Muthi’i, Takmilah al-Majmu’, [Beirut: Darul Fikr, t.t.], jilid VII, hal. 111).
Al-Muthi’i dalam kasus ini lebih condong kepada pendapat bahwa dirinya tetap terkena dosa karena menyia-nyiakan haji dengan sengaja, hingga akhirnya ajal menjemput. (Al-Muthi’i, Takmilah al-Majmu’, jilid VII, hal. 111).
Kesimpulan
Dengan adanya pemaparan panjang di atas, bahwa hadits yang disebut memang tidak sahih berasal dari Nabi saw sebab tidak terpenuhinya standar sahih menurut ulama hadits. Kendati demikian para fuqaha tetap memandang orang yang mampu melaksanakan haji namun enggan, maka terkena dosa karena tidak menunaikan rukun Islam yang kelima.
Lebih dari itu, apabila dirinya mengingkari rukun Islam yang kelima, semisal tidak meyakini kewajiban haji, menganggap haji tidak memiliki status hukum apabila dilaksanakan atau ditinggalkan, maka dia bukanlah seorang muslim sebagaimana sikap ‘Umar. Wallahu a’lam
Ustadz Amien Nurhakim, Penulis Keislaman NU Online dan Dosen Universitas PTIQ Jakarta