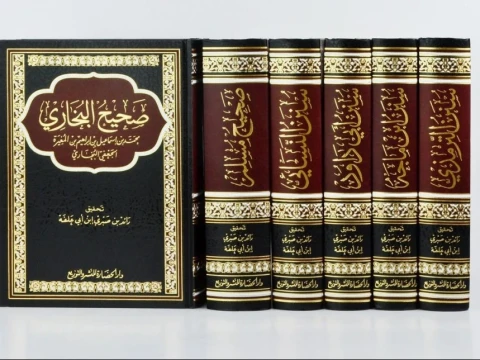Beberapa waktu lalu, sempat viral di media sosial terkait cuitan salah satu akun yang melampirkan terjemahan sebuah hadits yang berbunyi, “Barangsiapa yang mendengar adzan namun tidak mendatanginya, maka tidak ada shalat baginya kecuali [memiliki] udzur.” (HR Abu Dawud dan Ibnu Majah). Teks asli hadits tersebut adalah:
مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ، فَلَا صَلَاةَ لَهُ، إِلَّا مِنْ عُذْرٍ
Artinya, ”Siapapun yang mendengar azan kemudian tidak mendatanginya, maka shalatnya tidak sempurna, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur.” (HR. Ibnu Majah)
Tidak ada yang salah dari teks hadits, bahkan kualitas sanadnya shahih sebagaimana penuturan Ibnul Atsir dalam Jami’ul Ushul. Hanya saja an-Nawawi dalam al-Majmu’ syarhul Muhadzdzab menyatakan ada perawi dalam sanad Abu Dawud yang dha’if dan mudallis (perawi kerap menyembunyikan fakta, baik dalam sanad atau matan), namun luput dari penilaian Abu Dawud (An-Nawawi, al-Majmu’, [Beirut: Darul Fikr, t.t.], jilid IV, hal. 205).
Terkait pemaknaan tekstual pun tidak ada masalah, sebab sebagian ulama ada yang mengatakan demikian, di antaranya adalah Ath-Thibi dan Abu Tsaur, berdasarkan hadits dalam Shahih Muslim yang menjadi penguat bagi hadits di atas, yaitu:
عن أبي هريرة، قال: أتَى النبي صلى الله عليه وسلم رجُلٌ أعْمَى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يَقُودُني إلى المسجد، فَسَأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُرَخِّص له فيصلِّي في بَيْتِه، فرَخَّص له، فلمَّا ولىَّ دَعَاه، فقال: هل تسمع النِّداء بالصلاة؟ قال: نعم، قال: فأجِب
Artinya, “Abu Hurairah bercerita, ‘Seorang laki-laki buta datang kepada Nabi saw lalu ia berkata, ‘Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku tidak memiliki penuntun yang mengarahkanku pergi ke masjid.’ Lalu ia meminta kepada Rasulullah saw untuk memberinya keringanan mengerjakan salat di rumah. Beliau pun memberinya keringanan. Namun, ketika orang tersebut beranjak pergi, beliau memanggilnya kembali kemudian bertanya, ‘Apakah engkau mendengar seruan azan?’ Ia menjawab, ‘Ya.’ Beliau bersabda, ‘Penuhilah!’ (HR Muslim).
Berbeda dengan ath-Thibi dan Abu Tsaur, Ibnu Hajar menyatakan tidak ada indikasi fardhu ‘ayn (kewajiban personal) dalam hal shalat jamaah bagi seseorang yang memiliki uzur bahkan untuk sebagian ulama mazhab Syafi’i, hukumnya adalah fardhu kifayah (kewajiban kolektif). (Al-Mula Al-Harawi, Mirqatul Mafatih, [Beirut: Darul Fikr, 2002], jilid III, hal. 834).
Lebih lanjut lagi, Ibnu Hajar al-‘Asqallani tidak berhenti pada sanggahan akan pendapat kewajiban shalat jamaah bagi tiap muslim. Dalam ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsil Hidayah, Ibnu Hajar melampirkan hadits-hadits yang menjadi pembanding hadits di atas, agar kaum muslimin dapat memahami bahwa shalat sendiri pun tetap sah.
Riwayat yang dijadikan pijakan oleh Ibnu Hajar ialah hadits yang diriwayatkan Ibnu ‘Umar, yaitu:
عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة
Artinya, “Diriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar, bahwa Rasulullah bersabda, ‘Shalat jamaah lebih baik dari pada shalat sendirian dengan pahala 27 derajat’.” (HR Al-Bukhari).
Secara tekstual, adanya perbandingan dari hadits di atas menegaskan shalat jamaah merupakan impelementasi dari bentuk shalat yang sempurna, sementara shalat sendiri tetap sah, hanya saja tidak sempurna layaknya shalat jamaah (Ibnu Hajar al-‘Asqallani, ad-Dirayah fi Takhrij Ahaditsil Hidayah, [Beirut: Darul Ma’rifah, t.t.], jilid I, hal. 166).
Perbedaan pendapat di atas merupakan bukti bahwa satu teks hadits dapat memiliki ragam penafsiran, termasuk di tengah para fuqaha atau ahli fiqih. As-Sindi misalnya, memilih untuk menafsir secara tekstual bahwa hadits di atas merupakan bentuk kewajiban jamaah bagi orang yang belum shalat, kemudian mendengar azan pada masjid terdekat.
Di sisi lain, As-Sindi sendiri mengakui bahwa para fuqaha tidak menafsirkannya secara tekstual. Bagi para fuqaha, menurut as-Sindi, makna yang dikandung dalam hadits ‘la shalata lahu’ atau ‘tidak ada shalat baginya’ adalah berkurangnya kesempurnaan shalat (As-Sindi, Hasiyatus Sindi ‘ala Sunan Ibn Majah, [Beirut: Darul Jayl, t.t.], jilid I, hal. 266).
Dengan nalar perbandingan yang dilakukan oleh para ahli fiqih, maka kurang lebih makna hadits yang tepat adalah, “Lelaki muslim yang mendengar azan dan memungkinkannya untuk berjamaah namun ia tidak melaksanakannya, maka tidak mendapat kesempurnaan dan keutamaan shalat.”
Lebih detailnya lagi dalam rangka menepis pemahaman yang parsial, baiknya kita gunakan nalar perbandingan al-Mawardi pada riwayat-riwayat terkait shalat jamaah secara komprehensif dalam al-Hawil Kabir (Al-Mawardi, al-Hawil Kabir, [Beirut: Darul Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994], jilid II, hal. 300).
Pertama, al-Mawardi menegaskan bahwa ulama Mazhab Syafi’i sepakat bahwa shalat jamaah bukan fardhu ‘ayn (kewajiban individu). Alasannya adalah ditemukannya riwayat, salah satunya dari Imam asy-Syafi’i yang menyebut shalat jamaah lebih baik dari shalat sendiri dengan bandingan 27 derajat.
Artinya kedua jenis shalat, baik sendiri maupun jamaah sama-sama sah, hanya saja jamaah lebih baik daripada shalat sendiri. Lalu apabila ada yang mengatakan, “Bukan begitu maksudnya! Maksudnya adalah shalat jamaahnya orang yang sedang memiliki uzur, lebih utama baginya daripada shalat sendiri!.”
Tafsiran di atas menurut al-Mawardi tidak tepat, karena ada hadits lainnya yang menyatakan orang sakit ketika melaksanakan shalat sendirian, maka pahalanya dinilai layaknya shalat jamaah subuh, atau lebih sederhananya pahalanya besar layaknya shalat berjamaah di waktu subuh yang dinilai sulit dilakukan oleh umat Islam.
Selanjutnya, ada hadits lain yang menganulir pendapat wajibnya shalat jamaah, yaitu hadits yang diriwayatkan oleh Ubay bin Ka’ab dengan teks yang cukup panjang terkait keutamaan shalat jamaah Subuh dan ia merupakan shalat jamaah yang paling sulit dilakukan umat Islam. Penggalan hadits tersebut adalah:
وَإِنَّ صَلَاةَ الرَّجُلِ مَعَ الرَّجُلِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ وَحْدَهُ وَصَلَاتُهُ مَعَ الرَّجُلَيْنِ أَزْكَى مِنْ صَلَاتِهِ مَعَ الرَّجُلِ وَمَا كَثُرَ فَهُوَ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى
Artinya, “Sesungguhnya shalat seseorang yang berjamaah dengan satu orang, adalah lebih baik daripada shalat sendirian. Lalu shalatnya bersama dua orang jamaah, adalah lebih baik daripada shalat bersama satu orang jamaah. Semakin banyak jama'ahnya, maka semakin dicintai oleh Allah Ta'ala." (HR Abu Dawud).
Al-Mawardi memaparkan secara logis bahwa Nabi saw juga membandingkan keutamaan shalat berjamaah dengan shalat sendirian dengan patokan jumlah orang yang berpartisipasi di dalamnya. Semakin banyak orang yang berpartisipasi, maka semakin baik.
Tentu saja hadits di atas menunjukkan bahwa shalat berjamaah bukanlah kewajiban, karena tidak ada pernyataan yang menganulir bahwa shalat sendiri tidak sah. Hanya saja shalat sendiri kurang sempurna jika dibanding shalat jamaah bersama satu orang, dan makin banyak orang yang berpartisipasi dalam jamaah maka semakin banyak keutamaannya.
Al-Mawardi juga memaparkan lebih lanjut, ada sebuah riwayat yang menceritakan suatu hari ada sahabat yang terlambat shalat jamaah. Nabi pun berkata kepada orang-orang yang hadir di masjid, “Siapa yang hendak bersedekah dengan cara shalat berjamaah dengan orang ini?”
Logika al-Mawardi, apabila shalat jamaah hukumnya adalah wajib, maka Rasulullah tidak akan bersikap seperti itu. Tentu yang dilakukan Rasulullah adalah menggertaknya sebab ia telah meninggalkan kewajiban, kemudian melarangnya dari keterlambatan mengikuti jamaah.
Akan tetapi nyatanya yang dilakukan Rasulullah adalah menawarkan para sahabat yang lain untuk berderma dengan melakukan shalat jamaah bersama satu orang sahabat yang tertinggal itu, sehingga keduanya sama-sama mendapatkan keutamaan.
Kemudian, apabila dihadapkan pada sebuah hadits yang mengisahkan Rasulullah konon bertekad membakar rumah orang-orang muslim yang meninggalkan shalat jamaah, teksnya adalah, Rasulullah saw bersabda:
لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلَاةِ فَتُقَامَ ثُمَّ آمُرَ رَجُلًا فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ ثُمَّ أَنْطَلِقَ بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَمٌ مِنْ حَطَبٍ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَأُحَرِّقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ بِالنَّارِ
Artinya, “Aku sangat berkeinginan agar shalat ditegakkan, lalu aku perintahkan seorang laki-laki shalat berjamaah, sedangkan aku bersama beberapa laki-laki pergi membawa kayu bakar menuju orang-orang yang tidak ikut shalat berjama'ah, hingga aku dapat membakar rumah mereka.” (HR. Ibnu Majah).
Menanggapi hadits di atas, al-Qurthubi menjelaskan jika hadits ini digunakan sebagai dalil wajibnya shalat jamaah seperti yang dilakukan Abu Tsaur maka kurang tepat, sebab Nabi saw dalam konteks hadits tersebut hanya berniat membakar tanpa melakukannya.
Nabi saw mengatakan seperti itu dalam bentuk ancaman keras bagi orang-orang munafik yang meninggalkan shalat jamaah dan shalat Jum’at. (Al-Qurthubi, al-Mufhim lima Asykala min Talkhish Kitab Muslim, [Beirut: Dar Ibn Katsir, 1996], jilid II, hal. 276).
Selain al-Qurthubi, al-Mawardi juga menyanggah pemahaman tekstual orang-orang yang berpendapat shalat jamaah adalah wajib berdasarkan hadits kisah Nabi ingin membakar rumah orang-orang yang tidak shalat berjamaah.
Menurut al-Mawardi, ‘membakar rumah’ di atas tentunya adalah ancaman yang tidak boleh dipraktikkan. Alasannya adalah adanya ijma’ terkait larangan membakar rumah dan melenyapkan harta seseorang yang tidak ikut jamaah.
Selain itu, menurut al-Mawardi juga pada hakikatnya orang yang di rumahnya telah melaksanakan shalat secara berjamaah dengan keluarganya secara otomatis telah menggugurkan kewajiban shalat dan tidak mendapatkan dosa (Al-Mawardi, al-Hawil Kabir, jilid II, hal. 300).
Dengan demikian, maka hadits di awal tulisan yang menjadi sumber persoalan karena dilempar begitu saja secara tekstual harus dimaknai secara bijaksana supaya tidak mengagetkan orang-orang.
Para ulama besar layaknya Ibnu Hajar, Zakaria al-Anshari, al-Bujairimi, al-Khathib asy-Syirbini bahkan Imam asy-Syafi’i tentu lebih dahulu mengetahui akan eksistensi hadits tersebut. Bedanya, mereka tidak langsung memproduksi hukum dengan satu hadits saja, akan tetapi melakukan komparasi kepada berbagai hadits sehingga pemahaman terhadap hukumnya tampak utuh dan komprehensif serta tidak parsial. Wallahu a’lam
Ustadz Amien Nurhakim, Penulis Keislaman NU Online dan Dosen Fakultas Ushuluddin, Universitas PTIQ Jakarta