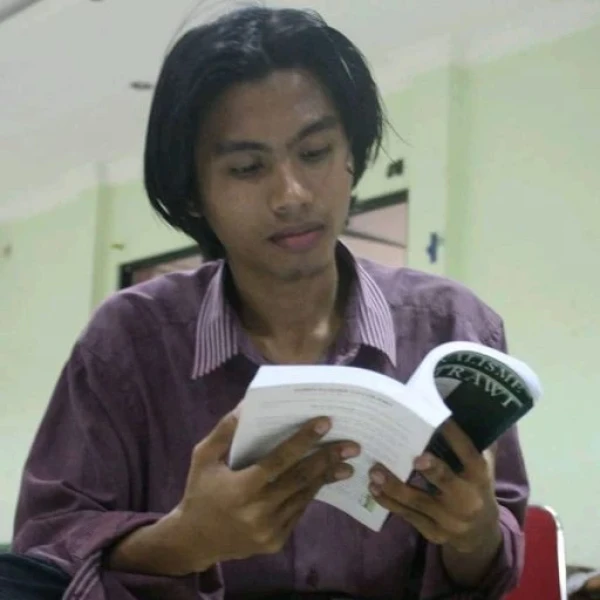Tafsir Surat Al-Baqarah Ayat 181: Anjuran Meninggalkan Wasiat Sebelum Meninggal Dunia
NU Online · Selasa, 20 Mei 2025 | 09:00 WIB
Zainuddin Lubis
Penulis
Kematian tidak selesai dengan kematian itu sendiri. Kematian, akhirnya, bukanlah titik. Ia hanya koma—sebuah tanda yang memberi jeda, namun tidak memutuskan. Goethe pernah berkata, “Manusia tak pernah mati; ia hanya berubah wujud.” Dalam Islam, barangkali, kalimat itu menemukan maknanya dalam wasiat.
Karena di situ, seseorang mengucapkan sesuatu setelah mulutnya tak lagi bisa bicara. Wasiat adalah suara terakhir yang tak pernah benar-benar terakhir. Ia menyambung hidup dalam cara yang tak terduga, sejenis pesan yang menyambung hidup seorang manusia bahkan setelah tubuhnya menyatu dengan tanah.
Namun, Islam tidak memberi keleluasaan penuh pada keinginan pribadi. Wasiat dibatasi: tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta. Selebihnya, adalah hak para ahli waris yang telah ditentukan dengan tegas dalam Al-Qur’an. Batas sepertiga ini bukan sekadar angka; ia adalah teguran halus agar kita tidak pongah bahkan dalam kematian. Kita boleh berkehendak, tapi tidak untuk seluruhnya. Ada ruang bagi Tuhan untuk menata, bahkan ketika kita sudah tiada.
Barangkali itulah yang membedakan wasiat dari warisan. Warisan adalah hak; wasiat adalah amanah. Dan dalam amanah itu, tersimpan harapan: agar apa yang kita tinggalkan bisa menjadi kebaikan yang terus mengalir. Sedekah yang hidup lebih lama dari tubuh kita sendiri.
Dalil tentang anjuran meninggalkan wasiat tertuang dalam firman Allah lewat surat Al-Baqarah ayat 180:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ اِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ الْمَوْتُ اِنْ تَرَكَ خَيْرًاۖ ࣙالْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْاَقْرَبِيْنَ بِالْمَعْرُوْفِۚ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِيْنَۗ ١٨٠
kutiba ‘alaikum idzâ ḫadlara aḫadakumul-mautu in taraka khairanil-washiyyatu lil-wâlidaini wal-aqrabîna bil-ma‘rûf, ḫaqqan ‘alal-muttaqîn
Artinya, "Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."
Prof. Quraish Shihab menyibak makna ayat 180 dari Surat Al-Baqarah, bahwa ajal bukan hanya sebuah akhir, melainkan awal dari tanggung jawab yang belum selesai. Ayat 180 itu menegaskan, bila kematian mulai menyapa — entah lewat sakit, uban atau batuk yang tak kunjung reda, maka manusia diperintahkan menyusun wasiat. (Profesor Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah, [Ciputat: Penerbit Lentera Hati, 2002], Jilid I, halaman 397).
Kata Prof. Quraish, wasiat secara bahasa diartikan sebagai pesan baik yang disampaikan kepada orang lain untuk dilaksanakan, baik saat si pemberi pesan masih hidup maupun setelah ia wafat. Namun, secara umum, istilah wasiat digunakan untuk pesan-pesan yang dilaksanakan setelah kematian.
Kata "kutiba" muncul dalam teks. Artinya: diwajibkan. Maka, wasiat bukan sekadar anjuran moral; ia bertransformasi menjadi hukum. Bahkan, oleh sebagian ulama, dikatakan: wajib. Berapa pun jumlah hartanya. Tapi seperti hukum-hukum yang lain dalam kitab suci, tafsirnya kerap bercabang seperti akar pohon tua yang merambat ke berbagai arah.
Pemilihan kata ini menunjukkan bahwa wasiat memiliki bobot kewajiban, bukan hanya anjuran. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika banyak ulama dari berbagai mazhab fiqih mewajibkan wasiat bagi mereka yang memiliki sesuatu untuk ditinggalkan. Penegasan bahwa wasiat adalah haq, sebuah hak yang harus diberikan kepada yang berhak, semakin menguatkan posisi wasiat sebagai tindakan yang tidak boleh diabaikan, terutama jika seseorang mengetahui bahwa hidupnya berada di ambang batas.
Menariknya, tanda-tanda menjelang kematian tidak selalu hadir dalam bentuk penyakit kronis atau kecelakaan mendadak. Dalam Islam, tanda-tanda ini bisa sangat halus dan perlahan, seperti rambut yang mulai memutih, gigi yang mulai rontok, menurunnya kesehatan, atau usia yang kian senja. Semua itu merupakan isyarat dari alam bahwa ajal kian mendekat. Maka, menunda-nunda membuat wasiat padahal tanda-tanda tersebut sudah hadir, merupakan bentuk kelalaian terhadap kewajiban yang telah Allah tetapkan.
Sejatinya, dalam Kompilasi Hukum Islam [KHI], dijelaskan tentang syarat wasiat pada Pasal 194:
- Setiap orang yang telah berusia sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan, berhak untuk mewasiatkan sebagian dari harta bendanya kepada orang lain atau kepada suatu lembaga.
- Harta benda yang dapat diwasiatkan adalah harta yang menjadi hak milik sah dari pewasiat.
- Kepemilikan terhadap harta benda yang diwasiatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku dan dapat dilaksanakan setelah pewasiat meninggal dunia.
Selanjutnya, Pasal 195, KHI juga mengatur tentang tata cara pelaksanaan wasiat dalam hukum waris, yang dapat dilakukan dengan beberapa metode. Wasiat sah dilakukan secara lisan di hadapan dua orang saksi, atau secara tertulis dengan kehadiran dua orang saksi, maupun di hadapan seorang notaris. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin keabsahan dan kejelasan dari isi wasiat yang dibuat oleh pewaris, serta untuk menghindari sengketa di kemudian hari terkait dengan keinginan pewaris atas harta bendanya.
Selain itu, di Pasal 195, juga menegaskan batasan jumlah harta yang dapat diwasiatkan, yaitu maksimal sepertiga dari total harta warisan. Pengecualian terhadap batasan ini hanya diperbolehkan apabila seluruh ahli waris memberikan persetujuan. Bahkan jika wasiat ditujukan kepada salah satu ahli waris, maka pelaksanaannya tetap memerlukan persetujuan dari semua ahli waris yang lain.
Sementara itu, Ibnu Asyur dalam kitab Tafsir Tahrir wa Tanwir, Syekh Muhammad al-Tahir Ibnu 'Asyur menyebut ayat ini dengan cakupan yang luas, tidak hanya sebatas hukum waris dalam fiqh, melainkan juga mengupas dimensi sosial, psikologis, dan moral yang terkandung dalam perintah ini.
Baginya, wasiat bukan hanya perintah hukum, tapi juga pernyataan etika. Ia bicara bukan sekadar tentang harta, tapi tentang ketegangan batin, tentang hubungan yang, kalau tak ditata, bisa retak oleh warisan yang salah niat.
Yang menarik, kata Ibnu Asyur, ayat ini, tidak seperti banyak ayat hukum lain, tak dibuka dengan sapaan khas: “Wahai orang-orang yang beriman.” Tak ada panggilan khusus, seolah Tuhan menyapa semua, tanpa prasangka iman, tanpa prasyarat taat. Karena wasiat, tampaknya, telah lebih dulu dikenal oleh masyarakat Jahiliah. Bukan hal baru yang dibawa wahyu, melainkan tradisi tua yang kini ingin diperhalus.
Masyarakat sebelum Islam, tulis mufassir asal Tunisia ini, mengenal wasiat dengan caranya sendiri. Namun sering kali ia menjadi alat menunggu ajal orang lain, sejenis keserakahan yang berkamuflase sebagai kesabaran. Kerabat bukan lagi jalinan kasih, tapi penanda siapa akan mendapat bagian paling besar. Maka, Islam datang, bukan untuk membatalkan, tapi untuk memperbaiki. Seperti halnya air yang tak melawan api, tapi memadamkannya perlahan. Dengan kata lain, ayat ini bukan memerintahkan hal asing, tetapi memperbaiki sesuatu yang sudah ada agar lebih adil dan bermartabat.
Ibnu Asyur memandang ayat ini sebagai koreksi sosial. Pasalnya, pembagian waris di masyarakat jahiliyah tidak adil. Dalam kondisi tersebut, ahli waris sering mengabaikan orang tua dan kerabat dekat. Alasannya, mereka kadang dituduh "orang" yang menanti kematian pewaris untuk mendapatkan harta. Ayat ini datang membela mereka-- orang tua dan kerabat dekat--, yang sering kali dilupakan karena hukum waris bisa bersifat teknis. Dan di situlah letak keindahan Islam: ketika hukum tak kehilangan hati.
Salah satu latar belakang historis turunnya ayat ini adalah kerusakan sosial akibat praktik waris dan wasiat yang tidak adil di masyarakat jahiliah. Dalam kondisi tersebut, ahli waris sering mengabaikan orang tua dan kerabat dekat, bahkan saling menanti kematian pewaris untuk mendapatkan harta.
Pun konflik dan permusuhan menjadi hal yang lumrah, yang secara psikologis menggoreskan luka mendalam. Syair Tarafah yang mengungkapkan bahwa betapa hubungan kekeluargaan bisa rusak karena sengketa warisan.
وَظُلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشُدُّ مَضَاضَةً ... عَلَى الْمَرْءِ مِنْ وَقْعِ الْحُسَامِ الْمُهَنَّدِ
Artinya, "Kezaliman yang dilakukan oleh kerabat lebih menyakitkan bagi seseorang daripada tebasan pedang yang tajam."
Di tengah kerusakan itulah Islam meletakkan wasiat sebagai alat perbaikan. Bukan sekadar distribusi kekayaan, tapi juga pemulihan luka sosial. Menarik bahwa ayat ini diletakkan berdekatan dengan ayat tentang qishash, tentang pembalasan atas kematian. Seakan ingin berkata: dalam menghadapi kematian, keadilan harus hadir. Bukan sebagai pedang, tapi sebagai keseimbangan.
Ibnu Asyur menaruh perhatian pada satu frasa: ḥaḍara al-mawt, “datangnya maut.” Bukan kematian yang masih jauh dan diperkirakan, tapi yang telah terasa di napas, yang ditunjukkan lewat sakit keras. Dalam momen itu, ketika waktu tinggal sisa, seseorang diminta menyusun ulang hidupnya dengan wasiat: kepada siapa hartanya akan pergi, kepada siapa kasih yang belum selesai akan ditunaikan dalam bentuk amanah.
Wasiat, dalam pandangan Ibnu Asyur, bukanlah sekadar surat hukum. Ia adalah amanah. Sebuah ikrar terakhir dari manusia kepada sesamanya, bahwa walau ia tak akan ada lagi, kebaikan masih bisa berlangsung. Terutama kepada mereka yang sering terlewat dalam sistem waris yang resmi: orang tua, kerabat, atau hamba sahaya. Wasiat menjadi jembatan antara norma legal dan nurani sosial.
Islam meletakkan etika di dalam hukum. Kata bil-ma’ruf yang digunakan ayat ini menunjukkan bahwa wasiat bukan saja harus adil secara teknis, tapi juga bijak, santun, dan tidak membakar kecemburuan. Wasiat yang sah bisa saja menyulut perang, tapi wasiat yang ma’ruf menyelamatkan silaturahmi. Inilah seni sosial dalam agama: mengatur bukan hanya dengan akal, tapi juga hati.
Ibnu Asyur mengaitkan kewajiban berwasiat dengan ketakwaan. Mereka yang bertakwa, katanya, justru yang paling pantas menjadi teladan dalam menyelesaikan urusan dunia. Takwa, dalam tafsir ini, tidak dibiarkan menggantung di langit. Ia ditarik turun ke bumi: ke akta, ke surat, ke relasi sosial.
Secara hukum, Ibnu Asyur membaginya dua: wasiat adalah kewajiban pribadi (fardhu ‘ain) bagi yang berharta dan tengah mendekati ajal. Tanpa itu, wasiat menjadi ruang kosong bagi konflik. Dalam dunia yang sering kali riuh oleh sengketa setelah kematian, wasiat adalah bentuk tanggung jawab spiritual agar yang hidup tak saling mencakar demi harta mati.
Namun, terdapat perdebatan di kalangan ulama tentang status hukum wasiat setelah turun ayat-ayat hukum warisan yang lebih rinci. Ada pendapat bahwa ayat wasiat ini dinasakh (dihapus) oleh hukum warisan sehingga wasiat hanya menjadi pelengkap atau tambahan. Tetapi Syekh Ibnu Asyur condong pada pendapat yang lebih moderat dan kuat bahwa hukum wasiat tetap berlaku, khususnya bagi pihak yang tidak termasuk ahli waris seperti orang tua non-Muslim, hamba sahaya, dan kerabat dekat lainnya, atau siapa pun yang mungkin tertinggal di belakang sistem.
Pendekatan ini terasa lebih manusiawi. Sebab hukum, betapapun mulia, tak selalu cukup untuk menjangkau keunikan tiap kehidupan. Wasiat adalah ruang fleksibel yang memungkinkan kasih sayang mengambil bentuk hukum.
Nah dalam konteks Indonesia, di KHI, sudah ada solusi bagi mereka yang terhalang syariat tentang waris. Namanya, Wasiat wajibah, yang berarti wasiat yang diperuntukkan bagi ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan karena adanya halangan syar'i. Wasiat ini bertujuan untuk memberikan jaminan bahwa pihak-pihak yang terhalang dari warisan tetap mendapatkan sebagian harta peninggalan pewaris.
Misalnya, jika seorang anak angkat tidak memiliki wasiat dari orang tua angkatnya, maka hakim dapat memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat tersebut. Besaran wasiat wajibah ini tidak boleh melebihi sepertiga dari harta peninggalan orang tua angkat. Dalam Pasal 209 KHI dijelaskan;
- Harta peninggalan anak angkat dibagi berdasarkan Pasal 176 sampai dengan Pasal 193 tersebut di atas, sedangkan terhadap orang tua angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta wasiat anak angkatnya.
- Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.
Di tengah masyarakat modern, tafsir ini terasa relevan. Sengketa warisan masih membelah rumah tangga, bahkan ketika rumah itu belum sempat menata luka. Wasiat, jika dilakukan dengan hati yang ma’ruf, bisa menjadi penutup yang hangat: tanda bahwa seseorang tidak hanya meninggalkan harta, tapi juga ketertiban.
Dalam perspektif psikologis, kewajiban berwasiat memberikan ketenangan batin bagi pewasiat. Ia menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan urusan dunia dengan cara yang terbaik, meninggalkan ketidakpastian dan kemungkinan konflik bagi keluarga yang ditinggalkan. Wasiat yang disusun dengan ma’ruf menjadi wasilah untuk menguatkan ikatan keluarga sekaligus mencegah potensi perpecahan.
Pendekatan ini sangat penting secara sosial, karena hukum warisan yang kaku tidak selalu mengakomodasi kebutuhan dan hak kemanusiaan yang lebih luas. Wasiat menjadi instrumen fleksibel untuk memastikan perhatian kepada pihak-pihak yang rawan terabaikan dalam pembagian warisan formal.
Lebih jauh lagi, ayat ini mengajarkan prinsip keadilan yang berwawasan sosial. Wasiat harus memerhatikan keseimbangan kepentingan semua pihak, khususnya kedua orang tua dan kerabat dekat, agar tidak menimbulkan konflik. Ini adalah pesan etis yang relevan hingga kini, di mana sengketa waris masih menjadi sumber konflik keluarga dan sosial yang serius.
Dalam perspektif psikologis, kewajiban berwasiat memberikan ketenangan batin bagi pewasiat. Ia menjadi kesempatan terakhir untuk menyelesaikan urusan dunia dengan cara yang terbaik, meninggalkan ketidakpastian dan kemungkinan konflik bagi keluarga yang ditinggalkan. Wasiat yang disusun dengan ma’ruf menjadi wasilah untuk menguatkan ikatan keluarga sekaligus mencegah potensi perpecahan.
Kewajiban ini juga menunjukkan kedalaman dimensi sosial agama Islam yang mengintegrasikan aspek spiritual dan kemanusiaan. Wasiat bukan sekadar aturan teknis, melainkan juga cerminan tanggung jawab sosial, kesadaran moral, dan penghormatan terhadap nilai kekeluargaan.
Syekh Nawawi Banten, dalam tafsir Marah Labib, ayat 180 dari Surat al-Baqarah bicara soal wasiat; sebuah tindakan akhir, sebuah pernyataan diam yang mencerminkan bagaimana seseorang menimbang keadilan di ambang perpisahan. Wasiat bukan sekadar pembagian harta. Ia adalah keputusan yang lahir ketika ego telah berkurang dan dunia tak lagi bisa dipeluk erat.
Jika kita membayangkan pewarisan harta sebagai sebuah ritus, ia mengingatkan pada konsep Heidegger tentang Sein-zum-Tode—ide bahwa kematian adalah bagian integral dari keberadaan manusia (Dasein). Kematian bukan hanya akhir dari kehidupan, tetapi juga merupakan cakrawala eksistensial yang memandu bagaimana manusia memahami dirinya dan dunia.
Wasiat menjadi perwujudan otentisitas ini: kata-kata terakhir yang tidak sekadar mengatur dunia materi, melainkan menegaskan relasi kemanusiaan. Di sini, kita bisa menengok kembali kritik Ash-Sham dalam Tafsir Marah Labib, yang menyatakan bahwa dahulu orang lebih suka mewasiatkan harta pada orang jauh untuk mencari kehormatan dan pamer status, sedangkan kerabat dekat yang seharusnya menjadi prioritas justru dikesampingkan.
Sebuah ironi yang mengingatkan kita pada Jean Baudrillard dan konsep simulacra, ketika realitas digantikan oleh tanda-tanda kemewahan palsu, dan hubungan otentik dengan manusia lain menjadi terdistorsi. Nietzsche pernah menulis dalam Thus Spoke Zarathustra, bahwa "the greatest events, they are not our loudest but our stillest hours." Barangkali, momen menulis wasiat itulah jam sunyi yang dimaksud: ketika seseorang tak lagi bersuara, tapi diamnya menggetarkan sistem nilai, memaksa kita menimbang kembali siapa yang benar-benar kita sayangi, dan siapa yang sekadar tampil di foto pesta.
Di Barat, wasiat sering dikaitkan dengan hukum dan kepemilikan. Di Timur, ia lebih mirip puisi yang terakhir — sebuah jeda yang memuat harapan, kadang luka, dan kadang juga dendam yang dilestarikan. Namun Islam, dalam firman yang dikutip Syekh Nawawi, membawa bentuk wasiat itu menuju arah yang lain: keadilan. Tidak melampaui sepertiga dari harta si pewasiat, tidak mendahulukan yang kaya, dan tidak melupakan yang dekat.
Keadilan dalam wasiat bukanlah hukum positif semata, melainkan etika mendalam, sebuah virtue, dalam istilah Aristoteles yang lahir dari kesadaran bahwa semua hal fana, dan hanya kebaikan yang bertahan. Karena seperti kata Marcus Aurelius, “It is not death that a man should fear, but he should fear never beginning to live.” Barangkali wasiat adalah hidup terakhir yang sempat kita pilih.
Dan bila benar seperti yang dikatakan Walter Benjamin, bahwa setiap dokumen peradaban juga adalah dokumen barbarisme, maka wasiat adalah upaya kecil untuk menolak itu: bahwa dalam warisan yang tertulis, masih bisa ada belas kasih; bahwa dalam pembagian yang terbatas, masih bisa ada keadilan yang tak terbatas.
Simak penjelasan Syekh Nawawi berikut:
كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ أي فرض عليكم الوصية للوالدين والأولاد كما قاله عبد الرحمن بن زيد أو الرحم غير الوالدين، كما قاله ابن عباس ومجاهد بالعدل بحسب استحقاقهم فلا يفضل الغني ولا يتجاوز الثلث إذا ظهرت على أحدكم أمارات الموت كالمرض المخوف إن ترك مالا
قال الأصم: إنهم كانوا يوصون للأبعدين طلبا للفخر والشرف ويتركون الأقارب في الفقر والمسكنة فأوجب الله تعالى في أول الإسلام الوصية لهؤلاء منعا للقوم عمّا كانوا اعتادوه حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ
Artinya; "Diwajibkan atas kalian, apabila kematian datang kepada salah seorang di antara kalian, jika ia meninggalkan harta yang banyak, (agar) membuat wasiat untuk kedua orang tua dan kerabat dengan cara yang baik." Maksudnya: Diwajibkan atas kalian untuk membuat wasiat bagi kedua orang tua dan anak-anak, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdurrahman bin Zaid; atau bagi kerabat selain kedua orang tua, sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid — yaitu dengan adil, sesuai dengan hak mereka, sehingga tidak memprioritaskan yang kaya dan tidak melampaui sepertiga dari harta, apabila tanda-tanda kematian telah tampak pada salah satu dari kalian, seperti penyakit yang mengkhawatirkan, jika ia meninggalkan harta.
Hatim al-Asham berkata: Dahulu mereka biasa mewasiatkan hartanya kepada orang-orang jauh demi mencari kemegahan dan kehormatan, dan mereka meninggalkan kerabat dekat dalam keadaan miskin dan kekurangan. Maka Allah Ta'ala mewajibkan wasiat kepada para kerabat ini pada masa awal Islam, untuk mencegah orang-orang dari kebiasaan buruk tersebut. (Semua itu adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (Syekh Nawawi Banten, Tafsir Marah Labib, [Beirut: Darul Kutub Ilmiyah, 1417 H], Jilid I, halaman 59).
Dengan demikian, Surat Al-Baqarah ayat 180 menjelaskan bahwa kematian bukan akhir dari tanggung jawab sosial. Wasiat menjadi sarana menebar manfaat dan kasih sayang, bahkan setelah seseorang tiada. Toh, ayat ini mendorong kaum muslimin untuk memberikan wasiat sebelum akhir hayat. Wallahu a'lam.
Ustadz Zainuddin Lubis, Pegiat Kajian Keislaman, tinggal di Parung
Terpopuler
1
Taj Yasin Pimpin Upacara di Pati Gantikan Bupati Sudewo yang Sakit, Singgung Hak Angket DPRD
2
Peringatan HUT Ke-80 Kemerdekaan RI, Ketum PBNU Ajak Bangsa Teguhkan Persatuan
3
Targetkan 45 Ribu Sekolah, Kemendikdasmen Gandeng Mitra Pendidikan Implementasi Pembelajaran Mendalam dan AI
4
Kiai Miftach Jelaskan Anjuran Berserah Diri saat Alami Kesulitan
5
Tali Asih untuk Veteran, Cara LAZISNU Sidoarjo Peduli Pejuang Bangsa
6
Gerakan Wakaf untuk Pendidikan Islam, Langkah Strategis Wujudkan Kemandirian Perguruan Tinggi
Terkini
Lihat Semua