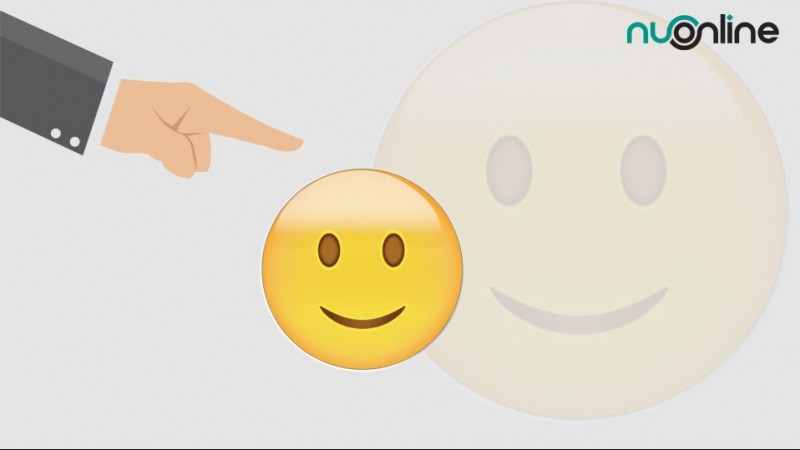Dalam Kitâb al-Imtâ’ wa al-Mu’ânasah, Imam Abu Hayyan al-Tauhidi mencatat sebuah kisah ketika Ibnu Mukaddam dipanggil ‘kafir’ oleh seseorang. Berikut kisahnya:
وقال رجل لابن مكدّم: يا كافر. قال: وجب عليَّ الشُّكرُ، حيث لم يجر ذلك علي لساني، ولم تجب عليَّ إقامةُ الحُجّة فيه، وقد طويتُ قلبي علي جملة أشياء. قال: ما هنّ؟ قال: إن قُلْتَ ألفَ مرّة، ولا أحقِدُ عليك، ولا أشكوك إلي أحد، وإن نجوْتُ من الله عزّ وجلّ بعد هذه الكلمة شفعتُ لك. فتاب الرجل.
Seorang laki-laki berkata kepada Ibnu Mukaddam: “Wahai kafir!”
Ibnu Mukaddam menjawab: “Aku mewajibkan diriku untuk bersyukur, di mana ucapan itu tidak mengalir di atas lidahku, dan aku tidak wajib menyuguhkan hujjah atas ucapan ‘kafir’ itu. Sungguh, aku malah mengalihkan hatiku terhadap beberapa hal (lain).”
Laki-laki itu bertanya: “Apa itu?”
Ibnu Mukaddam menjawab: “Jika pun kau mengatakan (tuduhan itu) seribu kali, aku tidak akan menjawabnya sekalipun. Aku tidak akan menaruh dendam kepadamu, dan tidak akan mengeluhkan (perbuatan)mu pada seorang pun. Jika aku berhasil melakukannya karena Allah ‘Ajja wa Jalla setelah ucapan(mu) ini, aku akan memberimu pertolongan.”
Kemudian laki-laki itu bertobat (setelah mendengar perkataan Ibnu Mukaddam). (Imam Abu Hayyan al-Tauhidi, Kitâb al-Imtâ’ wa al-Mu’ânasah, Beirut: al-Maktabah al-‘Ashriyyah, 2011, h. 247)
****
Untuk sebagian orang, dituduh buruk adalah berkah, seperti yang dilakukan Ibnu Mukaddam. Ia mewajibkan dirinya sendiri untuk bersyukur setelah mendengar panggilan “hai kafir” dari seseorang. Ia tidak marah, menghardik, apalagi menyerangnya secara fisik. Ia pun merasa tak perlu untuk membantahnya. Ia sadar betul, tidak ada manusia yang benar-benar sempurna; tidak ada manusia yang bisa lepas dari perbuatan dosa. Selama mereka hidup, potensi berdosa, dan bersalah tidak kalah besarnya dari potensi berpahala, dan beramal baik.
Ia malah senang dituduh “kafir”, karena ia menerima kemungkinan “kafir” pada dirinya sendiri. Ia menjadikan tuduhan itu sebagai pengingat, ‘apakah ia akan berhasil menghindari kekafiran sampai ia mati?’ Karena itu, ia mengatakan (terjemah bebas): “Jika aku berhasil melakukannya karena Allah ‘ajja wa jalla setelah (tuduhan kafir)mu ini, aku akan memberikan pertolongan kepadamu kelak.”
Ini menunjukkan, ia sendiri takut akan terjerumus ke dalam kekafiran. Sebab, selama nafas masih dikandung badan, kemungkinan akan selalu ada, yang mukmin bisa menjadi kafir, begitu pun sebaliknya, yang kafir bisa menjadi mukmin. Siapa yang tahu. Dan itu semua adalah hak Allah, bukan manusia yang menentukannya.
Dalam kisah di atas, Ibnu Mukaddam malah bersyukur disebut ‘kafir’. Alasan syukurnya ini menarik. Ia mengatakan (terjemah bebas): “Karena tuduhan kafir tidak keluar dari lisanku, dan aku tidak wajib mengemukakan hujjah (argumen) atas tuduhan itu, (maka aku bersyukur).”
Ia bersyukur bahwa kata-kata itu tidak keluar dari lisannya, dan ia pun bersyukur karena tidak diharuskan menyuguhkan argumentasi kuat untuk membenarkan tuduhan ‘kafir’ tersebut. Apalagi menuduh atau memanggil seorang muslim dengan ‘kafir’ mendapat peringatan keras dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam. Rasulullah bersabda (HR. Imam al-Bukhari):
وَمَنْ دَعَا رَجُلًا بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللَّهِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ إِلَّا حَارَ عَلَيْهِ
“Barangsiapa yang memanggil seseorang dengan panggilan ‘kafir’, atau mengatainya ‘musuh Allah’, sedangkan ia tidak seperti itu, maka tuduhan itu akan kembali pada si penuduh.”
Karena itu, Ibnu Mukaddam berjanji akan menolong laki-laki yang menuduhnya itu. Satu sisi, ia ingin membuktikan bahwa dirinya termasuk kelompok “laisa kadzalik” (sedangkan ia tidak seperti itu) dalam hadits di atas. Di sisi lain, ia tak mau orang yang menuduhnya terjerumus.
Di samping itu, ia berterima kasih kepada penuduhnya. Karena tuduhannya itu melecut jiwanya untuk berjuang sepenuh daya, disertai memohon pertolongan dari Allah, agar terhindar dari kekafiran. Sebab, bagi orang-orang semacam Ibnu Mukaddam, tuduhan buruk selalu dirayakan dengan muhasabah (instropeksi diri) sekaligus pengingat diri. Bahkan di titik tertentu, mereka lebih menyukai tuduhan daripada pujian. Karena tuduhan membuat mereka meraba-raba ke dalam diri, melihat kesalahan yang tidak disadari sebelumnya, dan bertobat. Sedangkan pujian, seringkali menjebak manusia dalam kesombongan, riya, ujub dan takabbur.
Dan pada akhirnya, laki-laki itu bertobat setelah mendengar penjelasan Ibnu Mukaddam. Pertanyaannya, seberapa mampu kita mensyukuri tuduhan buruk orang lain kepada kita?
Wallahu a’lam bish-shawwab....
Muhammad Afiq Zahara, alumni PP. Darussa’adah, Bulus, Kritig, Petanahan, Kebumen