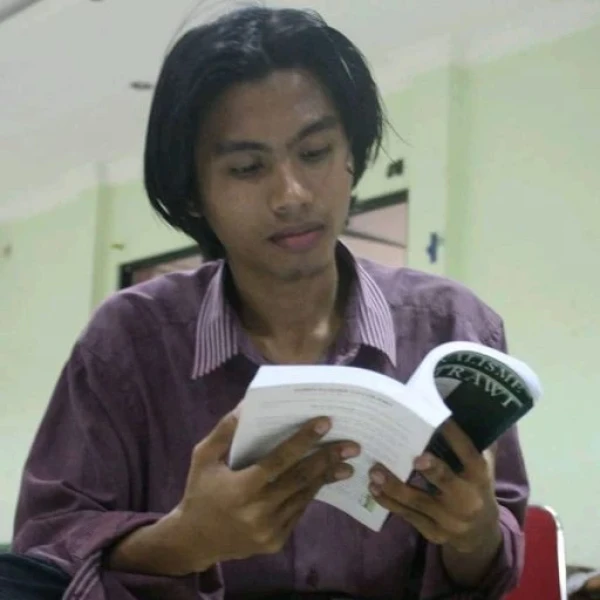Surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan ayat terpanjang dalam Al-Qur'an, yang mengatur prinsip-prinsip transaksi keuangan dan administratif. Ayat ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kewajiban mencatat utang hingga keterlibatan saksi.
Salah satu bagian menarik dari ayat ini adalah penekanan pada perlakuan khusus terhadap pihak yang tidak mampu melaksanakan transaksi secara langsung, yang dalam istilah fiqih disebut dengan al-hajr atau al-mahjur alaih.
Menurut Syekh Zakariya Al-Anshari dalam kitab Fathul Wahhab bi Syarh Minhajuth Thullab, bahwa al-hajr secara bahasa berarti penangguhan atau penahanan. Sedangkan menurut syariat, hajr adalah penangguhan atau pencegahan seseorang dari melakukan tindakan-tindakan transaksi yang berkaitan dengan harta. Beliau mengatakan:
باب الحجرهو لغة المنع وشرعا مِنْ التَّصَرُّفَاتِ الْمَالِيَّةِ
Artinya, "[Bab tentang penangguhan transaksi keuangan] secara bahasa, al-hajru berarti penangguhan/penahanan, sedangkan secara syariat adalah penangguhan dalam melakukan tindakan-tindakan yang berkaitan dengan harta."
“Mengapa seseorang bisa dikenakan hajr?" Dalam syariat, penangguhan transaksi ini diterapkan pada seseorang yang dianggap tidak cakap secara hukum untuk mengelola hartanya, seperti anak kecil, orang gila, atau orang yang boros (mubazir). Hal ini bertujuan untuk melindungi mereka dari kerugian atau penyalahgunaan harta.
Misalnya, seorang anak kecil tidak boleh menjual harta yang bernilai besar karena ia belum memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakannya. Praktik ini semua adalah bentuk kasih sayang Islam agar harta tetap terjaga dan digunakan dengan bijak.
Dalam Al-Qur'an, tepat di surat Al-Baqarah ayat 282, Allah berfirman tentang orang-orang yang ditangguhkan transaksi keuangannya ini:
فَاِنْ كَانَ الَّذِيْ عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيْهًا اَوْ ضَعِيْفًا اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهٗ بِالْعَدْلِۗ
Fa'in kānal-lażī ‘alaihil-ḥaqqu safīhan au ḍa‘īfan au lā yastaṭī‘u ay yumilla huwa falyumlil waliyyuhū bil-‘adl(i)
Artinya, "Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar,"
Tafsir Munir
Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Tafsir Al-Munir menjelaskan bahwa Surah Al-Baqarah ayat 282 memiliki korelasi (munasabah) dengan ayat sebelumnya, yang membahas tentang infak beserta pahalanya, serta larangan riba dan dampak buruknya.
Ayat 282 ini berisi panduan tentang pinjaman yang baik (tanpa bunga) dan tata cara muamalah dalam transaksi non-tunai. Allah SWT menegaskan pentingnya menjaga keamanan transaksi dengan mencatatnya, menghadirkan saksi, serta menyediakan barang jaminan. Tata cara ini mencerminkan nilai kasih sayang dan saling tolong-menolong antar manusia, yang berlawanan dengan praktik riba yang mengandung unsur penganiayaan dan kekasaran.
Lebih jauh, menurut Wahbah Zuhaili, hukum-hukum yang mengatur transaksi tunai dan non-tunai mengandung hikmah berupa kemaslahatan dan keadilan. Allah SWT memerintahkan umat Islam untuk bersedekah, memberikan pinjaman tanpa bunga, dan melarang praktik riba yang merugikan.
Dalam konteks ini, umat Islam juga diajarkan untuk mengelola hartanya secara bijaksana melalui kegiatan perdagangan yang halal. Sebagai manfaatnya, umat terhindar dari kerugian akibat riba dan dapat menjaga harta mereka dari kerusakan atau kehilangan dengan cara yang sesuai dengan syariat.
Selanjutnya, Syekh Wahbah az-Zuhaili dalam Tafsir Al-Munir memberikan penjelasan mengenai ayat 282 dari Surah Al-Baqarah, ayat terpanjang dalam Al-Qur'an yang berisi tentang hukum-hukum muamalah, khususnya dalam transaksi utang-piutang.
Dalam Jilid III, halaman 109, ia menjelaskan bahwa ayat ini memberikan panduan tentang perlindungan terhadap orang-orang yang memiliki kekurangan dalam kewenangan, seperti orang yang lemah akalnya, boros, atau tidak mampu mengelola keuangan dengan baik.
Selain itu, kelompok yang membutuhkan perlindungan juga mencakup anak kecil, orang gila, lansia yang pikun, atau mereka yang secara fisik tidak mampu mendiktekan isi transaksi, misalnya karena kebutaan, bisu, atau kebodohan. Dalam kondisi ini, wali atau wakilnya diberi tanggung jawab untuk mendiktekan isi surat transaksi kepada juru tulis secara jujur dan adil tanpa ada penambahan maupun pengurangan.
Syekh Wahbah Zuhaili juga menerangkan pentingnya kejujuran dan keadilan dalam penyusunan dokumen sebagai bukti transaksi. Wali atau juru bicara harus memastikan bahwa apa yang didiktekan kepada juru tulis sesuai dengan kesepakatan yang sebenarnya.
Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat, termasuk mereka yang tidak mampu menyampaikan sendiri maksudnya. Ketelitian dalam mendokumentasikan transaksi merupakan bagian dari kehati-hatian syariat Islam agar tidak ada pihak yang dirugikan di masa depan, baik karena kesalahan pencatatan maupun karena celah dalam hukum yang dimanfaatkan secara tidak adil.
Kemudian, Syekh Wahbah Zuhaili menjelaskan bahwa Allah SWT memberikan petunjuk berupa anjuran kuat untuk memperkuat transaksi yang dilakukan dengan menghadirkan saksi. Dalam hal ini, transaksi harus disaksikan oleh dua orang laki-laki atau, jika tidak ada, dapat digantikan oleh satu laki-laki dan dua perempuan.
Ketentuan ini mencerminkan perhatian syariat terhadap keabsahan dan kepercayaan dalam setiap transaksi, terutama yang dilakukan secara tidak tunai. Kehadiran saksi bukan hanya bertujuan untuk memastikan keadilan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menghindari sengketa di masa mendatang. Simak penjelasan Syekh Zuhaili berikut ini;
ثم أوضح تعالى أحوال ناقصي الأهلية، فإن كان المدين (الذي عليه الحق) سفيها أي مبذرا في ماله ناقص العقل والتدبير، أو ضعيفا بأن كان صبيا أو مجنونا أو جاهلا أو هرما لم تساعده قواه العقلية على ضبط الأمور، أو عاجزا عن الإملاء لكونه جاهلا أو ألكن أو أخرس أو معتقل اللسان، أو أعمى، فعلى وليه الذي يتولى أموره من قيّم أو وكيل أو مترجم أن يملي الحق على الكاتب بالعدل والإنصاف، بلا زيادة ولا نقص. ثم جاء دور الإثبات، فأرشد تعالى على سبيل الندب لضبط الوقائع وحفظ الأموال إلى الشهادة على المداينة، ونصاب الشهادة: رجلان أو رجل وامرأتان
Artinya; Kemudian Allah Ta'ala menjelaskan keadaan orang-orang yang kurang cakap dalam bertindak. Apabila si berutang (yang memikul tanggung jawab atas hak) adalah seseorang yang safih; boros dalam mengelola hartanya, kurang akal, dan tidak pandai mengatur keuangan, atau lemah seperti anak kecil, orang gila, orang yang bodoh, atau orang tua yang lemah akal karena usia lanjut sehingga tidak mampu mengendalikan urusannya dengan baik, atau tidak mampu untuk menyampaikan (isi perjanjian) karena tidak tahu, gagap, bisu, tidak lancar berbicara, atau buta, maka walinya yang mengurus urusannya, seperti seorang pengelola, wakil, atau penerjemah, bertanggung jawab untuk menyampaikan kebenaran kepada penulis dengan adil dan jujur, tanpa menambah atau mengurangi.
Setelah itu, giliran pembuktian dijelaskan. Allah Ta'ala memberi petunjuk, sebagai anjuran, untuk mencatat dan menjaga harta dengan baik melalui kesaksian dalam transaksi utang-piutang. Jumlah saksi adalah dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan (Tafsir Munir, [Darul Fikr Muashir, 1991 M], Jilid III, hlm, 109).
Tafsir Thabari
Imam Thabari dalam kitab Tafsir Jami'ul Bayan menerangkan tentang makna kata safih dalam Surah Al-Baqarah ayat 282. Kata safih, dalam konteks ini mencakup setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk memahami dengan benar apa yang harus didiktekan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, safih mengacu pada ketidakcakapan seseorang dalam memahami dan mengelola kewajibannya dengan tepat.
Menurut Imam Thabari makna lahiriah ayat ini lebih cenderung merujuk kepada setiap orang yang tidak dapat membedakan antara kebenaran dan kesalahan dalam hal yang harus didiktekan. Hal ini menunjukkan bahwa "ketidakcakapan" bukan hanya berkaitan dengan usia atau jenis kelamin, tetapi juga mencakup kondisi intelektual atau kemampuan seseorang dalam memahami perkara yang sedang dibicarakan.
Oleh karena itu, safih dalam ayat ini tidak hanya mengacu pada seseorang yang bodoh secara umum, tetapi lebih kepada ketidakmampuan dalam konteks spesifik pengelolaan dan penulisan hutang. Nah, tentu saja, penafsiran ini menunjukkan betapa pentingnya memperhatikan kompetensi seseorang dalam hal yang berkaitan dengan tanggung jawab keuangan, khususnya dalam urusan hutang-piutang.
Imam Thabari dengan bijak menggarisbawahi perlunya keterlibatan pihak yang lebih cakap untuk membantu mereka yang dianggap safih agar tercipta keadilan dan kejelasan dalam pencatatan perjanjian. Ini mencerminkan kepekaan syariat Islam terhadap kebutuhan manusia dalam menjaga hak dan kewajiban dengan adil. Simak penjelasan Imam Thabari berikut;
وقد يدخل في قوله:"فإن كان الذي عليه الحق سفيهًا"، كل جاهل بصواب ما يُملّ من خطئه، من صغير وكبير، وذكر وأنثى. غير أن الذي هو أولى بظاهر الآية أن يكون مرادًا بها: كلُّ جاهل بموضع خطأ ما يملّ وصوابه:
Artinya; "Dan termasuk dalam firman-Nya: 'Maka jika orang yang berhutang itu bodoh (tidak cakap)', mencakup setiap orang yang tidak mengetahui dengan benar apa yang harus didiktekan, baik itu anak kecil maupun orang dewasa, laki-laki maupun perempuan. Namun, yang lebih sesuai dengan makna lahiriah ayat ini adalah bahwa yang dimaksud adalah setiap orang yang tidak mengetahui letak kesalahan dan kebenaran apa yang harus didiktekan." (Tafsir Thabari, [Makkah: Darul Tarbiyah wa Turats, tt], jilid VI, hlm, 57).
Sementara itu, kata "dhaif" dalam ayat 282 ini maksudnya adalah seseorang yang sudah lanjut usia tetapi memiliki keterbatasan akal, atau dalam istilah lain, seorang tua yang bodoh atau idiot (ahmaq). Penafsiran ini menunjukkan bahwa kelemahan yang dimaksud bukan hanya fisik, tetapi juga mencakup ketidakmampuan seseorang dalam memahami atau mengambil keputusan yang bijak terkait urusan dirinya maupun hartanya.
Selanjutnya, Imam Thabari menjelaskan frasa "اَوْ لَا يَسْتَطِيْعُ اَنْ يُّمِلَّ هُوَ" (atau orang yang tidak mampu mendiktekan sendiri). Pada Jilid VI, halaman 59, ayat ini, kata Imam Thabari merujuk pada seseorang yang sehat akalnya dan memiliki kendali penuh atas hartanya, tetapi mengalami hambatan sehingga tidak bisa mendiktekan pernyataannya. Hambatan tersebut bisa berupa gangguan fisik, seperti bisu, atau kendala situasional, misalnya ketidakhadirannya di lokasi penulisan dokumen.
Pada akhirnya, ayat ini menggambarkan perhatian khusus Al-Qur'an terhadap kondisi seseorang dalam transaksi dan pencatatan utang. Selain itu, lewat ayat ini, Imam Thabari menjelaskan bahwa syariat Islam sangat memperhatikan kebutuhan setiap orang, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan tertentu.
وأن"الضعيفَ" هو الكبير الأحمق. لأن ذلك إن كان كما قال، يوجب أن يكون قوله:"أو لا يستطيعُ أن يملّ هو" هو، العاجز من الرجال العقلاء الجائزي الأمر في أموالهم وأنفسهم عن الإملال، إما لعلة بلسانه من خرس أو غيره من العلل، وإما لغيبته عن موضع الكتاب.
Artinya; "Dan (maksud) 'lemah' adalah orang tua yang bodoh [idiot]. Karena jika hal itu seperti yang dia katakan, maka hal itu menunjukkan bahwa firman-Nya: 'atau orang yang tidak mampu untuk mendiktekan (sendiri)' merujuk pada orang laki-laki yang tidak berdaya namun berakal, yang memiliki kewenangan atas harta dan dirinya sendiri tetapi tidak mampu mendiktekan, baik karena suatu sebab di lisannya seperti bisu atau sebab lainnya, ataupun karena ia tidak berada di tempat penulisan (dokumen tersebut)." (hlm, 59).
Marah Labib
Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Marah Labib menjelaskan secara rinci tentang ayat 282 Surat Al-Baqarah , bahwa ayat ini menyebutkan tiga kondisi yang menyebabkan seseorang perlu pendampingan dalam transaksi:
Pertama, Safih (idiot/lemah akal): Orang yang memiliki keterbatasan dalam memahami konsekuensi transaksi, seperti anak-anak atau orang dengan gangguan mental.
Kedua, Dha'if (lemah): Orang yang memiliki kelemahan fisik atau sosial yang membuatnya tidak mampu terlibat aktif, seperti lansia atau orang yang sakit parah.
ketiga, Lā yastaṭī‘u an yumilla (tidak mampu menyatakan): Orang yang mengalami hambatan bahasa, keterbatasan kemampuan komunikasi, atau situasi khusus lainnya.
Dalam kondisi tersebut, kata Syekh Nawawi, menjelaskan bahwa orang-orang seperti ini perlu didampingi oleh wali yang bertugas memberikan pengakuan atau keterangan kepada penulis. Wali ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban individu tersebut tetap terlindungi dan dapat dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi. Simak penjelasan berikut:
أي فإن كان المديون ناقص العقل مبذرا أو عاجزا عن سماع الألفاظ للكاتب لصغر أو كبر مضعف للعقل، أو لا يحسن الإسماع بنفسه على الكاتب- لخرس أو جهل باللغة أو بما عليه- فليقر على الكاتب ولي كل واحد من هؤلاء الثلاثة
Artinya, "Yaitu, jika orang yang berutang memiliki kekurangan akal, pemboros, atau tidak mampu mendengar kata-kata dari penulis karena usia yang terlalu muda atau tua yang melemahkan akal, atau tidak bisa menyampaikan suara kepada penulis—karena bisu atau ketidaktahuan bahasa atau apa yang menjadi kewajibannya—maka ia harus memberikan pengakuan kepada penulis, dan setiap orang dari ketiga pihak tersebut."
Dengan demikian, surat Al-Baqarah ayat 282 merupakan contoh nyata peran syariat Islam mengatur kehidupan dengan sangat rinci dan penuh keadilan. Orang-orang yang ditangguhkan transaksi, seperti anak-anak, orang sakit, atau orang dengan keterbatasan akal, tetap mendapatkan hak mereka melalui peran wali.
Pada akhirnya, dengan prinsip ini, Islam memastikan bahwa setiap orang dihargai dan dilindungi, tanpa terkecuali. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting bagi hukum syariat dan perdata dalam melindungi hak asasi manusia. Wallahu a'lam.
Ustadz Zainuddin Lubis, Pegiat kajian Islam Tinggal di Parung